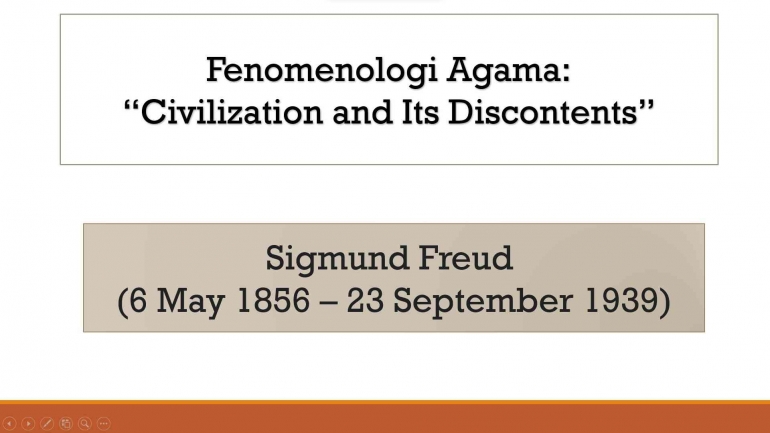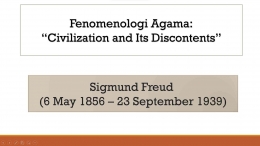Sekularisme Dan Fenomenologi Agama
Di Wina hampir 90 tahun yang lalu, kritik inovatif Sigmund Freud terhadap peradaban modern muncul. Civilization and Its Discontents, sebagaimana judulnya dalam terjemahan bahasa Inggris, menjadi salah satu buku penting abad ke-20 dan memang telah secara signifikan membentuk pandangan dunia modern dan pemahaman diri. Ketidakpuasan dalam bentuk jamak dibicarakan di sini dapat dengan mudah direduksi menjadi satu temuan: manusia modern tidak bahagia.
Buku ini ditulis pada tahun 1929 dan pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman pada tahun 1930 dengan judul Das Unbehagen in der Kultur ("Kegelisahan dalam Peradaban"). Menjelajahi apa yang dilihat Freud sebagai pertentangan penting antara hasrat terhadap individualitas dan ekspektasi masyarakat, buku ini dianggap sebagai salah satu karya Freud yang paling penting dan banyak dibaca, dan digambarkan pada tahun 1989 oleh sejarawan Peter Gay sebagai salah satu karya paling penting dan paling banyak dibaca. buku-buku yang berpengaruh dan dipelajari di bidang psikologi modern.
Dalam Civilization and Its Discontents , Freud berteori tentang ketegangan mendasar antara peradaban dan individu; teorinya didasarkan pada gagasan bahwa manusia memiliki naluri karakteristik tertentu yang tidak dapat diubah. Ketegangan utama berasal dari upaya individu untuk menemukan kebebasan naluri, dan tuntutan sebaliknya dari peradaban akan konformitas dan penindasan terhadap naluri. Freud menyatakan bahwa ketika situasi apa pun yang diinginkan berdasarkan prinsip kesenangan berkepanjangan, hal itu menimbulkan perasaan dendam ringan karena bertentangan dengan prinsip realitas .
Naluri primitive misalnya, hasrat untuk membunuh dan hasrat yang tak terpuaskan akan kepuasan seksual berbahaya bagi kesejahteraan kolektif komunitas manusia. Undang-undang yang melarang kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan perzinahan dikembangkan sepanjang sejarah sebagai akibat dari pengakuan atas kerugian yang ditimbulkannya, dan penerapan hukuman berat jika peraturan tersebut dilanggar. Proses ini, menurut Freud, adalah kualitas yang melekat pada peradaban yang menimbulkan perasaan tidak puas yang terus-menerus di antara individu, yang tidak membenarkan baik individu maupun peradaban tersebut.
Ketidakbahagiaan adalah konsekuensi dari kehidupan manusia yang berada dalam batasan masyarakat dan penolakan paksa terhadap hasrat-hasrat instingtualnya. Judul asli Jerman Das Unbehagen in der Kultur, yang secara harafiah diterjemahkan sebagai Kegelisahan dalam budaya, yaitu ketidaknyamanan dan ketidak-ramahan hidup dalam sangkar besi (Weber) yang membatasi peradaban, cukup menyampaikan isu inti dari ini memaksakan ketidakbahagiaan.
Meskipun perjuangan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan individu telah menjadi tugas utama atau lebih tepatnya obsesi banyak orang di dunia kontemporer, buku Freud masih mempertahankan validitas diagnostiknya hingga saat ini. Slogan terkenal Neil Postman Menghibur Diri Sampai Mati telah memicu perdebatan yang menawarkan variasi pada topik yang sama: apakah peradaban Barat modern, teknologi, media, dll., membantu kita memfasilitasi dan memperkaya kehidupan kita hingga pada titik di mana kita menjadi lebih bahagia;
Namun, berkembangnya bentuk kehidupan Barat ini entah itu sebuah cita-cita yang dicita-citakan atau sebagai gambaran musuh yang paling dibenci menimbulkan banyak kendala, kecanduan, dan ketidakpuasan baru, dengan globalisasi yang melambangkan kecenderungan ambigu ini. Saat ini, tidak diragukan lagi, karakternya yang seperti pusaran air, ketidakadilan, ketidakamanan dan ancaman yang ditimbulkannya, tampak mengguncang kebosanan dan depresi yang sangat dirasakan yang menjadi atribut struktural dari imajinasi sosial individualis modern kita. Setelah perkembangan ini, gagasan-gagasan tentang keadilan kosmopolitan, keramahtamahan antaragama, pasca-pertumbuhan, dan instrumen-instrumen empati jarak jauh lainnya baru-baru ini dihidupkan kembali atau bahkan diciptakan kembali, sehingga menekankan perlunya memediasi dampak-dampak sampingan yang ambigu dari kebijakan tersebut. pencapaian peradaban terkini umat manusia.
Dialektika teknologi yang luar biasa dan kekerasan neoliberalisme yang dibumbui secara sistematis di era globalisasi akhir jelas membuktikan ambiguitas mendasar ini. Semakin jelas upaya mengejar kebahagiaan individu terkait dengan kebosanan struktural dan ketidakpedulian masyarakat yang terikat secara sempurna namun tidak berfungsi secara sosial. Namun hal ini dengan jelas mengungkapkan pemikir terjebak dalam mimpi nihilis yang akhirnya akan berakhir sesuatu yang tampaknya dijanjikan oleh visi ilmiah kontemporer kita tentang peningkatan kualitas manusia, pasca-humanisme, dan tata kelola algoritmik atau mungkin, sebaiknya dikatakan, pertanda.
Namun ambiguitas tersebut muncul bukan hanya sebagai konsekuensi dari proses globalisasi yang beragam dan seringkali bersifat spektral. Pandangan awal Freud mengenai proses peradaban dan sosialitas negatif yang terlalu gamblang dari kemajuannya sudah mengandung tanda ambiguitas yang melekat. Apa yang memaksa manusia, menurut Freud, untuk melawan dan menekan naluri terdalamnya sehingga menjadi (kurang lebih) tidak bahagia pada saat yang sama dianggap sebagai langkah penting untuk menjinakkan manusia binatang. di dalam diri kita, yaitu, semacam pengorbanan diperlukan untuk menjamin kehidupan yang baik dalam komunitas manusia. Kedamaian lahiriah menyebabkan perselisihan batin yang permanen, merupakan gambaran singkat dari proses ini.
Jika ditransformasikan ke tingkat masyarakat, rumusan ini melambangkan posisi intelektual yang tidak sekadar menegaskan kembali kontraktualisme sosial Hobbes, namun secara sempurna mencerminkan dampak normatif yang ditimbulkannya bagi individu. Namun ini belum semuanya. Dengan fokusnya pada ketidakpuasan yang bertahan lama dalam proses ini, dengan pendewaan manusia yang menonjol dalam hal ini, hal ini menandakan gerakan selanjutnya: ini adalah sengatan dari ketidakbahagiaan Tuhan prostetik yang akan membatalkan degradasi sentimen keagamaan karena pada potensi kecenderungan mereka terhadap irasionalitas, fanatisme, dan kekerasan hanya pada ranah pribadi, sesuatu yang sudah secara eksplisit dikemukakan oleh Hobbes.
Namun justru dalam konteks inilah baru-baru ini agama kembali berperan dengan semangat yang luar biasa. Dalam hal ini, kita mungkin ingat Freud menganggap agama sebagai alat tertua dan mungkin paling kuat untuk mengatasi kecenderungan proses peradaban yang tak henti-hentinya dan tidak dapat diprediksi. Namun Freud bukanlah orang pertama atau satu-satunya yang menggambarkan agama sebagai bentuk utama pembentukan budaya dunia kehidupan manusia.
Hal ini tentu saja merupakan wawasan yang, misalnya, merupakan bagian integral dari teori sosial Perancis klasik dan cara para pendukungnya mengaitkan integrasi ikatan sosial dengan penggunaan kerapuhan afektif umat manusia, sehingga menjamin terjadinya transformasi yang berbahaya., pengaruh kebinatangan ( perturbatio animi) ke dalam orkestrasi sosial yang dapat ditempa dari sentimen moral kita yang benar-benar manusiawi. Dalam konteks ini, signifikansi penilaian Freud berasal dari wawasannya terhadap potensi reflektif dan ekspresif sistem pengetahuan keagamaan. Seperti yang ditunjukkan dengan paling tegas dalam buku terakhirnya, Musa dan Monoteisme, agama memang berfungsi tidak hanya sebagai pemicu, namun merupakan ekspresi kritis dari perkembangan sejarah tersebut.
Monoteisme, dalam pengertian ini, karena potensi abstraksinya yang luar biasa dan pencapaian intelektual yang lebih besar, tidak diragukan lagi merupakan bukti adanya kemajuan umat manusia walaupun perkembangan ini mungkin bersifat ambivalen. Namun, pandangan mengenai agama sebagai pembentuk sejarah umat manusia tidak mengarah pada satu arah, melainkan bersifat ambigu. Menurut keyakinan Freud, posisi agama dalam dunia kontemporer dan masa depannya sangat dipertanyakan, bahkan bisa diabaikan. Dia memang memiliki preferensi yang jelas terhadap solusi yang lebih rasional sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan hangat dunia yang dia ketahui dibandingkan jaket lurus agama lama. Namun pertanyaannya masih tetap ada: mengapa pendekatan yang dirasionalisasikan ini ternyata menghasilkan ketidakpuasan yang sama banyaknya dengan pandangan dunia mitologis yang lebih tua;
Meskipun Freud bersikeras pada preferensi ini, dia tetap tidak mau membuang agama secara keseluruhan ke ranah mitologis. Sejalan dengan penilaian ulangnya secara umum terhadap kondisi manusia, ia justru menunjukkan kepekaan yang besar terhadap kembalinya orang-orang yang tertindas yang selalu mungkin terjadi, yaitu hal-hal yang luar biasa, atau tidak sehari-hari, sebagai sesuatu yang tertanam dalam tatanan kehidupan sosial. Pengecualian yang terlalu rasionalis terhadap agama akan menuntut kritik terhadap nalar sebagai sesuatu yang bersifat neo-mitos.
Persis di persimpangan inilah volume kita dimulai dan, dalam beberapa hal, berlanjut sepanjang alur pertanyaan yang sama seperti Freud. Namun hal ini muncul dari sudut pandang yang berbeda, bahkan mungkin berlawanan. Idenya sama sekali bukan sekedar memulihkan hal-hal yang sakral, untuk membangun kembali, memperoleh kembali atau mengambil kembali (intuisi asli atau potensi normatif) agama demi (demi menebus) dunia Barat yang sekuler. Dalam pandangan kami, sikap seperti itu masih merupakan gagasan kaum religius dan kaum sekuler adalah dua wilayah yang jelas-jelas dibatasi batasnya dan penalaran yang lebih luas pada akhirnya akan mampu mengasimilasi potensi kognitif agama yang belum terpikirkan dan secara instrumental mengintegrasikan irasionalitas, ketidakjelasan, ketidakjelasan, dll. ke dalam satu pandangan dunia yang terpadu dan objektif.
Untuk menentang visi integrasionis (dan hegemonik jika bukan imperialis), tugas kita bukanlah untuk mengeksplorasi tantangan ekstrinsik seperti apa yang ditimbulkan oleh kembalinya ini ke apa yang disebut pandangan dunia sekuler; seolah-olah sebuah retorika baru tentang hal-hal sakral sekadar menuangkan anggur lama ke dalam kantong baru, sehingga mengingatkan kita akan upaya kita yang masih belum selesai untuk membentuk kembali nalar di era hermeneutik yang penuh dengan perbedaan dan keberagaman. Menindaklanjuti hipotesis Derrida kedua sumber iman dan pengetahuan bersinggungan secara konstitutif lebih berhipotesis kembalinya ini kembalinya ekspresi keagamaan yang benar-benar baru dan belum pernah terjadi sebelumnya---secara intrinsik terkait dengan krisis sekularisme dan alasan sekuler.
Agama, yang dipandang demikian, tidak hanya kembali sebagai yang tertindas, sebagai yang lain dari nalar, sebagai inti yang buram atau misteri. Sebaliknya, agama justru tampil dalam transformasi dan penyebarannya ke dalam masyarakat modern yang secara kreatif menerapkan motif, simbolisme, dan semantik keagamaan. Dan lebih jauh lagi, bahkan praktik-praktik keagamaan yang asli pun mengadopsi dan menggabungkan cara-cara yang dianggap mengambil alih rasionalisme tele-techno-saintifik, yang pada akhirnya mencapai tingkat pemulihan dalam medium kinerja dan pengesahan dari yang transenden, suci, dll., suplemen asli agama, menggunakan istilah Derrida.
Baru-baru ini, situasi yang penuh teka-teki ini tercermin dalam istilah ambivalensi atau dialektika sekularisasi. Seperti yang ditunjukkan oleh berbagai fenomena membingungkan yang termasuk dalam judul ini, sekuler atau akal budi yang tidak terlibat telah merasa yakin akan sifat-sifatnya yang membebaskan, menyelamatkan dan hampir mendewakan manusia. Dan meskipun masih banyak diperdebatkan apakah kembalinya agama merupakan fakta sosiologis, artefak filosofis, atau khayalan teologis, bukti sejarah yang membingungkan ini pasti menarik perhatian kita dengan sangat tajam: sekularisme bukanlah solusi yang tepat. solusi terhadap permasalahan umat manusia modern, seperti yang diharapkan banyak orang, termasuk mungkin Freud. Berkuasanya nalar sekuler justru membuat kita mengalami ketidakpuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam bentuk jamak. Meskipun banyak masyarakat telah memperoleh keuntungan besar dari orientasi regulatif menuju emansipasi kolektif dan otonomi pribadi, namun terdapat kelemahan yang sangat besar.
Hal ini terutama berlaku pada pusaran globalisasi yang muncul setelah perkembangan ini. Berbagai fenomena meresahkan terlintas dalam pikiran: kebangkitan tribalisme dan politik identitas; kembalinya kekerasan kolektif ekstrem yang tidak terduga dan penggunaan kekejaman secara politis; sebuah perang baru terhadap masyarakat miskin dalam kondisi ekonomi neokolonial; pergerakan penerbangan dan migrasi yang berkaitan erat yang baru-baru ini mempengaruhi Dunia lama; meningkatnya kelas-kelas berbahaya di negara-negara pasca-industri; eksploitasi sumber daya alam yang berbahaya dan penciptaan lahan terlantar yang menandakan zaman antroposen; keruntuhan afektif seluruh masyarakat yang disatukan hanya oleh berhala-berhala nalar instrumental dan kemanjuran neoliberal; atau kemiskinan spiritual dan tunawisma transendental yang disebabkan oleh ego-start-up yang sudah habis.
Semua ini, selain beberapa perkembangan dan masalah terkini, membuktikan meluasnya perasaan tidak nyaman yang menghantui situasi masa kini, pemahaman diri, dan imajinasi sosial yang semakin rapuh. Sebagaimana diperlihatkan oleh perkembangan-perkembangan yang membingungkan ini, kekecewaan dunia yang sering disebut ( yang mungkin dipahami sebagai langkah paling penting dalam sejarah pemberdayaan diri rasional manusia dan penaklukan teknologi yang terkait dengan dunia) telah mengakibatkan, seperti yang dikatakan Jean-Luc Nancy, dalam penciptaan tanah tandus yang penuh perasaan. Di tanah tandus ini, mengutip Nietzsche, perburuan besar-besaran terhadap kemungkinan-kemungkinan yang masih belum habis dalam kehidupan dilakukan berulang kali.
Dengan demikian, perburuan besar berkontribusi pada pembentukan masyarakat spektakuler tampaknya ditakdirkan untuk mengejar maknanya yang semakin memudar dalam perkembangan gambar dan pertunjukan yang tiada henti. Menurut Michel Henry, dinamika ini mencerminkan pola dasar globalisasi dan menghasilkan pemerintahan sistemik dari barbarisme batin yang benar-benar meniadakan kehidupan dan menurunkan makna kehidupan ke dalam ekspresi kegembiraannya. Dengan berubahnya kategori-kategori terkait kemajuan, popularitas, dan komodifikasi menjadi nilai-nilai sosial yang sakral, upaya tanpa henti untuk mencapai proyek yang disebut modernitas mencapai puncaknya, mungkin titik transisinya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H