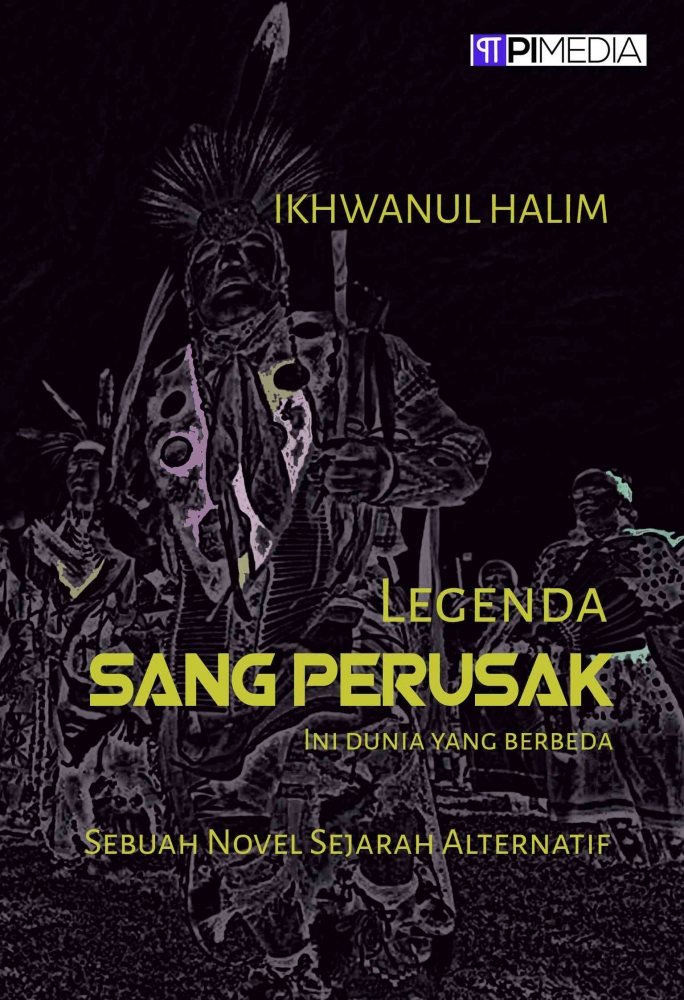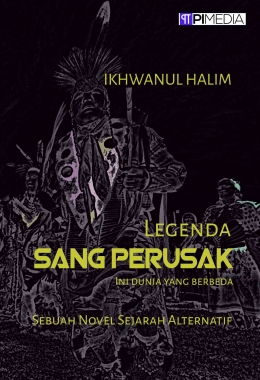"Wah, apa yang terjadi, Pak?" Bagas tergagap sebelum otaknya bisa mengendalikan mulutnya.
Masih merasakan darah dan tanah di lidahnya, Awang melirik pakaian dokternya yang kotor, dan tidak bisa menjernihkan pikirannya untuk dapat menjawab pertanyaan bocah itu selain, "Berapa banyak utangku padamu, Nak?"
"Ehm... satu dinar lima dirham. Masih seperti bulan lalu, Pak."
"Oh ya, aku ingat sekarang." kata Awang, melihat ekspresi kebingungan di wajah anak laki-laki itu.
Awang merogoh sakunya dan secara serampangan mengeluarkan tiga logam dinar. "Ini, ambil kembaliannya untukmu," dia berkata sambil menutup pintu.
Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengobrol dengan tukang koran. Dia baru saja masuk ke rumah beberapa saat yang lalu dan ketika dia bertemu Kuntum, pertengkaran segera dimulai.
"Terima kasih Pak."
Bagas berbalik. Ada nada kecewa dalam suaranya karena dia gagal mengatasi mulutnya yang usil, karena belum cukup umur. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Bagas menaiki ke sepedanya dan menuju rumah.
Awang kembali ke dapur, tempat Kuntum duduk sambil menangis. Mungkin banyak kesedihan dalam diri Bagas seperti halnya kemarahan dalam diri Awang, tapi setidaknya dia berhasil mengendalikan perasaannya di depan bocah itu. Bagas akan segera mengatasi kekecewaannya, tetapi kemarahan Awang akan bertahan lebih lama. Hanya Kuntum yang akan meneerima kemarahannya jika dia bisa menahannya.
"Siapa itu?" Kuntum mebentak saat Awang memasuki dapur. "Bagas, tukang koran, dan aku senang aku yang membukakan pintu, bukan kamu," Awang balas membentak sarkastis.
"Bagaimana kamu bisa bersikap baik pada anak kecil brengsek itu? Aku tidak melihat gunanya."
"Dia anak yang baik, Kuntum, dan jika kamu tidak menyukainya, itu masalahmu. Tapi seharusnya kamu memberikan anak itu kesempatan. Anak laki-laki yatim itu ingin menjadi dokter suatu hari nanti, dan dia meminta nasihatku sesekali."
Dari balik air matanya, Kuntum menatap pria pria yang berantakan dan acak-acakan di depannya. Nada suaranya dingin, tidak lagi bergaung sengau dengan tangisnya.
"Kamu menyukai anak itu karena dia membangun egomu, Awang, dan kamu tahu itu. Dia mungkin tidak ingin menjadi dokter ketika saatnya kelak tiba. Kenapa kamu tidak turun saja dari kudamu, dan gunakan semangatmu untuk hal yang berguna?"
Kata-kata Kuntum sudah terlalu berlebihan untuk Awang. Mereka sekarang bahkan bertengkar karena tukang koran. Apa guanya pernikahan mereka?
Mereka selalu berdebat tentang hal-hal bodoh, tapi tidak pernah sebodoh ini.
"Tak usah bawa-bawa anak itu, Sayang! Ini tentang kamu dan Gumarang. Jangan coba-coba melenceng dari topik!" pekik Awang dengan meluap-luap, lebih dari yang dia inginkan.
"Aku tidak mengubah topik pembicaraan karena tidak ada yang perlu diubah. Aku sudah memberitahumu ribuan kali bahwa tidak ada apa-apa antara Gumarang dan aku. Mengapa kamu tidak bisa melihat itu? Aku tidak pernah punya rasa apa pun untuk laki-laki itu, dan aku tidak melihat bahwa aku akan pernah punya rasa untuknya, kecuali kalau kamu terus mendorongku dengan fantasi paranoidmu ini."
Kata 'kecuali' membuat kesabaran Awang habis, dan tanpa berpikir dua kali, dia menyerbu keluar dari pintu belakang ke garasi. Semburan adrenalin yang meledak memenuhi emosinya, kelelahan setelah serangan epilepsi yang hampir tidak memungkinkannya untuk pulang beberapa saat yang lalu lenyap ditelan badai emosi.
Kerikil berhamburan saat Awang mundur di jalan keluar garasi, dan kemudian Mercedes Benz SLS-nya terbang ke jalan raya bahkan sebelum dia menyadari bahwa dia berada di dalam mobil. Dan begitu pikiran sehatnya kembali, meskipun ketegangan dan kemarahan masih menguasai benaknya, Awang memutar mobil dan kembali ke rumah.
Dia terlalu marah untuk berbicara dengan Kuntum, tapi mustahil dia berpacu di jalan kota seperti ini.
Aku harus tenang.
BERSAMBUNG
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H