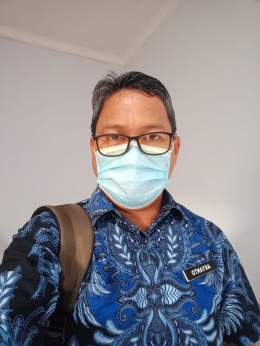Jika Pandemi COVID-19 ini terjadi pada 2030 nanti, kita mungkin tidak hanya cemas dan khawatir. Teror dan takut akan menghiasi kehidupan manusia pada saat itu. Para pakar memprediksikan sepuluh tahun dari sekarang Bumi sudah dalam kondisi 'absolutely crisis'. Menghadirkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Dalam kondisi 'absolutely crisis', dunia dalam keputusasaan yang luar biasa karena kelaparan, kepanasan, konflik berkepanjangan dan kelangkaan sumber daya alam. Bumi telah sangat berbeda dan bukan lagi tempat yang layak ditinggali. Suhu bumi yang sedemikian panasnya akibat global warming melelehkan bongkahan es Arktik lebih cepat. Akibatnya paras air laut naik dan menenggelamkan pulau-pulau dan banyak kota besar dunia.
Kemajuan teknologi yang berkembang pesat menuju revolusi industri teknologi terkini, era 6.0, tidak bisa memecahkan semua masalah. Inovasi Artificial Intelligence, Robotic, Biomimicry dan berbagai inovasi teknologi lainnya hanya bisa memuaskan kebutuhan manusia namun belum bisa memecahkan permasalahan kehidupan secara menyeluruh.
Kegagapan global menghadapi Pandemi COVID-19 adalah salah satu bentuk tidak berdayanya kemampuan teknologi yang dimiliki manusia saat ini. Apapun alasannya, apakah teori 'konspirasi' atau karena siklus tahunan pandaemi, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menghadirkan vaksin penangkalnya secepat outbreak Virus Sars Cov-2. Kegagapan ini antara lain karena penerapannya masih parsial dan hanya pada skala tertentu.
Persoalan lainnya adalah kesadaran terhadap permasalahan bumi masih bersifat retorika dan paradoksal. Pertemuan-pertemuan internasional yang membahas perubahan iklim justeru diwarnai pemborosan energy, dari emisi gas CO2 keluar dari pesawat-pesawat jet yang membawa Kepala Negara menghadiri konferensi perubahan iklim. Maka jika hari ini, kesadaran manusia terhadap bumi tidak kunjung berubah maka persoalannya bukan lagi tentang kecemasan terhadap Pandemi tapi ketakutan hilangnya kehidupan dan peradaban bangsa-bangsa bumi untuk selama-lamanya.

Kesadaran kita terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi sangat penting. Bumi memiliki sumberdaya yang terbatas. Alih-alih menahan hasrat di tengah kelangkaan sumberdaya, keinginan manusia justeru melewati batas yang seharusnya, bahkan sering bermuara pada kompetisi dan konflik penguasaan sumberdaya.
Ada juga kesepakatan. Pada KTT Bumi 1992, para pemimpin dunia sepakat mendukung isu pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Agenda 21. Pada 2012, Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal Rio+20 mengusulkan Global Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai panduan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pasca MDGs 2015. SDGs melampaui tujuan penyusunan MDGs dan menyediakan visi yang komprehensif dan kerangka kerja bagi evolusi semua negara di tahun-tahun mendatang. SDGs adalah kesepakatan global yang segera membumi karena urgensi implementasi pembangunan berkelanjutan di seluruh negara.
Namun fakta berbicara lain. Menjelang Paris Agreement 2015 laju emisi Karbon belum bisa dikendalikan sesuai perjanjian. Pada kenyataannya negara maju seperti bermain pat gulipat dalam pengendalian emisi karbon. Banyak negara maju yang meratifikasi Kyoto Protocol namun tidak terbukti dalam kebijakan domestiknya. Industri berbahan baku fossil masih terus berkembang dan menghasilkan polusi. Perdagangan Karbon, menukar emisi dengan green forest yang dikembangkan di negara-negara berkembang menjadi tameng. Permainan ini menuju kompetisi yang tidak sehat, kondisi nash equilibrium antar negara penghasil emisi.
Pada kondisi ini kita tidak dapat mengharapkan kesepakatan berjalan normal. Seperti dalam teori prisoner's dilemma, kompetisi ditengah makin langkanya sumberdaya ini membuat banyak negara wait and see. Satu sama lain saling menunggu, curiga dan mencuri-curi kesempatan untuk dirinya. Kondisi Nash equilibrium seharusnya menjadi alert bagi kesadaran sebelum Bumi mengalami tragedy of common secara global
Kenapa kesepakatan ini penting?