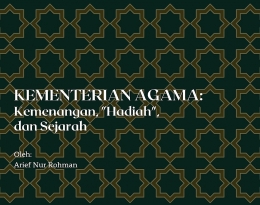Kemenangan dan Hadiah adalah dua hal yang tidak terlepas satu sama lain, serupa dua sisi mata uang yang memiliki nilai masing-masing. Hadiah diberikan ketika seseorang memenangkan sebuah kompetisi atau hal lain yang memungkinkan dirinya "berhak" memperoleh hadiah.
"Hadiah" adalah pemberian, ganjaran, kenang-kenangan. Begitulah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikannya. Perolehan hadiah diberikan secara sukarela oleh siapa pun (individu, instansi, pemerintah) termasuk negara.
Berbicara soal hadiah, pernyataan Menteri Agama pada webinar Peringatan Hari Santri yang diselenggarakan oleh PBNU beberapa waktu lalu, memantik polemik. Begini ujarnya:
"Kemenag itu hadiah negara untuk NU bukan untuk umat Islam secara umum, tetapi spesifik untuk NU. Jadi wajar jika NU menanfaatkan peluang yang ada di Kemenag." Ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (20/10). Sebagaimana dinukil pula dari berbagai situs berita.
Pernyataan ini memantik kesadaran berpikir, bertindak, dan bersikap kita selaku individu, kelompok, dan anak bangsa. Beberapa kelompok bereaksi dengan mengeluarkan pernyataan serupa, ada pula yang memilih untuk diam memendam. Namun yang terpenting, hal ini perlu disikapi dengan sadar, arif, dan inklusif.
Sehingga hal ini tidak lagi sebagai narasi yang kontra produktif, yang mampu mengoyak kesadaran kebhinekaan kita sebagai anak bangsa.
Dalam tulisan ini, saya ingin menelaah sejarah, bagaimana sebenarnya Kementerian Agama bermula? Sudahkah kita bijak menerima Kementerian tersebut sebagai "hadiah"?

Sebuah Sejarah
Kevin W. Fogg, seorang sejarawan ahli yang banyak melakukan riset dalam bidang komunitas masyarakat dan Islam di Asia Tenggara, juga seorang yang pernah bekerja di Pusat Studi Islam Oxford University, menulis dalam bukunya "Spirit Islam pada Masa Revolusi Indonesia" (Noura, 2020). Fogg menuturkan, pada mulanya pendirian Kementerian Agama dilatari oleh dua tren dalam pemerintahan pada awal kemerdekaan. Pertama, kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan Islam, terutama dengan kegagalan Piagam Jakarta. Kedua, kebutuhan mengintegrasikan secara khusus ulama, para tokoh teologis dari masyarakat Islam di pemerintahan baru.