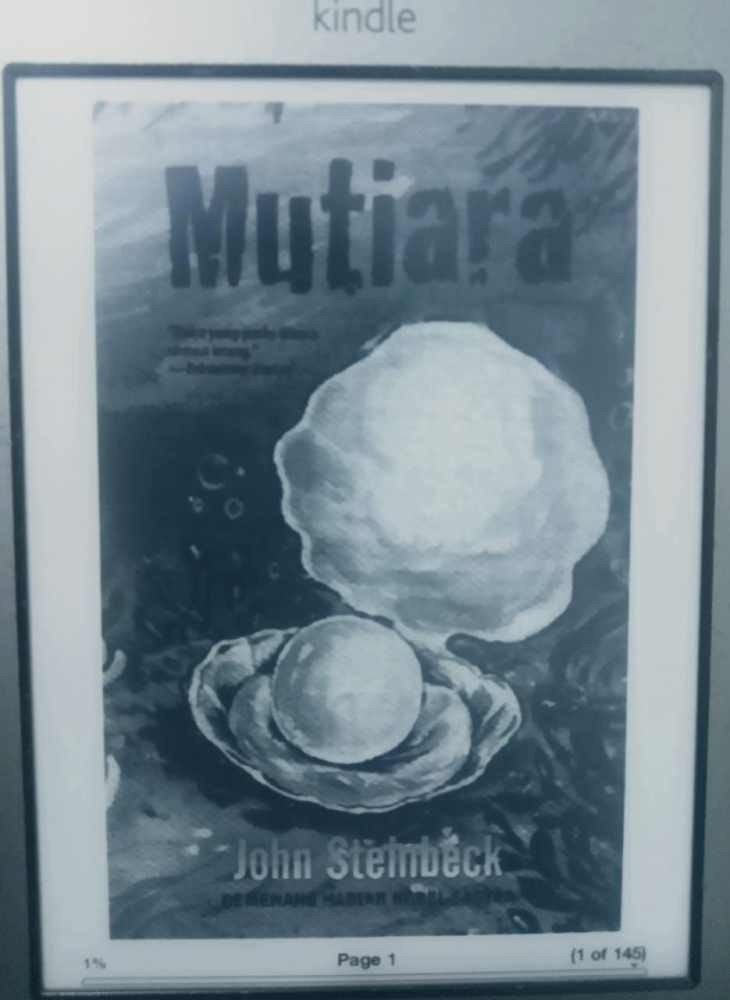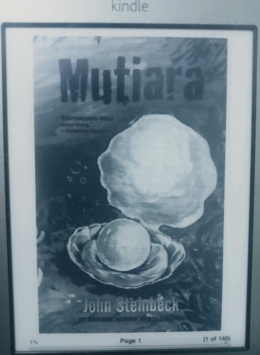Ada yang salah dari sinopsis singkat yang dicantumkan penerbit Serambi di novela terjemahan John Steinbeck berjudul "The Pearl" (Mutiara) ini.
"Harta bukanlah segalanya," ringkas penerbit di sampul belakang, "dan kebahagian tidak bisa dibeli."
Dalam novel yang pertama kali terbit tahun 1947 ini, Steinbeck mengangkat kisah seorang pribumi Mexico bernama Kino yang ketiban rezeki setelah menemukan sebongkah mutiara terbesar di dunia saat melaut. Seperti kebanyakan kehidupan sosial masyarakat desa yang akrab dengan "getok tular", informasi cepat menyebar ke seantero penjuru, menggemparkan seisi daerah, mulai dari pengemis sampai para elite.
Kino yang seumur hayat hidup dalam kemiskinan langsung berfantasi ketinggian, membayangkan apa yang akan ia lakukan dengan hasil penjualan harta luar biasanya, apalagi di saat yang sama bayi laki-lakinya, Coyotito, sedang sekarat setelah disengat kalajengking, dan tak bisa diobati karena dokter meminta bayaran tinggi.
Tapi kisah ini bukan soalan karma dari keserakahan manusia saat mendadak punya kuasa dan harta, seperti kecenderungan interpretasi yang dipakai penerbit sebagai sinopsis. Bukan.
Steinbeck sedari awal sudah menggambarkan bagaimana tragisnya hidup para pribumi yang ratusan tahun sujud menyerah karena terjajah--sesuatu yang tentu akrab bagi pembaca di negeri kita.
Tak hanya dikuras hasil buminya, Kino yang jadi perwakilan mereka yang kalah, juga jadi korban manipulasi pihak kolonial, yang membuatnya tak punya pilihan apa-apa karena tak punya pendidikan dan sumber daya yang ada di titik terendah untuk sekadar awas, apalagi sampai melawan. Ini tergambar saat dokter picik memanfaatkan keluguan Kino dengan meracuni anaknya dan kemudian berlagak jadi penyelamat, demi mengeruk keuntungan dari harta yang mendadak didapat Kino, seorang manusia yang di awal ia sebut sebagai "hewan".
Apa yang dibayangkan Kino saat melihat masa depannya setelah menjual mutiara raksasa bukanlah bentuk keserakahan, tapi keinginan normal seorang manusia, seorang ayah, seorang suami, untuk lepas dari jerat kemiskinan, kebodohan dan riwayat panjang sebagai yang tertindas. Ia melihat putranya, yang kelak bisa sekolah, bisa membaca, bisa menjadi pembuka jalan bagi kelompoknya untuk bangkit dari keterpurukan.
Ia melihat dirinya dan istri yang dia cintai setengah mati, Juana, bisa menikah secara "resmi" di gereja dengan pakaian bagus dan upacara meriah.
Kisah ini memang berakhir tragis. Lagi-lagi, dari sinopsis yang dicantumkan, kesan itu sudah bisa diketahui lebih dulu.
Hanya saja, kisah ini bisa diartikan sebaliknya. Harapan besar dan perjuangan Kino yang disandarkan pada mutiara "terkutuk" itu merepresentasikan kesadaran untuk berubah dan melawan, yang melebihi kepentingan egoistik.
Seperti kalimat penutup Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia-nya Pram (yang mengakui jika Steinbeck adalah gurunya dalam menulis), kisah ini walau ditamatkan dengan kehilangan dan duka yang dalam, setidaknya Kino sudah melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI