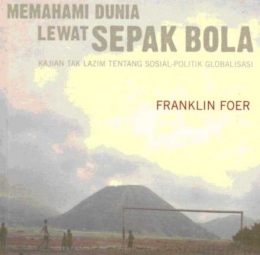Foer terbang jauh ke kota mode Milan untuk menyaksikan dengan gamblang bagaimana Silvio Berlusconi--dibantu dengan jejaring media--mampu memanfaatkan kekuatan luar biasa sepakbola untuk menaikkan elektabilitas dan kelak menjadi penguasa tanah Italia.
AC Milan, klub yang diakuisisi Berlusconi, tidak hanya sekadar tim yang dipadati pemain bintang dan gelar juara--ia merangkap sebagai kendaraan politik.

Tidak cuma itu, sepakbola juga ternyata memiliki cukup daya untuk mencetus revolusi. Di negara sekonservatif Iran misalnya. Negeri Ayatollah pernah jadi tempat terjadinya "pemberontakan" yang dirangsang oleh euforia sepakbola. Menarik, karena revolusi tersebut justru diprakarsai oleh kaum perempuan. Negara Islam Iran yang berusaha memisahkan perempuan dan olahraga, yang dalam pandangan budaya dan teologi dianggap tidak layak menggandrungi olahraga maskulin semacam sepakbola, mesti mengaku kalah saat globalisasi ikut campur tangan.
Untuk sepakbola, para wanita nekat melawan. Mulai dari aksi kecil namun berbahaya dengan menyamar sebagai pria untuk menonton pertandingan sepakbola,
"Kalau dicermati lebih lanjut, jelaslah bahwa pria-pria ini sebenarnya bukan pria.Mereka pres payudaranya, gelung rambut panjangnya, berpakaian dengan jubah pria, dan menyelinap masuk ke dalam stadion."
hingga lima ribuan perempuan Iran yang bersatu menembus barikade aparat demi menyaksikan para pemain idolanya secara langsung pasca memastikan lolos ke Piala Dunia,
"Ribuan perempuan mengabaikan himbauan pemerintah, mereka berkumpul di seberang gerbang Azadi pada suhu menggigilkan minus 2 derajat Celsius. Ketika polisi menolak masuknya perempuan-perempuan ini, mereka berteriak, "bukankah kami juga bagian dari bangsa ini? Kami ingin merayakannya juga. Kami bukan semut!" Takut akan massa yang membludak, polisi pun memperbolehkan 3 ribu perempuan memasuki tempat khusus. Tapi bagaimana dengan 2 ribu perempuan yang lainnya? Mereka mendobrak pagar polisi dan berebut masuk ke stadion. Polisi tak punya pilihan selain membolehkan mereka masuk dan mengaku kalah."
Buku ini juga membahas mengenai keterlibatan para pelaku kejahatan kemanusiaan dalam konflik Serbia-Bosnia yang menjadi pendukung penting klub raksasa Serbia, Red Star Belgrade. Ia juga menyusuri fenomena masa lalu cerah dan mulai redupnya praktik hooliganism di Inggris raya lewat interview mendalam dengan pentolan HeadHunters, suporter garis keras Chelsea.
Pembahasan bernas juga bisa ditemukan dalam kajian Foer perihal rasisme sepakbola di Ukraina, nasionalisme Katalan yang kental diwakili oleh mes que un club, Barcelona, serta fakta unik sejarah Zionisme yang bersinggungan dengan sepakbola dan di saat yang sama gerakan anti-semit yang mewarnai kompetisi Eropa. Foer juga tidak lupa membahas negeri para Dewa Bola, namun dengan sorot suram, saat sepakbola menjadi lahan seksi untuk praktik korupsi di Brazil.
Lewat pandangan teoretis dan pengamatan langsung yang panjang, Foer berusaha menjalin hubungan rasional yang tercipta antara globalisasi dan sepakbola sebagai sebuah kondisi yang punya pengaruh menentukan bagi banyak aspek vital global; sosial-politik, ekonomi sampai primordialisme. Dan tampaknya, ia berhasil.
Namun akibatnya, buku ini jadi tampak kering jika pembaca berharap mendapat sajian sepakbola murni sebagai sebuah permainan. Tidak banyak kisah-kisah menarik yang terjadi di atas lapangan, tidak ada cerita gol-gol spektakuler atau data dan fakta yang membawa kita lebih dekat ke pemain-pemain bintang.