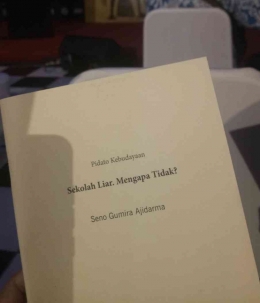Tanggal 2 Mei yang disahkan sebagai Hari Pendidikan Nasional selalu menjadi momentum untuk mengulas kembali historisitas sistem pendidikan di Indonesia maupun menjadi momentum untuk mengkritik sistem pendidikan nasional hari ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh sastrawan Indonesia, Seno Gumira Ajidarma, dalam pidato kebudayaannya pada Selasa (2/5/2023) di Gedung The Ratan, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Pidato Kebudayaan tersebut merupakan salah satu agenda dalam gelaran Jogja Art + Books Fest yang diselenggarakan Yayasan Seruang mulai 29 April – 16 Mei 2023. Sebelum pidato dimulai, Fajar Merah, seorang putra dari aktivis HAM Widji Thukul yang hilang pada tahun 1998, mempersembahkan dua buah lagu berjudul “Lagu Anak” dan “Bunga dan Tembok”. Para hadirin dibuat terpaku oleh pembawaan Fajar yang begitu menyelami emosi dari setiap karyanya.

Suara gitar dan nyanyian berhenti, sang sastrawan memulai pidatonya. Seno mengawali isi pidato dengan membahas ihwal kritik Ki Hajar Dewantara terhadap sistem pendidikan di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pendidikan pada masa itu tidak dapat dipisahkan sebagai bentuk perjuangan kebebasan yang dicurigai sebagai “gerakan nasionalis”, yang mana hal itu menjadi momok bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara mengkritik bahwa pendidikan kolonial itu “tidak membantu mengembangkan badan dan pikiran, tapi semata-mata memberikan surat diploma yang memungkinkan mereka menjadi buruh”.
Pendidikan kolonial mencegah terciptanya masyarakat sosial dan menghasilkan kehidupan yang tergantung kepada bangsa barat. Hal itu tidak hanya dapat diatasi dengan konfrontasi fisik melalu gerakan politik saja, tetapi juga dengan menanamkan bibit-bibit gaya hidup yang merdeka dalam jiwa rakyat melalui sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu Taman Siswa didirikan dan disebut sebagai tipe ideal sistem pendidikan yang dibangun dari tradisi kebudayaannya sendiri.
Taman Siswa, beserta sekolah-sekolah lain yang hidup tanpa subsidi pemerintah kolonial disebut sebagai sekolah-sekolah liar, yang kemudian pada tahun 1932 munculah Ordonansi Sekolah Liar atau upaya penertiban dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah ini. Menurut Dewantara, ordonansi itu menghilangkan hak asasi orang tua dan rakyat untuk memilih bagaimana mendidik anaknya, serta mematikan kebebasan rakyat untuk mengadakan pendidikan menurut cara-cara dan tujuan mereka sendiri.
Namun, tak semua sekolah liar merupakan gerakan pendidikan. Apabila sekolah liar didirikan hanya dimaksudkan sebagai pengganti nafkah yang hilang dalam krisis ekonomi, maka Dewantara menyebutnya sebagai “rumah perniagaan, toko atau ambachtswerkplaats untuk ‘menjual ilmu’”, yang mana guru-gurunya adalah ‘tukang dagang intelek’. Kemudian jika melihat pada konteks pendidikan nasional di Indonesia saat ini, apakah hal itu sudah berubah?

Merujuk pada sejarah yang lebih jauh lagi, Seno mengambil penggambaran tentang seorang mahaguru dari kisah wayang, yakni Mahaguru Dorna. Dari ilustrasi yang digambarkan dalam buku Het Javaansche Tooneel (J.Kats, 1923), busana sang mahaguru sangat menunjukkan posisi kehormatannya juga keduniawiannya, yang mana hal tersebut merepresentasikan kaum guru sekolah liar saat itu yang tergolong “tukang dagang intelek”. Dalam mengemban tugasnya sebagai pengajar para putra Bharata, yakni Bangsa Aria (Pandawa dan Kurawa), mahaguru Dorna bersumpah tidak akan mengajar bangsa lain agar keturunan Bharata menjadi yang paling unggul.
Suatu hari datang seorang putra mahkota dari negeri Nisada yang bernama Ekalaya kepada sang mahaguru. Kedatangan Ekalaya bermaksud mencari ilmu kesaktian sebagai bekalnya untuk menjadi raja kelak. Namun, sesuai sumpahnya, Dorna menolak untuk menerima Ekalaya sebagai murid karena menganggap warga Nisada sebagai manusia yang derajatnya lebih rendah. Hal itu menunjukan bahwa Dorna memang menjual ilmunya kepada penawar tertinggi (keturunan Bharata) atas kemewahan dan kehormatan yang diterimanya. Rupanya meski dihina begitu rupa, Ekalaya masih mengakui Dorna sebagai guru meskipun pada akhirnya ia belajar memanah secara mandiri di dalam hutan. Ekalaya bahkan membuat patung Dorna sebagai konstruksi ilmu pengetahuan mandiri dalam imajinasi kreatif Ekalaya.
Kembali melihat konteks pendidikan hari ini berdasarkan perlawanan Taman Siswa dan kisah Mahaguru Dorna, Seno melacak kemungkinan pembuktian terbalik: “adakah kiranya dalam iklim pendidikan hari-hari ini, terdapat suatu cara pembelajaran tanpa subsidi pemerintah, yang kehadirannya bukanlah sebagai rumah pengecer ilmu, melainkan justru alternatif, jika bukan perlawanan terhadap formasi diskursif kuasa pendidikan nasional kelas dominan”.
Satu contoh peristiwa dalam bidang pendidikan seni rupa disampaikan oleh sastrawan yang juga pengajar di IKJ tersebut, yakni tentang rencana tugas akhir seorang mahasiswa di perguruan tinggi seni yang ditolak pada tahun 1985. Rencana tugas akhir tersebut bertopik Kesenian Unit Desa (KUD) yang berbentuk seni instalasi: hamparan 23 tikar pandan, tempat diletakannya pincuk daun pisang berisi sejumput tanah dengan semaian biji jagung, bayam, tangkai kangkung dan ketela rambat jenis bibit tanaman ladang apung di atas rawa. Konsep tersebut menawarkan dialog dengan warga kampus tentang kemiskinan petani Maung, Tulungagung yang hidup di daerah rawa-rawa.
Penolakan disebabkan karena kriteria yang berlaku adalah seni lukis, sesuai jurusan mahasiswa bersangkutan, sehingga disebut “tidak memenuhi syarat akademis”. Namun, Seno berpendapat apabila hal ini dilihat dalam skala yang luas, sistem pendidikan nasional secara umum kapasitasnya cukup terbatas untuk menangkap denyar-denyar keliaran kreatif di luar sistem, yang justru konstekstual dengan kebutuhan zamannya.
Singkat cerita, setelah mahasiswa tersebut lulus, ia menjadi seorang guru gambar. Baginya, seni rupa adalah media dialog non-jenjang, non-hierarkis dan sepenuhnya dikuasai, dihidupi, dibutuhkan, dikembangkan, dikendalikan oleh kepentingan rakyat bawah guna mengungkapkan aspirasi komunitasnya ke arah kemandirian, keadilan, dan demokratisasi. Dalam prakteknya, Moelyono, nama guru gambar tersebut, mengajari anak-anak kaum nelayan yang tidak mampu membeli alat dan buku gambar untuk menggambar menggunakan kaki atau ranting di pasir pantai. Ia mengajari anak-anak tersebut untuk mengungkapkan kehidupan mereka yang dirundung malaria, maupun dunia yang penuh konflik karena persoalan remeh, seperti berebut selang air.
Apa yang dilakukan Moelyono, memperlihatkan persoalan pendidikan nasional hari ini yang lebih menyediakan peluang bagi sukses individual, kemewahan dan kehormatan, daripada berpihak pada orang-orang kalah. Kiranya seorang Moelyono tidak hanya terdapat dalam pendidikan seni rupa, tetapi dalam segala bidang ilmu pengetahuan.
Pidato Seno ditutup dengan sebuah statement :
“Sekolah liar sudah merupakan gejala sejak Ekalaya belajar memanah dengan guru imajinatif di dalam hutan, maupun dalam perjuangan Taman Siswa ketika melawan Ordonansi Sekolah Liar penguasa kolonial, dan karena itulah sekolah liar akan selalu ada. Kehadiran saya di sini hanyalah untuk mengesahkan! Terima kasih dan salam.”
Tepuk tangan hadirin seketika bergemuruh riuh merespon pidato magis yang baru saja disampaikan oleh Seno Gumira Ajidarma. Kiranya pidato tersebut dapat menjadi bahan introspeksi dan perenungan terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia hari ini, khususnya bagi para pendidik agar tidak menjadi “tukang dagang intelek”, tetapi benar-benar memiliki niat tulus untuk membentuk karakter dan mencerdaskan bangsa yang sesuai dengan nilai kebudayaan Indonesia. Acara kembali ditutup dengan penampilan musik dari Fajar Merah yang membawakan “Sikap” dan sebuah musikalisasi dari puisi karya kakaknya, Fitri Nganthi Wani, yang berjudul “Kau Berhasil Jadi Peluru”.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI