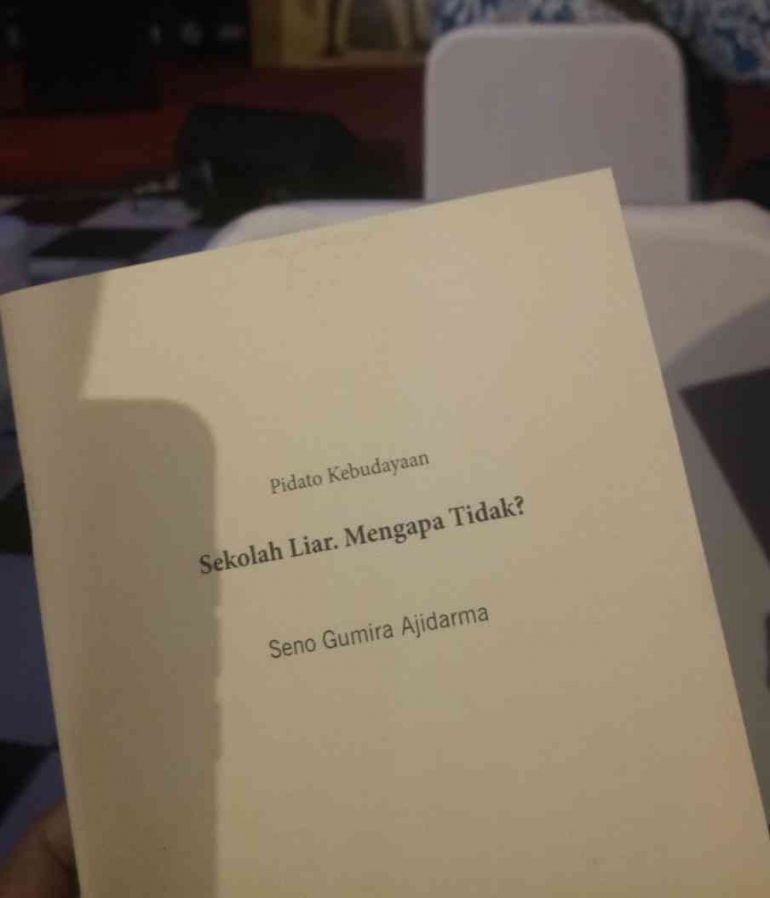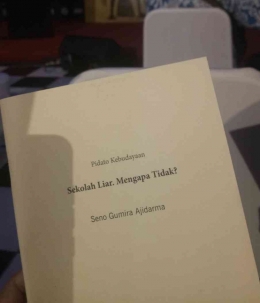Satu contoh peristiwa dalam bidang pendidikan seni rupa disampaikan oleh sastrawan yang juga pengajar di IKJ tersebut, yakni tentang rencana tugas akhir seorang mahasiswa di perguruan tinggi seni yang ditolak pada tahun 1985. Rencana tugas akhir tersebut bertopik Kesenian Unit Desa (KUD) yang berbentuk seni instalasi: hamparan 23 tikar pandan, tempat diletakannya pincuk daun pisang berisi sejumput tanah dengan semaian biji jagung, bayam, tangkai kangkung dan ketela rambat jenis bibit tanaman ladang apung di atas rawa. Konsep tersebut menawarkan dialog dengan warga kampus tentang kemiskinan petani Maung, Tulungagung yang hidup di daerah rawa-rawa.
Penolakan disebabkan karena kriteria yang berlaku adalah seni lukis, sesuai jurusan mahasiswa bersangkutan, sehingga disebut “tidak memenuhi syarat akademis”. Namun, Seno berpendapat apabila hal ini dilihat dalam skala yang luas, sistem pendidikan nasional secara umum kapasitasnya cukup terbatas untuk menangkap denyar-denyar keliaran kreatif di luar sistem, yang justru konstekstual dengan kebutuhan zamannya.
Singkat cerita, setelah mahasiswa tersebut lulus, ia menjadi seorang guru gambar. Baginya, seni rupa adalah media dialog non-jenjang, non-hierarkis dan sepenuhnya dikuasai, dihidupi, dibutuhkan, dikembangkan, dikendalikan oleh kepentingan rakyat bawah guna mengungkapkan aspirasi komunitasnya ke arah kemandirian, keadilan, dan demokratisasi. Dalam prakteknya, Moelyono, nama guru gambar tersebut, mengajari anak-anak kaum nelayan yang tidak mampu membeli alat dan buku gambar untuk menggambar menggunakan kaki atau ranting di pasir pantai. Ia mengajari anak-anak tersebut untuk mengungkapkan kehidupan mereka yang dirundung malaria, maupun dunia yang penuh konflik karena persoalan remeh, seperti berebut selang air.
Apa yang dilakukan Moelyono, memperlihatkan persoalan pendidikan nasional hari ini yang lebih menyediakan peluang bagi sukses individual, kemewahan dan kehormatan, daripada berpihak pada orang-orang kalah. Kiranya seorang Moelyono tidak hanya terdapat dalam pendidikan seni rupa, tetapi dalam segala bidang ilmu pengetahuan.
Pidato Seno ditutup dengan sebuah statement :
“Sekolah liar sudah merupakan gejala sejak Ekalaya belajar memanah dengan guru imajinatif di dalam hutan, maupun dalam perjuangan Taman Siswa ketika melawan Ordonansi Sekolah Liar penguasa kolonial, dan karena itulah sekolah liar akan selalu ada. Kehadiran saya di sini hanyalah untuk mengesahkan! Terima kasih dan salam.”
Tepuk tangan hadirin seketika bergemuruh riuh merespon pidato magis yang baru saja disampaikan oleh Seno Gumira Ajidarma. Kiranya pidato tersebut dapat menjadi bahan introspeksi dan perenungan terhadap sistem pendidikan nasional di Indonesia hari ini, khususnya bagi para pendidik agar tidak menjadi “tukang dagang intelek”, tetapi benar-benar memiliki niat tulus untuk membentuk karakter dan mencerdaskan bangsa yang sesuai dengan nilai kebudayaan Indonesia. Acara kembali ditutup dengan penampilan musik dari Fajar Merah yang membawakan “Sikap” dan sebuah musikalisasi dari puisi karya kakaknya, Fitri Nganthi Wani, yang berjudul “Kau Berhasil Jadi Peluru”.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H