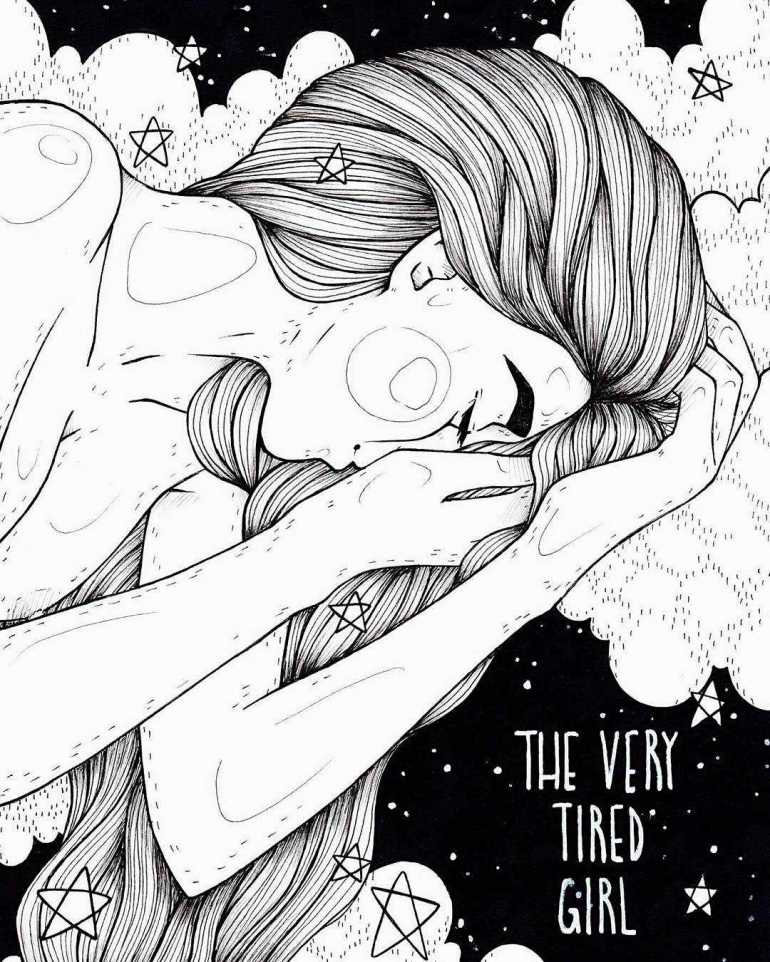Antara kau dan aku, jangan minta pendapat orang lain. Rasanya jika melihat kau mendengar mereka, membuatku merasa semakin kesepian saja. Dan itu benar.
Dua hari setelah kita berpisah, aku sering melamuni banyak hal di atas kendaraanku. Memikirkan tentangmu, bukan tentangmu dan sama sekali bukan tentang kita berdua.
Terkadang aku memang sengaja berhenti, memarkir kendaraanku di tepi trotoar hanya ingin tahu caranya menyaksikan bagaimana pada akhirnya seseorang dikelabuhi selintas pikiran mereka sendiri, yang membuatnya berubah pikiran hingga memutuskan mengemudikan kendaraannya lagi, karena tak pernah yakin dapat mencapai keputusan mutlak yang segala hal tentang resikonya kelak menguntungkan atau justru akan disesalinya di masa depan.
Aku tidak pernah menyesal berpisah denganmu. Dan kulihat dengan kedua mata kepalaku sendiri, kau berbahagia di waktu yang sama. Sungguh melegakan jika urusan perpisahan ini berjalan lancar tanpa kesulitan laksana kebutuhan pagi hari ketika kita buang air besar.
Akan tetapi aku mudah sekali kecewa dengan jalan berlubang yang seolah-olah mengaku diciptakan untuk memantul-mantulkan kepala pengendara pelamun sepertiku. Bagai anak kecil yang suka bermain botol soda, mereka mengocok-kocok isi kepalaku. Yang membikin jaringan sarafku kembali konsleting, yang akibatnya harus kusesalkan karena mampum membuatku berubah pikiran lagi.
Kupikir, aku kesepian dan menyesali keputusanku berpisah denganmu. Sementara itu, tidak; kau masih mengambil keuntungan pertama dari perpisahan ini: kau ingin bahagia. Dan rupanya, kau berhasil.
Dua hari sebelum kita berpisah. Aku membayangkan kita terlibat dalam adegan drama yang masing-masing tokoh-tokohnya hanya dimainkan oleh kita berdua. Kau sebagai laki-laki pemurung, keras kepala, dan susah diatur. Sementara aku, aku lah perempuan pemarah itu. Yang penyayang namun juga tak mau mengalah.
Maka ketika kau bilang padaku di atas panggung, "Sebaiknya pikirkan dulu. Aku tak pernah memikirkan hidup tanpamu. Tapi jika sudah jadi keputusan bulat demi kemaslahatan bersama. Kita bisa melakukannya tanpa ragu-ragu."
Dan ketika kujawab dengan nada paling tak ramah, "Ya. Tapi kali ini aku berkeras. Ingin berpisah denganmu. Aku tak ingin membuatmu kecewa lebih banyak."
Kau, dengan nada yang kukenal betul intonasinya itu, membalas, "Asal kita cocok dalam segala hal. Sayangnya kecocokan itu cuma lahir kalau kita tidak saling membebani. Aku tak pernah berpikir bahwa kau mengecewakanku."
Ya. Dialog percakapan sore itu memang sama sekali tak jelas. Seperti rekaman kaset yang diputar terbalik. Apalagi jika kita menginginkan simpati penonton atau pendengar: kepada siapa sebaiknya mereka memihak. Namun faktor-faktor di samping alasan kita bertengkar di suatu sore pertengahan Mei yang gerimis, kurasa, kita berdua tak bisa menyembunyikan apa-apa, detik-detik paling penting untuk dilewatkan bersama bahwa: kau menginginkan bahagia, dan, aku tak bisa memberimu kebahagiaan.
Dua tahun setelah kita berpisah. Aku memutuskan menjadi rakyat sipil. Yang memang dulunya cuma warga biasa. Bedanya warga biasa bergabung bersama rukun tetangga, rukun warga, sampai rukun-rukun lainnya yang terdaftar sebagai anggota kelompok yang diakui karena ketetapannya hadir di suatu lingkungan. Sementara rakyat sipil, bertindak di bawah kuasa Yang Maha Adil. Sehingga segala hal tindak tanduknya sering dicurigai asing, terlebih jika mengingat riwayat hidupnya selama ini.
Aku berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melupakanmu dan berusaha merancang masa depanku bersama tidak denganmu, sambil berharap melakukan kesalahan yang bisa kuperbuat: aku bertemu dengan aparat pemabuk, yang memiliki masalah berat dengan hidupnya sendiri sehingga ia bisa menyalurkan kemarahannya dengan menghabisiku di tempat pertama kali ia berdiri.
Aku membayangkan aku mati dan aku melupakanmu.
Akan tetapi kunjunganku ke kota-kota jauh sia-sia saja. Aku tak bisa melupakanmu atau sekedar bertemu seorang aparat pemabuk itu, yang sering ditulis di koran-koran, suka menyiksa rakyat sipil karena berbagai alasan sepele dan kekanak-kanakan.
Lantas, bertahun-tahun setelah kita benar-benar berpisah. Aku bertemu seorang teman. Teman lama, kupikir begitu, yang entah kenapa setelah bertahun-tahun menikah ia tak kunjung memiliki anak. Di sebuah kedai kopi lima puluh meter dari stasiun, aku mendengarkan ocehnya berjam-jam sambil mengantuk. Lalu tanpa alasan yang kupahami tiba-tiba saja dia menyela ceritanya sendiri, bertanya padaku: berapa umurmu?
"Apa kau ingat berapa umurmu?"
Aku tidak tahu alasan tepatnya dia tiba-tiba mengataksn seperti itu. Mungkin hanya iseng. Tapi melihat ketulusan raut mukanya yang periang, aku menebak, barangkali dia juga bahkan tak ingat namaku?
Maka kujawab, taulah, dengan nada sok pintar.
Percakapan kami harus berakhir karena dia mesti mengejar kereta ke Manggarai. Aku memberinya salam perpisahan namun dia membalas dengan memberiku kartu namanya. Lalu sesaat setelah yakin dia sudah masuk ke dalam gerbong kereta api, aku melemparkan kartu nama itu ke tempat sampah yang berada di dekat kakiku. Hari yang buruk.
Aku mengambil tiket kereta tujuanku di dalam jaket yang sudah kupesan dua jam lalu. Kemudian, setelah sepuluah menit memastikan kereta akan melaju, aku duduk di dekat jendela bagai seorang yang baru saja dipenuhi kedukaan.
Kereta berjalan konstan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Melaju menyusuri lintasannya seperti aku yang juga sedang menyusuri lintasan hidupku sendiri, hingga tiba-tiba aku teringat tentangmu, bukan tentangmu, dan sama sekali bukan tentang kita berdua. Alih-alih aku teringat wajah lelaki yang baru saja menyapaku, ya, lelaki yang tak kukenali itu, tapi dia bahkan merasa sudah mengenalku dengan baik selama bertahun-tahun seperti halnya kau.
Kau mengenalku begitu lama, aku jadi penasaran bagaimana caramu melupakan orang yang bahkan tak kau kenal. Sementara aku yakin, kau sudah melupakanku, orang yang sudah bertahun-tahun akrab denganmu. Tahu nama kecilmu, tahu berapa umurmu. Tahu segala hal yang dibutuhkan sosokmu ketika merasa sedih atau berduka.
Kereta melaju seperti kecepatan cahaya, atau kecepatan angin minggat ke arah yang tak terduga. Lalu seketika selintas gerbong menjadi gelap gulita -mungkin sedang memasuki lorong sunyi- dan saat itulah hatiku mendadak berdegup. Tak bisa merasakan apa-apa. Hanya berdegup. Aku bahkan tak bisa merasakan angin di sekitarku. Kemana perginya angin-angin itu?
Namun sesaat kemudian kereta mulai melambat, dan berderit -di pemberhentian pertamanya- dan setengah hatiku ingin memutuskan setengahnya lagi yang menjadi pertimbangan sepenuhnya padamu. Aku sebaiknya cukup menyesali kesempatan kita berpisah saja. Bukan berharap menarik ulur dirimu di tiap kesempatan aku ingin kembali ke masa lalu itu. Ke tempat jauh itu. Hingga di masa depan tak mestinya buatku salah tingkah karena sebuah penyesalan yang sebetulnya kubuat sendiri.
Kalau saja penyesalan itu punya alamat, pasti akan lebih mudah untuk kita mengunjunginya dan meminta maaf.
Setiap merasa gelisah, aku mencari-cari doa penenang yang ada di dalam hatiku. Tak lain, untuk mendoakan diriku sendiri, mendoakanmu. Dan itulah yang kulakukan sekarang ini ketika mengingatmu.
Maka kelak setelah perpisahan ini, jika kau melihatku melalui mata orang lain, bahwa aku telah melupakanmu, percayalah bahwa yang mereka lihat itu bukan aku. Melainkan kesepianku yang cakap memilih doa di dalam hati.
Oleh karena itu, barangkali perpisahan ini bisa menjadi lebih menarik. Sebab tujuanku mencintaimu sekarang, bukan lagi soal penyesalan yang berlarut-larut menginginkanmu kembali bersamaku lagi, melainkan kesepian panjang itu yang serta merta turut menyertaimu dalam doaku.
Ajibarang, 15 Oktober 2017
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H