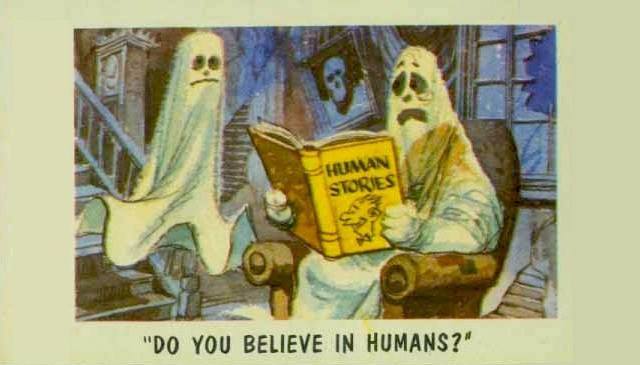Sekuat tenaga Ben berteriak memanggil Ki Plenyun. Tapi lidahnya terkunci urat ketakutannya sendiri, menyulapnya jadi amat kaku tanpa sedikitpun mampu untuk digetarkan.
Hal yang sama terjadi pula pada jaringan otot di seluruh tubuh Ben, membuatnya semakin panik ketika jempol setan itu kian beringas menghampiri. Siap mengunyah dirinya hingga menjadi ribuan serpih daging yang penuh saus darah.
Apakah aku akan mati di sini? Di WC? Juga karena menjadi korban Jempol Setan? Alangkah amat tak kerennya!
Ben ingin berdoa, tapi dia ingat wejangan Pak Ustadz tentang makruhnya menyebut nama Tuhan di dalam WC. Haruskah dia merendahkan nama-Nya, hanya demi keselamatan jiwa pribadi?
Begitu juga ketika Ben ingin melafal, “Numpang-numpang anak bagong lagi e’ek,” ajaran kakak pembina pramukanya waktu kecil dulu, dia justru merasa tak ikhlas.
Apa hebatnya berpura-pura jadi anak babi? Apakah hanya demi menyelamatkan diri dia harus hidup dari kepura-puraan? Mesti rela merendahkan diri menjadi anak dari hewan rakus, untuk kemudian kelak berubah kembali menjadi tikus kantor atau lintah darat penghisap masyarakat?
Bermacam-macam ingatan susul-menyusul di benak Ben dengan amat riuh, hingga akhirnya, sebuah ingatan jahil berhasil membangkitkan semangatnya.
Tubuhnya kembali rileks. Ditatapnya jempol setan yang terus menggeram seram di depannya dengan senyum sinis.
Seperti tahu disepelekan Ben, jempol setan meraung sejadi-jadinya. Taringnya mencuat ke depan, dengan seluruh bulu yang ada di sekujur jempolnya mengejang sekeras duri. Mulutnya terbuka lebar dan langsung mencaplok Ben bulat-bulat.
Sigap Ben menghindar ke samping, lalu dengan penuh keyakinan dia acungkan jari kelingking ke arah jempol setan, dan…
WUZZZ…!



![[3] Di Balik Pintu Kematian: Pekik Keramaian](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2024/12/13/keramaian-3-675c583034777c39f966e3d4.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)