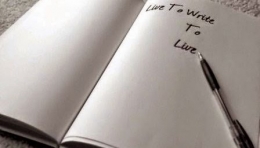Beberapa karya pernah menuliskan realitas “krisis” itu, dan Pramodeya lewat “Teatrologi Pulau Burunya”, secara tidak langsung bertutur tentang hal itu. Terlepas apakah kita sepakat atau tidak, bahwa mental-mental inlander yang melanda bangsa kita sejak dulu, seperti penyakit yang muncul saat kita berada dalam ambang krisis budaya, salah satunya akibat gagalnya kita memahami sejarah dan bangsa sendiri. Gagal memahami bukan hanya karena “keengganan” untuk memahami, tapi juga karena ketiadaan produk literasi yang mencerdaskan. Bahkan disebut-sebut, kalau bangsa kita baru menyadari dirinya terjajah, setelah karya “Max Havelar” Maltatuli sampai di tangan sebagian kaum terpelajar saat itu.
Dalam konteks inilah, kita berusaha menempatkan pada tempat yang layak, bahwa hanya budaya literasi yang bisa mendorong kita kembali pada kemajuan. Literasi, bukan sekadar ditempatkan sebagai wadah untuk mewarisi pengetahuan semata, tetapi pemahaman, yang dapat mendorong budaya diskursus “mencari” dan menemukan realitas akan ide-ide baru.
Sejarah bangsa sendiri, cukup apik menceritakan bagaimana pertautan perkenalan dunia literasi, menjadi momentum kebangkitan bangsa. Kita mengenal Tan Malaka, Kartini dll. Bahkan Pram dalam “Teatrologi Pulau Burunya” menempatkan kesadaran literasi sebagai titik tolak kebangkitan nasional. Lewat literasi kita berani dan memiliki kekuatan untuk bangkit. Ide-ide dan gagasan progresif, betul-betul beranak-pinak lewat literasi, menyebar dan membakar hingga ke ubun-ubun. Dari literasi berujung pada semangat agitasi.
Realitas
Namun, tak cukup hanya data statisitik untuk menunjukkan rendahnya budaya literasi kita. Sangat mudah dijumpai, disekolah-sekolah misalnya, tradisi bertutur tulis sangatlah rendah. Para pelajar lebih asyik untuk mendengarkan dan membicarakan ketimbang menuliskan.
Sekolah belum mampu membangkitkan tradisi literasi. Setali dengan gagalnya untuk mebangkitkan budaya baca.
Meski kita paham bahwa “Yang terucap akan hilang terbawa angin, hanya yang tertulislah yang abadi”. Namun, kurikulum sekolah memang tidak mengarah pada hal-hal yang bisa melangkah dalam budaya literasi tersebut. Kita akui, bahwa ditingkat operasional pun, penddikan kita masih berlatar budaya bisu: mendengarkan dan patuh. Tak ada selain itu.
Pembelajaran-pembelajaran sejarah sekalipun di sekolah, hanya dipelajari penuh hafalan. Ia hanya ditempatkan sebgai pengetahuan akan peristiwa masa lalu, yang bahkan terpisah-pisah. Bukan sebagai pemahaman, yang memiliki keterkaitan dasar satu sama lain. Pembelajaran sejarah tidak mengajarkan pelajar untuk “belajar” dari sejarah, termasuk menemukan pertautan kebangkitan bangsa kita dengan tradisi literasi.
Aku menulis maka aku ada
Di tingkat kesadaran personal, ada banyak alasan untuk menulis. Tidak hanya belajar menstrukturkan pikiran, juga kebutuhan psikologi di tengah interkasi sosial yang serba pragmatis, “mengeringkan” kehidupan. Menulis menjadi jalan semedi bagi sebagian manusia.
Selain itu, sebagian menempatkan menulis syarat untuk menegaskan realitas ke’aku’an. Apa lagi di era media sosial sekarang ini.