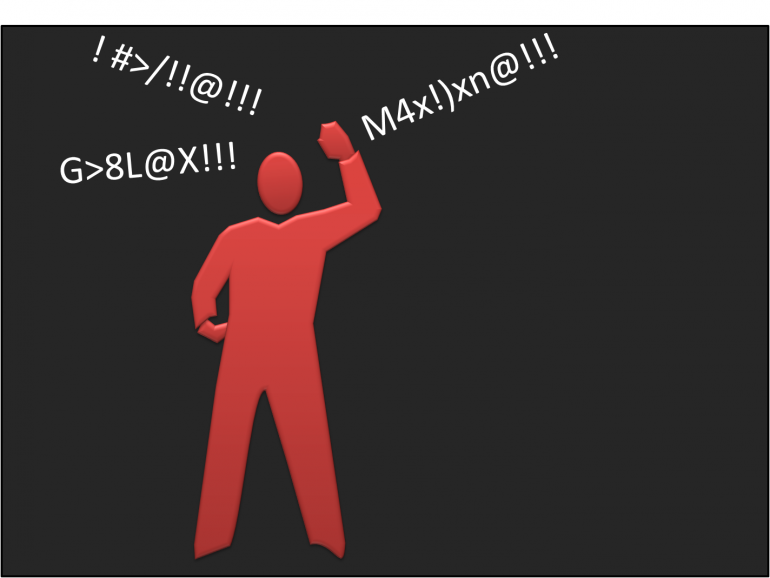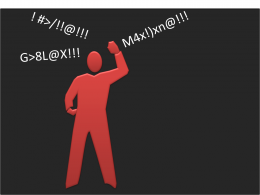Kebebasan berpendapat adalah sebuah privelese baru bagi warga bangsa Indonesia paska reformasi 1998. Sesuatu yang sebelum itu hanya bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, (dan betul) berkeringat dingin dan degup jantung di atas normal. Memang kebebasan berpendapat dicantumkan sebagai hak asasi manusia dalam deklarasi universal PBB.
Berbagai fenomena dan kejadian yang bermunculan beberapa waktu terakhir ini membuat saya menduga bahwa mungkin kita tidak cukup perduli tentang bagaimana kebebasan berpendapat seharusnya diselenggarakan atau diwujudkan. Karena, biarpun saya bukan ahli hukum atau tata pemerintahan, tetapi ketika saya membaca UU tersebut saya menganggap bahwa para pembuatnya telah berpikir keras disertai dengan empati yang dalam kepada semua pihak yang terkait dengan hak tersebut.
Sebuah kalimat yang menyentuh saya adalah:
mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945
Setiap HAK harus selalu disertai dengan KEWAJIBAN untuk bertanggung-jawab, karena itu pemerintah negeri ini memfasilitasi hak asasi ini dalam undang-undang no. 9 TAHUN I998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hak tanpa kewajiban adalah tirani.
Dulu di SMP saya pernah diajari bahwa syarat berdirinya sebuah negara ada 3: punya kedaulatan, punya wilayah, ada rakyatnya. Ketiadaan satu syarat saja akan membuat keberadaan sebuah negara menjadi tidak valid.
Kedaulatan dengan akar kata "daulat" berarti kekuasaan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara disebut penguasa, karena kekuasaan adalah sarana yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan amanat yang dibebankan rakyat kepadanya. Tanpa adanya kekuasaan, keteraturan dan ketertiban yang dibutuhkan untuk sebuah proses penyelenggaraan negara tidak akan dapat berlangsung efektif. Di sisi lain, kedaulatan membutuhkan kewibawaan. Kekuasaan tanpa kewibawaan adalah sesuatu yang aneh. Karena itu, untuk menjaga kedaulatan negeri ini mereka dilengkapi dengan instrumen-instrumen penegakan kedaulatan seperti tentaranya, dan hukum, seperti polisi, dan aparat pemerintah yang lain.
Namun jangan abai, bahwa Pemerintah kita, adalah sebuah entitas legal formal yang terbentuk dari beberapa sosok manusia. Sebagaimana umumnya manusia, mereka secara individu maupun kolektif juga tidak terlepas dari kekeliruan dan kesalahan. Karena itu, sistem pemerintahan dan tata-negara memberikan mekanisme untuk kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan melalui perwakilannya. Bahkan, selain itu, warga masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara publik, termasuk untuk meng-KRITIK Pemerintah sebagai kontrol publik terhadap para eksekutifnya..
Disisi yang lain, KRITIK (menurut KBBI) memiliki dua arti yaitu: kecaman atau tanggapan. Tetapi yang namanya kritik lebih lekat dengan makna kecaman, apalagi dalam konteks "Kritik Kepada Pemerintah." Tentunya kritik kepada PEMERINTAH seharusnya berbeda dengan kritik tentang rasa baso Pak Kumis di lapangan Blok S, Jakarta Selatan.
Karena kritik lebih berkonotasi kecaman, maka penyampai kritik kepada pemerintah seharusnya memperhatikan tata-caranya sebagaimana telah wujud dalam undang-undang tadi. Namun lebih dari itu, budaya kita yang ramah penuh sopan-santun, seharusnya juga menjiwai prosesnya. Seharusnya tujuan menyampaikan kritik adalah untuk perbaikan. Yang penting adalah hasilnya. Namun bilamana proses kritik tidak dilakukan dengan bertanggung jawab, mungkin tujuan dari kritik tersebut tidak akan pernah tercapai. Mungkin tercapai, tetapi dengan biaya yang luar biasa besarnya sehingga tidak sepadan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Sungguh saya heran dengan bahasa tubuh para penyampai pendapat di muka umum, suara lantang, kepalan tangan - seolah-olah ingin berperang. Siapa musuhnya, Bang?! Padalah, kritik, sebagai kecaman atau tanggapan, paling banter adalah sebuah counter pendapat, umumnya dicirikan dengan kesimpulan "Seharusnya.....!". Pendapat kita bisa agak benar, dan mungkin sangat salah.