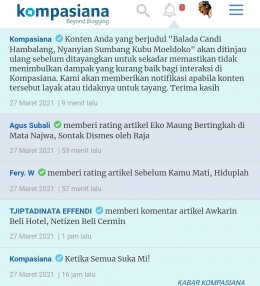Hai, Diari.
Aku berharap pagi ini suasana hatimu sedang adem. Kalau tengah panas, maaf, aku batal menulis luapan gundah di hatiku. Terus terang saja, Diari. Tidak perlu memendam dongkol, tidak usah menyembunyikan kesal. Nanti kamu makan hati, lalu sakit hati, lalu psikosomatik.
Jika hatimu sedang adem, kedipkan matamu satu kali. Kalau tengah panas, kedipkan berkali-kali. Oh, hanya sekali. Hatimu sedang adem atau tengah ganjen? Hahaha. Bercanda, Diari.
Begini, Diari. Kamu pasti tahu aku sudah lima tahun mengontrak kamar literasi di flat Kompasiana. Ya, sejak 16 Februari 2016. Lama juga, ya? Aku betah. Itu alasan mengapa aku bisa bertahan lama. Luar biasa. Padahal, aku ini tergolong umat angin-anginan.
Aku betah di Kompasiana bukan lantaran banyak yang membaca tulisan saya, Diari. Tidak begitu. Maksud saya, bukan hanya itu. Pembaca almarhum blog pribadi saya juga bejibun. Apalagi jika sudah mengudar politik termutakhir, bahasa Indonesia, dan trik menulis.
Namun, Kompasiana sungguh berbeda. Aku betah di sini karena aku merasa nyaman. Ada interaksi yang asyik dan mengasyikkan dengan sesama penghuni kos-kosan. Aku sebut kos-kosan lantaran aku bayar sewa, lo. Lumayan, premium bisa menjegal iklan kutil berkeliaran di monitor laptop.
Pagi ini aku sedikit sewot, Diari.
Bayangkan, satu artikelku masuk kandang. Macam ternak yang akan diperiksa punya bibit kuman atau tidak. Itu manusiawi. Pengelola kos-kosan bernama Kompasiana tentu berhak menata dan mengatur lalu lintas artikel. Jika ada yang terindikasi berkuman, karantina. Tidak apa-apa, asal jelas alasannya.
Pada awalnya aku jengkel. Bukan apa-apa, artikel kutulis setelah pontang-panting mencari data. Data dapat, aku masih harus memikirkan sudut pandang tilikan. Tilikan ketemu, aku mesti ubek-ubek otak. Setelah kelar, artikel itu kuunggah di Kompasiana.
Apa lacur, Diari, artikelku dipeluk mesin pemeriksa. Remuk. Bung Hatta, Buku dengan Halaman Terbuka yang Tak Kunjung Kelar Dieja. Dari notifikasi yang masuk, aku tahu alasan si robot. Ya, artikel itu mengandung kata atau kalimat yang dilarang di Kompasiana.
Kalau Kasino yang membaca notifikasi itu pasti bakal terperangah, lalu berkata, "Gile lu, Ndro!" Artikel itu mengudar kejujuran Bung Hatta yang patut kita tiru. Tidak ada serangan personal, tidak ada kalimat vulgar, tidak ada alinea taksa. Semuanya terang benderang.
Tahu-tahu, Diari, artikel itu tayang sendiri tanpa notifikasi seperti yang telah dijanjikan. Pendek kata, muncul seperti hantu yang tidak ketahuan dari mana asalnya. Momentum sudah lewat. Ya, tetap ada yang membaca artikel itu, tetapi sudah lewat dari target tayang.

Ndilalah, Diari, masuk karantina. Lucunya, artikel itu muncul tanpa pemberitahuan. Janji pengelola tidak terpenuhi. Artikel nongol di Pulau Entah-berentah. Tidak ada waktu tayang. Tidak ada di rubrik Terbaru, Pilihan Editor, atau Politik. Bahkan, tidak ada di profil akunku.
Aku tahu artikel itu tayang karena aku membaca cuitan Admin Twitter Kompasiana. Artikel itu kontan saya hapus. Tidak jelas.

Jika dulu menggunakan alasan "mengandung kata atau kalimat yang dilarang di Kompasiana", kini tidak lagi. Alasannya diganti dengan "sekadar untuk memastikan tidak menimbulkan dampak yang kurang baik bagi interaksi di Kompasiana".

Kalau dulu tidak jelas kriteria kata atau kalimat yang dilarang, sekarang tidak terang apa yang tergolong dampak kurang baik bagi interaksi di Kompasiana. Berbeda, Diari, tetapi mirip. Apa kemiripannya?
Pertama, sama-sama tidak jelas. Pendek kata, hanya pengelola Kompasiana dan Tuhan yang tahu alasannya. Kompasianer manut saja. Anak kos-kosan memang mesti menurut. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya.
Kedua, sama-sama tidak jelas. Pendek kata, hanya pengelola Kompasiana dan Tuhan yang tahu alasannya. Kompasianer manut saja. Anak kos-kosan memang mesti menurut. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya.
Ketiga, sama-sama tidak jelas. Pendek kata, hanya pengelola Kompasiana dan Tuhan yang tahu alasannya. Kompasianer manut saja. Anak kos-kosan memang mesti menurut. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya.
Itulah tiga persamaan dari dua alasan pengelola Kompasiana.
Plis, Diari. Tolong berhenti meminta agar aku berpikir positif. Otakku juga berhak berpikir negatif. Kamu kira pengacara dan jaksa berdiri di pengadilan atas dasar berpikir positif saja?
Satu-satunya hal positif yang kupikirkan sekarang adalah masih banyak Kompasianer yang suka berinteraksi denganku. Itu alasan kuat bagiku untuk bertahan menulis di Kompasiana.
Jadi, Diari, biarkan aku berpikiran kotor. Eh, berpikiran negatif! [kp]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H