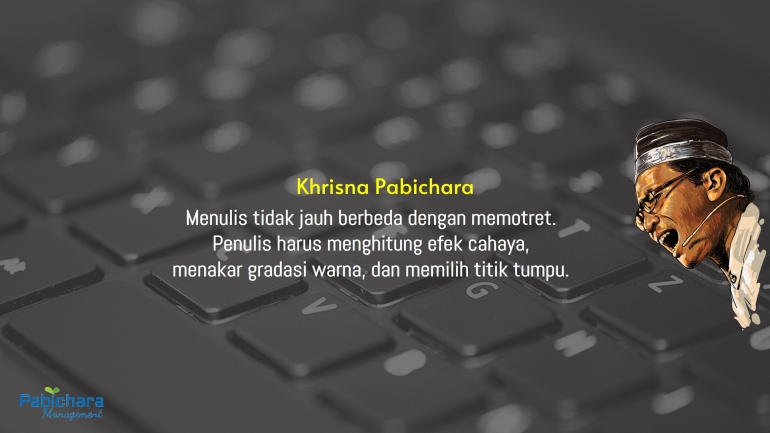PADA akhir November 2011, pada subuh yang dingin, pada kota besar yang lengang, pada ruang lapang di Monumen Nasional, saya terpaksa mengusir kantuk. Masih pukul lima. Orang-orang sibuk berlari, bersenam, dan berolahraga ringan.
Dahlan Iskan. Saya belum pernah bertemu dengan beliau. Sekali pun belum pernah. Namun, pagi itu saya mesti bertemu dengan beliau dan harus mampu meyakinkan beliau. Raja media dari Surabaya yang saat itu menempati posisi Menteri BUMN tengah bersenam.
Setelah beliau selesai, semasa keringat masih mengucur, asisten beliau mengantar kami lebih mendekat. Sang asisten memperkenalkan saya selaku penulis dan Deden Ridwan dari penerbit (Mizan Grup). Ia juga menjelaskan niat kami untuk menemui Pak Dahlan--belakangan hari saya menyapa beliau dengan sebutan Abah.
"Kenapa harus saya?" Itu pertanyaan pertama yang meluncur dari beliau. "Banyak sosok lain di negeri ini yang layak dibukukan, dibuatkan memoar, atau dituliskan kisah hidupnya."
Saya kontan menjawab, "Ada banyak inspirasi dari perjalanan hidup Bapak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jika Bapak mengizinkan, saya ingin menulis perjalanan hidup Bapak dengan gaya saya, pendekatan saya, dan kemasan sesuai kebiasaan saya."
Beliau tertawa sambil menyeka keringat. Dari tawanya saya simpulkan, beliau ramah. Dan, amat hangat. "Silakan ikut saya!" Kata beliau sambil berjalan. Langkahnya ringan dan cekatan.
Saya harus menahan napas berkali-kali, melompat agar tidak tertinggal, dan ngos-ngosan. Sang asisten dan Kang Deden naik lift. Saya juga ditawari, tetapi saya ingin menjajal naik ke lantai 19 lewat tangga. Di depan saya, Pak Dahlan berjalan dengan napas kuda. Takada lelahnya. Saya, di belakang beliau, mulai merasakan lutut gemetar ketika tiba di lantai 11. Masih delapan lantai.
Keringat mengucur. Baju di bagian punggung berasa lengket ke kulit. Lutut goyah. Betis pejal. Dan, masih tiga lantai. Pucuk dicinta ulam tiba. Pak Dahlan berhenti, berbalik, tersenyum. Lalu duduk begitu saja di lantai. Ingatan saya sontak memajang sosok almarhum ayah saya.
"Anda tahu saya juga sering menulis, kan?"
Saya mengangguk. "Tahu, Pak. Saya paling suka Ganti Hati. Menyentuh!"
"Bisa saja saya tulis sendiri biografi saya," ujar Pak Dahlan sambil tersenyum.
Saya menyanggah dengan santun. "Gaya Bapak berbeda dengan gaya saya."
Beliau tertawa lagi. Berdiri sambil berkata, "Saya hanya membantu agar Anda bisa bernapas lega!"
***

Pengalaman lutut goyah sungguh berguna. Presentasi soal apa yang akan saya tulis, bagaimana nanti proses riset, dan hal-hal teknis lain hanya pelengkap belaka. Saya tahu itu, sebab ketika tiba di lantai 19, sebelum memasuki ruangan beliau, pundak saya ditepuk sangat hangat.
Mengapa harus saya? Itulah pertanyaan yang kerap diajukan oleh seseorang tatkala saya tawari dituliskan memoar atau biografi. Jawaban yang sering saya lontarkan ialah agar cucu dan cicit kenal leluhurnya. Betapa banyak di sekitar kita yang kenal kakeknya sekadar nama saja. Tidak tahu kiprah sang kakek, tidak kenal jejak sang kakek.
Adakah yang lebih mengenaskan dibanding tidak dikenali oleh kerabat sendiri? Bahwa tiap insan adalah guru, itu benar. Bahwa tiap orang punya pengalaman inspiratif yang bisa disebar kepada khalayak pembaca, itu benar. Namun, dilupakan oleh keluarga sendiri adalah alasan sederhana mengapa seseorang butuh memoar.
Anda boleh punya uang berlimpah, perusahaan menumpuk, deposito di mana-mana, saham tiada terkira, selama Anda hanya bergerak di situ maka suatu ketika nama Anda akan hilang dari edar masa. Lewat buku, setidaknya, nama Anda akan mengabadi selama buku itu ada.
Anda boleh punya jabatan tinggi, pangkat yang membuat orang lain terus membungkuk, telunjuk yang dapat menggerakkan dan mengarahkan orang lain, selama Anda berada di situ saja maka suatu ketika nama Anda akan ditelan masa. Bukulah yang dapat, setidaknya, mengabadikan apa yang telah Anda lakukan, kapan Anda berbuat, dan bagaimana Anda melakukannya.
Di situlah pentingnya buku biografi atau memoar.
***

Kedua, disenangi pembaca. Tidak sedikit orang yang senang membaca kisah hidup orang lain. Jadi, penyebaran gagasan sebenarnya adalah aksi cerdas untuk menularkan visi, falsafah, dan nilai kehidupan. Dari sana, pembaca bisa menarik simpul faedah.
Jika Anda pernah membaca Sepatu Dahlan, sejatinya novel tersebut adalah biografi Dahlan Iskan. Kemasannya berbentuk novel, bangunan ceritanya tetaplah apa yang pernah dialami oleh Dahlan kecil dan Dahlan remaja. Itulah biografi pertama yang saya anggit.
Saya menyebutnya: novel biografis. Ada bangunan fakta, ada bubuhan fiksi. [kp]
Catatan: Tulisan ini adalah serial "Menulis Biografi" yang saya taja atas permintaan beberapa pihak setelah saya menganggit artikel tentang pengalaman saya menulis buku biografi. Semoga berguna.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H