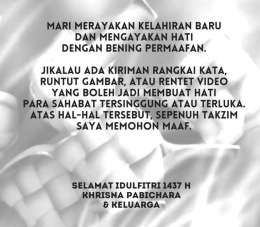Tepat ketika Syawal tiba, mata saya belum juga dipeluk kantuk. Alih-alih redup, mataku malah makin cerah. Sebuah pertanyaan gara-garanya. Sudah berapa kali selama hidup saya bertemu Lebaran dan mengucap, atau mendengar, kalimat "mohon maaf lahir dan batin"?
Saya bingung menghitungnya. Mengapa? Karena frekwensi pelafalannya ditentukan oleh seberapa kerap saya bertemu orang atau bertamu ke rumah sahabat dan kerabat. Dalam sekali Lebaran bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Kecuali kalau saya sederhanakan atau bulatkan menjadi satu kali setiap Lebaran. Itu berarti saya sudah mengutarakan kalimat sarat muatan emosi itu sebanyak 81 kali. Dengan perincian 41 kali untuk Idulfitri dan 40 kali buat Iduladha.
Lantas apa yang membuat batin saya tertegun, sampai-sampai melupakan kopi dan makanan pemantik air liur di dapur? Maaf, tolong jangan mendesak saya. Permenungan ini tualang spiritual belaka. Atau sebut saja hiburan batin. Tidak perlu mengerutkan kening, apalagi memeras pikiran. Santai saja. Izinkan saya menarik napas dulu. Begini, Kawan, yang sedang saya renungkan adalah: Apakah 81 kali pertemuan dengan kalimat itu betul-betul permaafan secara lahir dan batin?
Maaf secara lahir berarti saya melafalkan kalimat sakral itu secara sadar dan sengaja kepada siapa saja, yang pada saat bersamaan saya ucapkan dengan tulus di dalam batin. Hal sama berlaku apabila ada orang lain yang mengucapkan kalimat itu dan, tentu saja, ditujukan kepada saya. Secara lahir akan saya maafkan dan secara batin pun seyogianya demikian. Harus luruh seluruh amarah, mesti luluh semua benci. Semuanya. Tak boleh ada sisa. Selama masih bersisa, berarti belum tulus. Apabila saya hanya memaafkan secara lahir, berarti batin saya bermasalah. Nah, loh!
Hanya saja, hati kecil saya seketika bertanya-tanya. Adakah saya benar-benar sudah dimaafkan lahir-batin? Apakah saya betul-betul memaafkan lahir-batin? Jangan-jangan permaafan saya, juga mereka, cuma permaafan sejenak; jangan-jangan tidak tulus atau sekadar menyenang-nyenangkan hati; jangan-jangan tanpa sengaja saya sudah menzalimi mereka dan diri sendiri; jangan-jangan....
Lebih membingungkan lagi, selama ini saya banyak menebar kesalahan, baik lewat kata maupun gambar, di media sosial. Saya pernah merisak orang—termasuk pejabat atau tokoh publik—di twitter, pernah meledek teman di fesbuk, pernah mengusili kawan di instagram. Belakangan mulai menulis dan berkomentar macam-macam di Kompasiana. Sebagai orang yang doyan bersenda gurau, saya kadang melakukannya sebagai upaya bercanda agar jalinan pertemanan lebih akrab. Namun, si tertuju risakan, ledekan, atau usilan itu belum tentu beranggapan sama. Boleh jadi mereka tersinggung dan memendam bara kecewa di dada.
Bukan hanya itu, ada yang lebih bikin berdiri bebulu di tengkuk. Ada sahabat yang saya blokir atau saya hentikan pertemanan di path, facebook, atau twitter. Sebenarnya sah-sah saja. Toh media sosial menyediakan sarana untuk melakukan hal-hal seperti itu. Akan tetapi, bagaimana kalau mereka tersinggung, terluka, marah, atau kecewa? Apakah permintaan maaf lewat kata atau gambar yang saya sebar di media sosial sudah mencukupi? Apakah mereka mau memaafkan saya? Untung kalau pihak yang terluka itu membaca permintaan maaf saya dan berlapang dada memaafkan keusilan saya. Bagaimana kalau sebaliknya?
Duh, saya makin bingung. Bagaimana jika ternyata sekarang, beberapa saat menjelang pesta permaafan dan pembeningan hati kita rayakan, kalian malah ikut bingung gara-gara tulisan ini, lalu kesal lalu sewot lalu bertambah lagi kesalahan saya? Butuh berapa kali pertemuan lagi dengan "mohon maaf lahir-batin"?
Sekali lagi, Kawan, maafkan saya. Maaf lahir pun cukuplah, apalagi kalau sekalian maaf batin. Kalian masih punya banyak cadangan maaf di gudang perasaan, bukan? [kp]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H