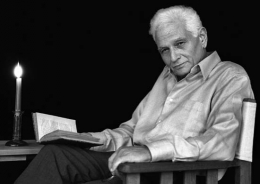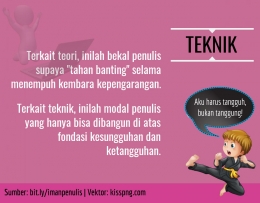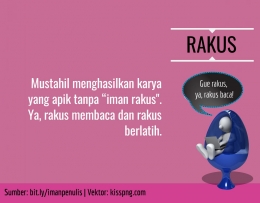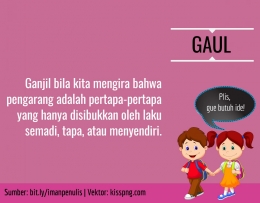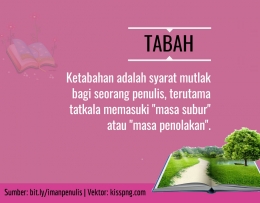Sebagai teks, karya sastra hanyalah jejak. Bekas telapak kaki. Di dalamnya, pembaca harus menemukan manusianya.~ Jacques Derrida (1976: 167)[1]
Sesuai dengan judulnya, Rukun Iman Penulis, maka hal-hal pokok yang didedah dalam tulisan ringan ini semata-mata buat menggelitik kesadaran dan keyakinan yang, seyogianya, dimiliki oleh siapa saja yang berminat, berkhayal, atau berharap menjadi penulis.
Bekal kesadaran dan keyakinan itu berangkat dari pengalaman pribadi dan sari dari bacaan-bacaan yang mengulas dan mengupas bagaimana seseorang bisa menjadi penulis, terutama prosa. Dengan demikian, tulisan ringan ini bukan sejenis kitab suci yang sakral dan tidak boleh diutak-atik, melainkan sejenis kendaraan umum yang cuma bisa mengantar ke terminal tertentu.
Di Indonesia, menjadi penulis belum diletakkan sebagai profesi yang sederajat dengan guru, dokter, karyawan, atau pekerjaan lain yang diakui sebagai penanda status kewarganegaraan. Penulis masih diduga sebagai “titisan dewa” yang menghasilkan karangan karena “desakan dari dalam” atau “panggilan nurani akibat masalah dan peristiwa di sekitar yang harus diurai-tuliskan”.
Lantaran itu pula, tidak banyak orang yang bernyali gede berani menceburkan diri ke dalam samudra kepenulisan secara menyeluruh. Menulis masih dianggap sebatas pekerjaan sambilan, profesi paruh waktu, atau sekadar pertaruhan gengsi. Padahal, pada beberapa negara di luar Indonesia, penulis benar-benar sebuah profesi. Pekerjaan yang menghasilkan, yang dihargai. Akibatnya, tak sedikit orang di Indonesia yang menduga bahwa bekal menjadi penulis itu hanya satu: bakat.
Alhasil, kita mengira kepenulisan memang sejalan dengan “kenabian”—yang pada tataran tertentu bekerja karena wangsit atau wahyu. Tentu sah saja anggapan yang demikian. Akan tetapi, apabila terus demikian, kita tidak akan pernah memandang kepenulisan sebagai dunia keilmuan, sesuatu yang bisa dipelajari, dilatih, dan diasah, sama seperti keterampilan merakit roket, menyusun bata, atau menggocek bola.
Benar, bakat dapat menentukan keberhasilan seseorang menjadi penulis. Hanya saja, menulis bukanlah melulu bakat. Seberapa murni kadar bakat menulis seseorang tidak akan berkilau selama ia tidak memiliki kegigihan dan kemauan kuat untuk terus mengasah kemampuan.
Dengan pertimbangan bahwa menulis itu bisa dipelajari dan dapat pula dijadikan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarga, perlulah diperbanyak kegiatan sejenis ini: bertemu dengan penulis dan mempelajari riwayat kepenulisan mereka.
Itu pula sebabnya tulisan ini dijuduli Rukun Iman Penulis—rukun yang harus diimani oleh siapa saja yang ingin menjadi penulis. Termasuk, boleh jadi terutama, penulis prosa.
Mengapa Harus Ada Rukun Iman Penulis?
Hasan Aspahani, dalam sebuah perbincangan santai di Batam, membutuhkan waktu lama hingga puisi-puisinya berhasil menembus rubrik sastra di koran-koran nasional.
Tersebut pula kepedihan Rowling menembus penerbitan demi novel fantasi yang baru rampung ditulis olehnya. Tidak hanya satu penerbit yang menolak naskahnya, tetapi puluhan. Bahkan, tersiar kabar bahwa Joni Ariadinata sempat berniat melupakan dunia cerpen karena karangan-karangannya tak kunjung bertemu media sejodoh, sedang hidup terus berjalan.
Belum lagi Muhidin M. Dahlan yang akhirnya mengubur hasrat menulis novel akibat Adam dan Hawa yang menuai banyak kecaman.
Ada banyak pengalaman yang bisa disuguhkan sebagai contoh dan tulisan ini akan menjadi sangat panjang. Ada yang kemudian “bertemu jodoh” dan tetap bersetia dengan laku kepenulisan. Damhuri Muhammad, misalnya. Ada pula yang hilang dan tak ditemukan lagi jejak karyanya.
Baik yang bertahan maupun yang akhirnya “hilang” mengalamatkan bahwa dunia menulis itu bukan alam mulus. Akan banyak perintang sepanjang perjalanan: dari masyarakat, kerabat, dan diri penulis itu sendiri.
Agar bisa bertahan menghalau perintang-perintang itu dibutuhkan “iman yang kuat”. Iman yang tidak gampang goyah, apalagi dirobohkan. Makin kuat iman itu mengakar di kedalaman jiwa, makin ulet seseorang menempuh jalan kepengarangannya.
Iman itu perlu, sangat perlu. Dalam keyakinan Walter Scott, “Bila seseorang ingin menaiki sebuah tangga, ia harus mulai dari anak tangga pertama.”
Tidak seorang penulis pun yang sekonyong-konyong bisa menghasilkan karya bernas. Ibarat menapak tangga, mereka melampaui banyak proses—sebagian besar “berdarah-darah”. Dan, tangga pertama yang harus dilaluinya adalah “beriman”.
Inilah Rukun Iman Penulis Itu
Sepanjang manusia memerlukan keseimbangan antara pertumbuhan jiwa dan jasmani, juga kepuasan jasmani dan rohani, sepanjang itu pula manusia membutuhkan karya seni—termasuk di dalamnya karya sastra. Dengan demikian, kebutuhan manusia atas karya sastra akan selalu ada.
Guna memenuhi kebutuhan itu, kehadiran pengarang amat penting dan akan selalu dirindukan oleh khalayak penikmat. Lantaran kebutuhan itu mengabadi, maka masing-masing penulis mesti menyadari bahwa mereka harus selalu bergerak, bergeliat. Mereka tidak boleh statis di tempat yang sama. Kualitas karya harus ditingkatkan adalah sebuah keniscayaan.
Oleh karena itulah dibutuhkan “iman”.

Kita bisa belajar pada John Ernst Steinbeck, novelis yang karya pertamanya, Cup of Gold, ditolak oleh tujuh penerbit.[2] Ia tidak patah arang. Ia terus menulis dan mencoba bertahan hidup sebagai sopir, tukang kayu, tukang batu, bahkan buruh pemetik buah.
Nasibnya berubah tatkala buku ketiganya, Tortilla Flat (1935)—diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Djoko Lelono dengan judul Dataran Tortilla—diterbitkan dan “mengguncang” dunia. Namanya pun berkibar, nasib baik terus menemaninya. Pada 1962, Steinbeck menerima anugerah Nobel Sastra. Bekal iman yang kuat membuat Steinbeck mampu bertahan dan bisa melewati masa-masa sulit dalam hidupnya.
Bukan sekadar kegigihan berkarya yang dibutuhkan oleh setiap pengarang, melainkan juga ketabahan tatkala diterpa “ujian” dan “pujian”. Ujian berupa kritik kadang memerahkan telinga, pujian berupa sanjungan sering melenakan hati. Bekal mental akan menguatkan penulis agar tetap tegar.

Dalam istilah Damhuri Muhammad, harus diperlakukan seperti membikin layang-layang: ditaksir, diraut, ditimbang, dipermak, kemudian diterbangkan. Namun, sedapat-dapatnya, kita tidak tergesa-gesa memajang karya di blog atau mengirimkan ke media koran atau majalah sekadar untuk memuaskan hasrat keterbacaan.
Di sinilah letak pentingnya penulis, terutama penulis prosa, mengedepankan teori. Mempelajari teori tak berarti harus patuh, taat, dan tunduk pada aturan yang ada, tetapi supaya tahu cara semestinya dalam menumpahkan imajinasi.
Teori menulis, barangkali sejalan dengan teori membuat layang-layang ala Damhuri tadi, dibutuhkan agar kita tahu perbedaan antara tokoh dan penokohan, alur dan alir, plot dan jalin kisah. Teori juga kita butuhkan biar kita melek pada gaya bahasa. Setelah itu, mudahlah bagi setiap orang untuk “tahan banting” di kembara kepengarangan.
Terkait teknik, butuh kesungguhan bagi penulis untuk terus belajar. Bisa dengan membaca karya-karya sastra yang “diakui oleh dunia”, bisa pula dengan menimba ilmu langsung kepada mereka yang sudah “benar-benar” pengarang. Dalam hal ini, “benar-benar” dimaknai sebagai “sungguh-sungguh”.

Semasa saya menulis Arajang, butuh riset berbulan-bulan di tengah para bissu—tokoh adat bertubuh lelaki berwatak perempuan di suku Bugis—dan penelitian mendalam di perpustakaan. Apalagi menulis Natisha, butuh belasan tahun.
Pendek kata, kedalaman makna dalam cerita selalu berkait-paut dengan kapasitas intelektual yang dimiliki oleh pengarangnya.
Ada cerita biasa dan kerap terjadi di sekitar kita, tetapi jadi begitu bernyawa karena tiba di tangan penulis yang tepat. Kuntowijoyo, misalnya. Bagi generasi yang mengalami represi Orde Baru tentu memahami betapa kuatnya tekanan penguasa. Akan tetapi, di tangan Kuntowijoyo lewat cerpen-cerpen dan novel-novelnya, menjadi berbeda. Lebih bernyawa.
Dengan demikian, wajar bila kemudian penulis meyakini bahwa kecendekiaan dan kepengarangan adalah dua sisi uang logam yang tak terpisahkan.

Apabila atlet menjadikan latihan sebagai makanan pokok dan vitamin sebagai asupan tambahan bagi kemajuan prestasinya, hal sama berlaku bagi penulis. Menulis kita anggap sebagai latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan, membaca adalah vitamin yang membuat “tubuh cerita” lebih kokoh.
Lewat aktivitas membaca akan tertemu rahasia menjalin alur cerita, mencipta tokoh, atau mengulik peristiwa. Kita bisa pula merekam banyak gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang lain, hingga pada muaranya kita akan bersua dengan gaya bahasa kita sendiri.
Singkat kata, mustahil menghasilkan karya yang apik tanpa “iman rakus baca”.

Guntur Alam, seorang cerpenis, malah kerap menemukan karakter tokoh lewat teman seperjalannya di kereta. Bamby Cahyadi, juga seorang cerpenis, kerap menemu plot dari peristiwa yang terjadi di restoran cepat saji tempatnya bekerja.

Kadang kala ada tulisan kita yang ditolak oleh media massa atau penerbitan. Pada saat seperti itu tidak usah bermuram durja. Kirim lagi naskah itu ke tempat lain. Bisa jadi penolakan terjadi lantaran karangan itu tak cocok dengan misi media massa atau penerbitan yang menolak, namun pas dengan selera media massa atau penerbitan yang lain.
Banyak yang pernah mengalami hal sedemikian. Ada cerpennya yang ditolak oleh sebuah koran, kemudian ia kirim ke koran lain. Tiga pekan kemudian, cerpen yang pernah ditolak itu hadir ke tengah khalayak.
Pada Akhirnya…
Perlu disadari, “beriman” saja belumlah cukup bagi seorang (calon) pengarang. Ada hal lain yang mesti dilakukan setelah kita beriman. Namanya, “beribadah”.
Bersyukurlah kita karena tak perlu berpayah-payah mengguratkan ide di permukaan “batu tulis”, atau kerap dinamai sabak. Beruntunglah kita karena teknologi telah menghadirkan sabak dalam bentuk lain, yakni sabak elektronik (baca: gawai).
Lebih bersyukur dan beruntung lagi karena kita tidak harus berpayah-payah menulis di lembaran daun lontar. Sekarang kita punya kertas dan mesin cetak. Begitu ada ide, jalan ibadah sudah sedemikian mudah. Tinggal tanak, olah, dan racik.
Persoalan baru yang bakal muncul adalah seberapa tekun kita “beribadah”! [kp]
Catatan:
[1] Of Grammatology, Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
[2] Beberapa karya Steinbeck telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain Dataran Tortilla yang diterjemahkan oleh Djoko Lelono, karya lainnya adalah Cannery Row (2001, oleh Eka Kurniawan), Tikus dan Manusia (1950, oleh Pramoedya Ananta Toer dari Of Mice and Man). Selengkapnya bisa dilihat dalam Ensiklopedi Sastra Dunia karya Anton Kurnia, diterbitkan oleh Indonesia Buku pada 2006, halaman 189.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H