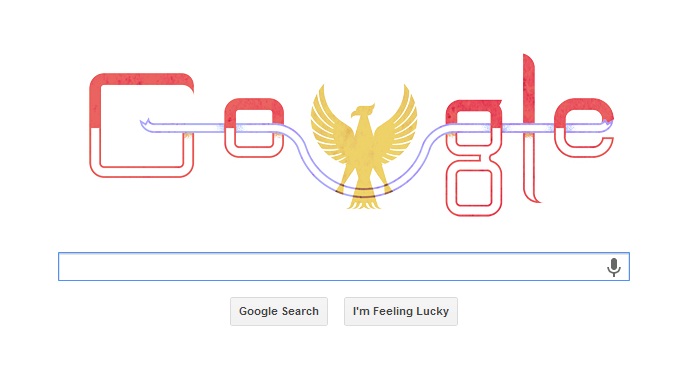Tampilan google.com doodle hari ini: [caption id="attachment_281328" align="aligncenter" width="690" caption="(google.com)"][/caption]
Merdeka!
Ada satu bagian dalam sajian Francis Fukuyama melalui bukunya The End of History and The Last Man yang begitu tertanam kuat di benakku ketika membacanya, yaitu simpulan essay Immanuel Kant, sang filsuf Jerman termasyur bahwa sejarah universal tidak lain adalah progres kesadaran tentang kemerdekaan/kebebasan (freedom).
Menurut Kant, sejarah memiliki akhir yaitu ketika kemerdekaan/ kebebasan manusia telah terealisasi. Terlepas dari bahasan tulisannya yang juga menyangkut soal hukum dan institusi negara, saya tertarik merenungkan sepotong simpulan diatas.
Dulu ketika “Indonesia” dijajah Belanda, Indonesia dalam tanda kutip karena Indonesia baru lahir setelah tahun 1900-an, saat Belanda pertama kali memasuki kawasan ini, yang ada adalah negara Mataram, negara Badung, Aceh, Banjar, Gowa, Ternate, dan lain-lain. Diantara negara-negara tersebut jelas sekali tidak ada perasaan satu bangsa sebagaimana yang belakangan terjadi pada Indonesia. Bahkan ada periode dimana terjadi perang antar negara/kerajaan dengan pihak kalah pada akhirnya menjadi jajahan. Ketika Pangeran Diponegoro ditangkap VOC, beliau tidak perlu diasingkan jauh-jauh, cukup di Makassar saja sudah asing. Begitu juga dengan Cut Nyak Dien, cukup diasingkan di Sumedang. Contoh nyata betapa saat itu, kata asing cukup menggambarkan hubungan politik antara negara-negara tersebut.
Lalu mengapa kemerdekaan yang diperingati adalah kemerdekaan dari penjajahan Belanda? Seorang kawan pernah menuliskan di sebuah forum facebook tentang sejarah yang anti. Bahwa sejarah yang anti itu adalah sejarah yang negatif. “Sejarah juga tidak dapat disusun sebagai anti. Sejarah yang anti berarti sejarah yang belum tulus menerima masa lalu sebagai sebuah kejadian yang sudah terjadi. Dia dibangun diatas pertentangan nilai-nilai dan karena itu menyimpan luka. Ketika dua posisi dibandingkan maka orang selalu mencoba membandingkan dengan sesuatu yang menjadi padanannya atau lebih tinggi dan karena itu sejarah yang anti berarti selalu memosisikan diri dibawah yang di anti-kan. Itu adalah sejarah yang negatif.” Demikian tulisnya secara lengkap.
Apakah betul kita merdeka dari Belanda? Bagi saya berkaca pada tulisan Kant dan komentar kawan diatas, yang lebih tepat dan positif adalah bahwa kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 itu adalah kemerdekaan dari hilangnya hak untuk menentukan nasib sendiri di tanah yang dianugerahkan Sang Khalik kepada nenek moyang kita turun temurun, kemerdekaan dari hilangnya hak untuk menentukan sendiri hukum dan pemimpin yang diinginkan, kemerdekaan dari hilangnya hak untuk hidup sesuai hasrat, kemerdekaan dari hilangnya hak untuk setara, kemerdekaan dari segala hak yang hilang oleh penjajahan.
Belanda (VOC) menjadi populer sekali karena dalam penjajahan Belandalah, semua negara-negara yang terbentang dari Aceh hingga Papua berhasil ditundukkan oleh Belanda dan disatukan dibawah administrasinya. Kecuali Timor Timur yang tetap dibawah kekuasaan Portugis. Kesatuan tersebutlah yang menimbulkan perasaan senasib, tetapi bukan sebangsa sampai proses-proses yang terjadi saat-saat itu menciptakan sebuah identitas baru: Indonesia. Bangsa Indonesia. Negara Indonesia.
Penyebutan dan pengekalan tokoh antagonis Belanda dalam sejarah kita, boleh jadi sesuai dengan renungan sang kawan diatas, merupakan sebuah sejarah yang anti. Ada pertentangan nilai-nilai yang terlibat didalamnya yang begitu sulit dilupakan yang membuat kita terkunci hanya pada pelaku-pelaku dan nilai-nilai materiil semata dan melupakan sesungguhnya kita merdeka dari apa, bukan dari pihak-pihak tertentu. Trauma yang membekas tak mungkin luntur yang ikut serta didalamnya mental terjajah, yang ditandai dengan masih seringnya disebut-sebut segala hal yang terjadi sejak kira-kira 350 tahun yang lalu.
Buku-buku pelajaran sejarah kita pun memahami ini semata pertarungan dua kebudayaan (baca: bangsa), menang kalah dan kepahlawanan. Dialog guru dan murid di ruang-ruang ajarpun masih dalam tema: “kita dijajah Belanda dan Jepang” dan bukan: “kita dijajah oleh orang lain sehingga kita kehilangan hak-hak kita sebagai individu dan bangsa dan kita bangkit dan berjuang untuk merebut kembali hak-hak kita yang hilang itu” sebuah pemahaman yang positif tentang penjajahan, hak dan kemerdekaan yang melahirkan sikap positif dalam memahami eksistensi diri sendiri dan hubungannya dengan usaha untuk memajukan diri sendiri.
Kapan kita bisa seperti Jepang yang dikalahkan dalam perang dunia kedua, “terjajah”, lalu bangkit seperti melupakan begitu saja mereka pernah dikalahkan demikian tragis dan dahsyat jika sikap kita memahami masa lalu begitu traumatis dan negatif?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H