Prinsip-prinsip Negara Hukum di Indonesia dilumpuhkan oleh sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh jaringan ekonomi politik. Sistem politik kartel telah menyusup ke partai politik sehingga infrastruktur politik dan demokratisasi disandera. Disini hak asasi manusia disubordinasikan dan dikalahkan oleh gerakan populisme, politik identitas, SARA, dan bahkan kepentingan oligarkis yang bias yang didukung oleh praktik kekerasan dan kekerdilan ruang kebebasan sipil.
Yang mengkhawatirkan adalah bahwa oligarki ini membuka peran militer untuk menopang kebijakannya; dan seterusnya, memiliki andil dalam melemahkan kontrol kebebasan sipil. Sejak 2014, peran militer di ranah sipil semakin menguat melalui strategi pembentukan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian. Seperti dikemukakan Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dan Kordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam konferensi pers Menyikapi HUT ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Jakarta pada (4/10/2019) yang menyatakan bahwa "Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa operasi militer selain perang hanya bisa dilakukan jika ada
keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden," (Dikutip dari mediaindonesia.com).
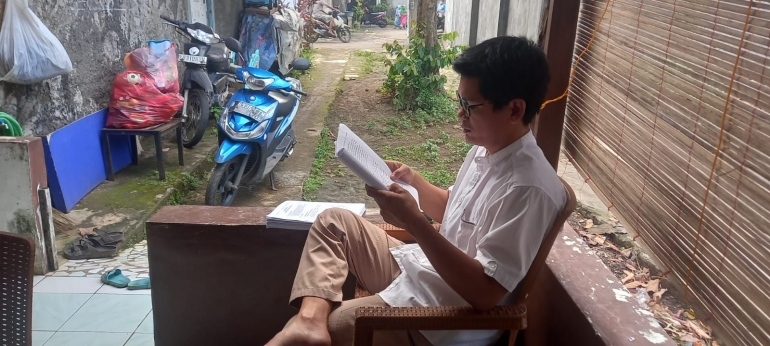
Pada saat yang sama, kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat, selain keterbatasan instrumen hukum yang selalu menjadi hambatan, juga lebih dominan dipengaruhi oleh tidak adanya komitme9n politik hukum yang kuat dalam menyelesaikannya. Bahkan sebaliknya adalah benar, Pemerintah saat ini mengedepankan politisasi yang kontraproduktif dengan upaya memajukan penyelesaian hukum itu sendiri, sebagaimana pernyataan Jaksa Agung di
depan umum yang memicu masalah, terutama dari keluarga korban dan korban. Situasi seperti itu menyebabkan konteks politik sosial menjadi kurang kondusif dan melemahkan sendi-sendi Negara Hukum Demokratis. Bagaimana situasi yang terjadi pada tahun lalu (2021) mempengaruhi perlindungan hak kewarganegaraan?
Kembali ke masalah Oligarki. Aristoteles menyatakan Oligarki akan berlawanan dengan kaum miskin yang jumlahnya banyak. Demokrasi akan berantagonisme dengan kaum kaya, yang jumlahnya sedikit tetapi sangat berpengaruh. Sebab itu, Oligarki dapat melindungi diri mereka sendiri dengan menyerap orang-orang tertentu ke dalam kekuasaan, sehingga bisa
melakukan penjaminan atas kekayaan mereka. Oligarki berbeda dengan Aristokrasi, karena apabila Aristokrasi diperintah oleh orang-orang terbaik demi kebaikan bersama, Oligarki diperintah oleh kaum kaya hanya demi kebaikan mereka sendiri. (Adams & Dyson, 2003: 17).

Omnibus Law Cipta Kerja sebagai Mesin Politik Legislasi Oligarki, cengkeraman oligarki dalam Negara Hukum ditandai dengan penggunaan instrumentasi hukum. Proses melegitimasi kekuatan politik ekonomi, dengan mengambil keuntungan dari eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, sumber daya manusia dan fleksibilitas kebijakan ramah pasar, menunjukkan karakter dominan yang melengkapi situasi.
Pemerintah dan DPR telah menegaskan sikap seperti itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang sering disebut omnibus law. Undang-undang ini sudah bermasalah sejak proses awal penyusunannya, di mana tidak ada yang terbuka alias tertutup, dilakukan terburu-buru bahkan terkesan sembrono, karena mengesampingkan begitu banyak prinsip hukum, baik formal maupun material. Kepentingan investasi, pemodal dan
kekuatan oligarkis seperti itu tidak mengherankan karena memanfaatkan representasi formal negara dalam membentuk hukum. Seperti yang disebutkan Sol Piciotto, dalam Regulating Global Corporate Capitalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), salah satu tujuan dari pembentukan omnibus law adalah agar modal kapitalisme global masuk ke negara-negara dalam bentuk investasi dengan jaminan kemudahan berusaha. Ciri khas penerapan produk hukum ini adalah hak-hak pekerja akan diabaikan, suara publik tidak akan didengar, demokrasi akan dikorbankan untuk kepentingan bisnis, dan nilai-nilai universal akan diabaikan.
Jika UU Cipta Kerja (UU CK) bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja, maka paradigma tersebut harus mendorong semangat ekonomi kerakyatan dan menjamin perlindungan HAM, serta menjaga alam tetap lestari. Namun, secara substantif, penyederhanaan regulasi melalui UU Cipta Kerja justru ditempatkan hanya orientasi kepentingan pemodal dan meliberalisasi pasar. Kepentingan politik seperti itu dalam catatan Wiratraman dan Paripurna2 melahirkan tiga hal berbahaya. Pertama, penguatan impunitas bagi investor, pemilik modal, dan perusahaan. Kedua, hilangnya peran publik (pembungkaman, penghapusan proses partisipasi). Ketiga, rentan terhadap ancaman/represi dan lemahnya perlindungan bagi aktivis. Ini mencerminkan setidaknya dua hal: siapa yang akan mengendalikan aturan implementasinya dan mengapa praktik sembrono terjadi begitu mudah dalam konteks kenegaraan.
Secara substantif, UU Ketenagakerjaan yang dihapus melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja otomatis menjadi tidak sah. Akibatnya akan ada sejumlah dampak yang cepat atau lambat menuai masalah mendasar terkait jaminan kerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2). Dampaknya meliputi:
Dampak 1: Mengubah / melemahkan jumlah pesangon.
Dampak 2: Melemahnya kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan cara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dampak 3: Potensi konflik dalam proses perubahan peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB).
Dampak 4: Regulasi semakin liar ditangan eksekutif, karena peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan akan berubah.
Dampak 5: Menutup peluang untuk transisi hubungan kerja dari pekerja penerima pekerjaan (vendor) ke pekerja di perusahaan pemberi kerja.
Dampak 6: UU Ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri, tetapi harus dimaknai dengan "kebaruan" UU Cipta Kerja.
Artinya, dari persoalan ketenagakerjaan saja, ada sejumlah hal dalam praktik Hukum Negara yang semakin tersandera oleh kepentingan oligarki.









