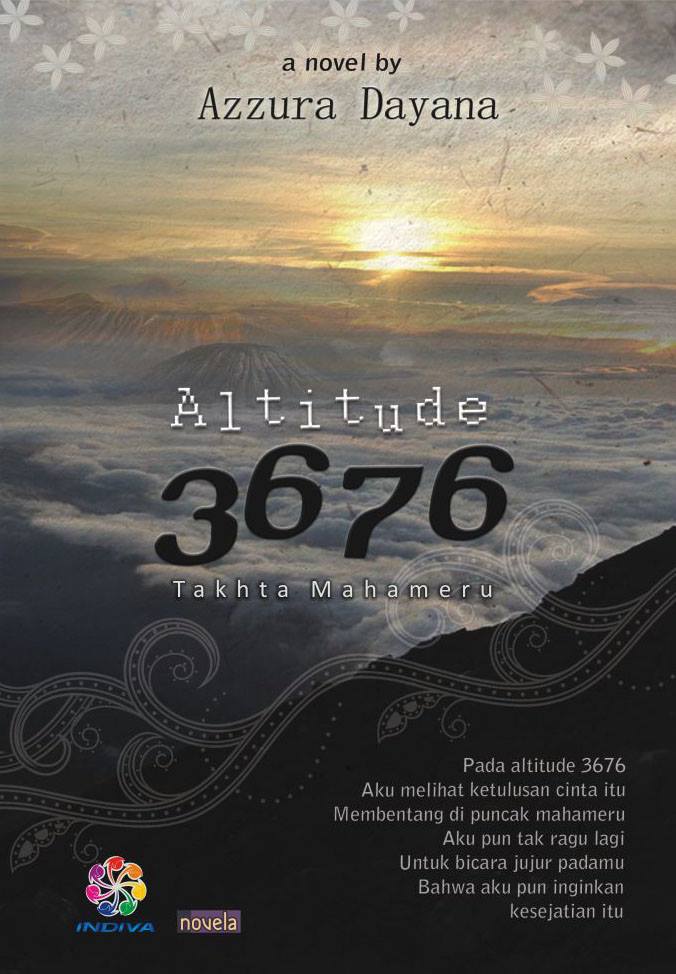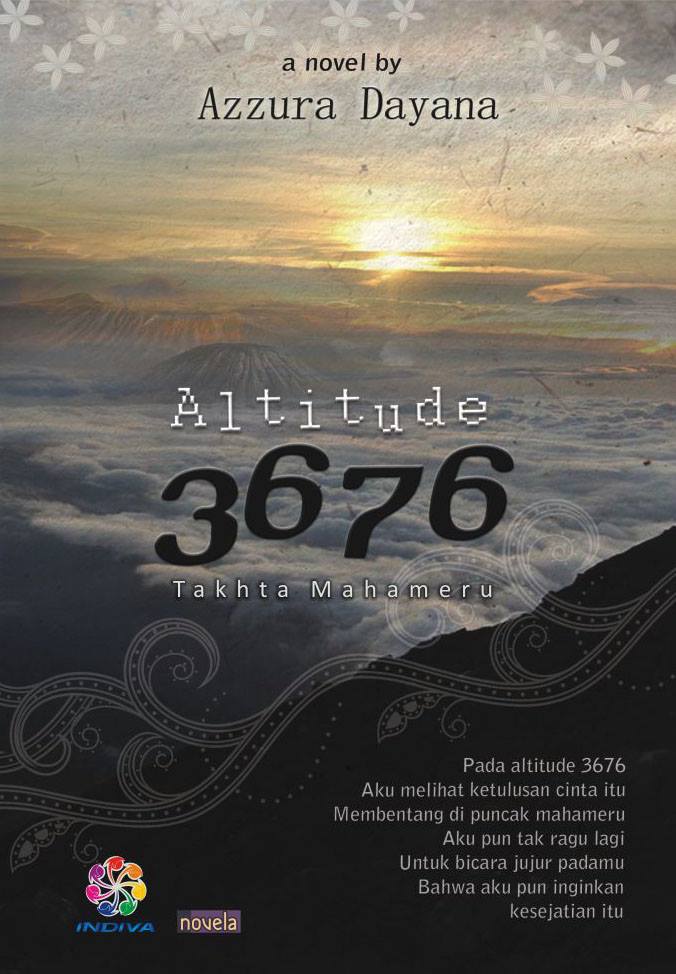Judul:Altitude 3676
Pengarang:Azzura Dayana
Penerbit:Indiva Media Kreasi
Cetakan :Pertama, Juli 2013
Tebal:416 halaman
ISBN;978-602-8277-92-1
Peresensi:Thomas Utomo; guru SD UMP
Ketinggian kerapkali menghadirkan campuran rasa ngeri, takjub, puas, haru, agung, sekaligus khusuk. Barangkali karena itulah orang-orang zaman dulu cenderung mengkeramatkan tempat-tempat yang tinggi. Mereka berpikir: tentulah ada Kekuatan Mahahebat yang bersemayam di sana.
Sama halnya dengan orang Jawa Kuna yang beranggapan dewa-dewa yang mereka sembah bermukim di puncak gunung. Hal ini dibuktikan dengan mitologi pewayangan yang menyebutkan Gunung Semeru menjadi tempat tinggal dewata. Oleh karena itu, penduduk memberi nama bagian-bagian tertentu dari gunung ini dengan nama kahyangan para dewa, seperti Jonggring Saloka—tempat tinggal Bethara Guru—dan sebagainya. Puncak Semeru sendiri dinamai Mahameru—artinya puncak abadi para dewa.
Lepas dari mitologi Jawa tersebut, gunung berketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini sudah menjadi “incaran” para pendaki sekurang-kurangnya sejak zaman pendudukan Belanda. Tidak sedikit orang ingin menjejak tanah Semeru hingga puncak untuk menemukan sensasi rasa yang menurut bahasa klise “tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata”.
Hal itulah yang dikehendaki Raja Ikhsan, pendaki tangguh yang sebelumnya sudah menaklukkan banyak gunung. Ikhsan berupaya menaklukkan Semeru didorong kekalutan hati yang mendendam setengah mati pada ayahnya—bahkan hingga ingin membunuhnya! (halaman 116). Dia ingin menyepi; menikmati suasana megah Semeru sambil berdialog dengan dirinya sendiri dan alam. “Setiap kali memandang puncak gunung ini, selalu ada getar di hatiku. Mungkinkah ini sekadar kekaguman belaka? Aku tidak tahu.” (halaman 108).
Pada kesempatan mendaki tersebut, dia bertemu Faras, gadis sederhana, penduduk asli Ranu Pane—desa tertinggi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (halaman 37-42). Tetapi, perkenalan dua makhluk beda latar belakang dan jenis kelamin itu tidak berlangsung lancar. Hal itu lebih disebabkan karena kelakuan Ikhsan yang ketus dan merendahkan sekeliling. Namun setelah sempat bercakap-cakap agak panjang, diam-diam Ikhsan heran dengan bahasa lisan Faras yang menurutnya, “...kadang-kadang memang tidak bisa dimengerti, seperti bukan keluar dari mulut seorang gadis desa, tapi dikabarkan oleh awan-awan di angkasa. Bahasa yang tinggi.” (halaman 91-92). Memang saat berbicara, kadang-kadang Faras menyitir perkataan Kahlil Gibran; penyair tersohor asal Libanon. Bagi Ikhsan yang serba to the point dan tak kenal basa-basi, gaya bahasa Faras jadi terkesan bertele-tele.
Tiga tahun berturu-turut Ikhsan mendaki Semeru; tiga kali berturut-turut pula dia bertemu dengan Faras—sampai kemudian gadis gunung itu mengetahui amuk dendam kesumat yang bersembunyi di balik dada Ikhsan. Kepergian Ikhsan selanjutnya; ialah kembali ke kota asalnya, justru menerbitkan kekhawatiran dalam diri Faras: ia khawatir Ikhsan betul-betul membunuh ayahnya!
Faras pun mengejar jejak pemuda itu. Alasan pengejaran itu semata untuk mencegah luapan dendam Ikhsan (halaman 105). Sayangnya upaya pengejaran tidak berlangsung mudah. Faras yang rela menempuh puluhan kilometer dari tanah asalnya, harus terengah-engah mengejar Ikhsan mulai sejak Borobudur, Tanjung Bira, hingga Makasar. Dan hasilnya nihil, nol! Namun dari penelusuran jejak inilah, Faras justru menemukan sisi lain dari diri Ikhsan. Penemuan ini yang kemudian mendorongnya pulang ke kampung halaman.
Sementara itu, dalam pelariannya dari persoalan dendam yang demikian merongrong, Ikhsan terdampar dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan serabutan lain; berpindah dari satu tempat ke tempat berikut. Dalam pelarian bermodal nekat ini, tanpa sengaja Ikhsan justru menangguk banyak pelajaran dari orang-orang yang dia temui. Anehnya, ada tali sambung atau kecocokan antara ajaran orang-orang itu dengan kata-kata yang pernah disampaikan Faras. Dalam perjalanan kali itu, Ikhsan justru menemukan kebenaran kata-kata Faras lewat lisan orang-orang yang berbeda. Kejadian tersebut berpengaruh besar bagi perkembangan Ikhsan selanjutnya.
Jalinan nasib yang serba tak terduga, mendorong Ikhsan untuk kembali mengunjungi Semeru. Dia ingin bertemu kembali dengan Faras sekaligus ingin merasakan kembali kemegahan Semeru; sembari berdialog dan berkaca ulang dari pengalamannya yang telah lalu. Di sisi lain, Faras juga tidak hanya pulang ke desa asal, sebuah dorongan tertentu mengajaknya untuk mendaki puncak Semeru. Dalam perjalanan mendaki itulah ia bertemu kembali dengan Ikhsan. Menariknya, kedua orang tersebut melakukan pendakian dengan tujuan: hendak melabuhkan rasa di atas tanah tertinggi Pulau Jawa (halaman 402).
“Di gunung, kamu akan melihat setiap orang dalam wujud aslinya. Karakter orang akan tampak jelas, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala kebaikan dan keegoisannya. Kuat atau tidaknya dia, mandiri atau manjanya, rewel atau tegarnya. Semua akan tampak di gunung,” begitu kata Ikhsan (halaman 394).
Sementara menurut Faras, “Aku tidak pernah berniat menaklukkan gunung. Mendaki gunung hanyalah bagian kecil dari pengabdian. Pengabdianku kepada Yang Mahakuasa!” (halaman 380).
Kualitas menonjol dari novel yang meraih IBF-IKAPI Award Kategori Fiksi Dewasa Terbaik 2014 ini adalah; Pertama, pelukisan suasana alam yang demikian meyakinkan, sehingga pembaca dapat turut larut, seolah-olah melihat dan merasakan keagungan gunung tertinggi yang jadi “titik kecil” tanda kemahabesaran Sang Pencipta. Meminjam bahasa Damar Junianto, pelukisan yang digunakan pengarang novel ini dinamakan realisme fotografis.
Kedua, sudut pandang penceritaan yang berubah di setiap bab. Masing-masing dengan cara bercerita yang berlainan sama sekali. Dalam hal ini, gaya penyajian novel ini barangkali mirip gaya penyajian dalam pagelaran wayang wong; ialah tiap babak disampaikan lewat tokoh yang berbeda-beda. Ketiga, alur cerita yang tidak datar—jalan terus sampai ujung, melainkan maju-mundur, meloncat-loncat, sehingga pembaca harus menyambung-nyambungkan sendiri bagian cerita menjadi runtut lewat pemunculannya yang terbelah-belah di tiap-tiap bab berbeda. Keempat, pengarang menyisipkan gagasan yang diusungnya secara halus, tanpa bahasa khotbah yang menggurui, seperti misalnya saat menyambungkan benang merah antara ketinggian Gunung Semeru dengan ayat Al Quran di surat Al A’raf. Benang sambung inilah yang kemudian menjadi jawaban Faras bagi Ikhsan mengenai kehadiran Tuhan di puncak Mahameru (halaman 411-413). Kelima, pengarang tidak “terjebak” untuk menjadikan “hubungan” Ikhsan dan Faras sebagai jalinan kisah asmara, melainkan kekawanan platonik semata.
Kritik untuk novel ini yaitu pemilihan nama Faras yang rasanya kurang cocok bagi gadis desa yang bermukim di gunung dan berasal dari satu keluarga Jawa sederhana yang jauh dari pengaruh modernitas kota. Abjad Jawa sendiri tidak mengenal huruf F, sehingga mungkin akan “lebih cocok” bila nama tokoh utama ini menjadi Laras atau Saras. Wallahu a’lam.
Ledug, 5 April 2014
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI