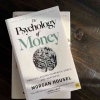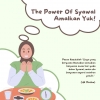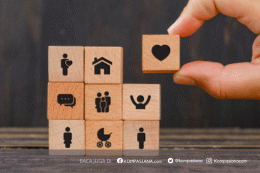Pagi itu, di sela-sela kunjungan ke pabrik daur ulang plastik di T***g, saya tersentak melihat tumpukan limbah tekstil yang justru dihasilkan dari seragam pekerja daur ulang sendiri. Ironi yang menggelitik - bagaimana sebuah solusi justru melahirkan masalah baru. Sebagai akademisi yang telah dua dekade meneliti ekonomi sirkular, saya sering dihadapkan pada paradoks semacam ini. Data Kemenperin 2023 memang menjanjikan potensi ekonomi sirkular sebesar Rp638 triliun, tapi realitanya, baru 11% yang benar-benar menerapkan prinsip sirkular secara utuh.
Mari kita ambil contoh nyata dari program daur ulang kemasan kopi sachet di J***a B***t. Secara permukaan, ini terlihat sebagai solusi brilian. Namun ketika saya dan tim menelusuri lebih dalam, ditemukan fakta mencengangkan. Biaya pengumpulan mencapai Rp5.000 per kilogram, sementara nilai jual ke pabrik daur ulang hanya Rp3.200. Lalu muncul subsidi pemerintah sebesar Rp2.500 per kilogram yang membuat seolah-olah ada keuntungan Rp700 per kilogram. Padahal, ini adalah ilusi akuntansi belaka. Subsidi tersebut bersumber dari pajak masyarakat, dan yang lebih mengkhawatirkan, tidak memperhitungkan biaya lingkungan yang ditimbulkan dari proses pengumpulan dan pengangkutan.
Di B***m, penelitian lapangan kami menemukan kasus lebih memprihatinkan. Sebuah pabrik daur ulang baterai ternyata menghasilkan limbah kimia yang mencemari laut setara dengan lima kali lipat dampak produksi baterai baru. Ini seperti mengobati demam dengan menimbulkan kanker. Analogi sederhananya, ekonomi sirkular ibarat hubungan modern yang mengklaim "putus tapi tetap berteman", tapi pada praktiknya masih menyimpan foto mantan di laci kamar.
Namun bukan berarti saya pesimis. Solusi yang lebih cerdas sebenarnya ada. PT. A***C di T***g telah membuktikan dengan mendesain ulang kemasan produk mereka yang bisa diisi ulang hingga lima kali. Hasilnya? Pengurangan biaya bahan baku mencapai 40 persen. Atau lihat saja kafe di kampus kami yang memberi diskon 20 persen untuk mahasiswa membawa tumbler sendiri. Kebijakan sederhana ini berhasil mengurangi 15.000 cup plastik setiap bulannya.
Pertanyaannya sekarang: apakah kita terjebak dalam euforia daur ulang tanpa melihat akar masalah? Seperti motor listrik yang dianggap ramah lingkungan, tapi lupa bahwa baterainya berasal dari tambang yang merusak alam. Ekonomi sirkular seharusnya bukan sekadar tentang mendaur ulang, tapi lebih pada mendesain sistem yang meminimalkan limbah sejak awal.
Pagi berikutnya, di tengah teriknya S***a, saya menyaksikan pemandangan absurd. Sebuah pabrik daur ulang plastik menggelar seminar "Go Green", sementara asap hitam mengepul dari cerobong belakangnya. Ironi sempurna! Ini mengingatkan saya pada petani di J***a T***h yang bangga memakai pupuk organik, tapi diam-diam membakar sampah plastik di belakang rumah.
Benarkah daur ulang selalu solusi?
Data Kemenperin (2023) menyebut nilai ekonomi sirkular Indonesia mencapai Rp638 triliun. Tapi riset lapangan kami menemukan fakta lain:
- Program bank sampah di Jakarta hanya menyedot 7% sampah plastik
- 80% pengumpul sampah masih dapat upah di bawah UMK
- Biaya daur ulang 3x lebih mahal daripada produksi baru
"Daur ulang itu seperti diet," canda Prof. Surya, kolega saya di UI. "Semua bilang mau, tapi saat lihat martabak, lupa semua resolusi."
Kisah Dua Pengusaha
Budi, pemilik pabrik sepatu di T***g, bercerita: "Dulu saya anggap daur ulang buang waktu. Sekarang, kulit sisa produksi jadi dompet ekspor ke Jerman." Omsetnya naik 40%.