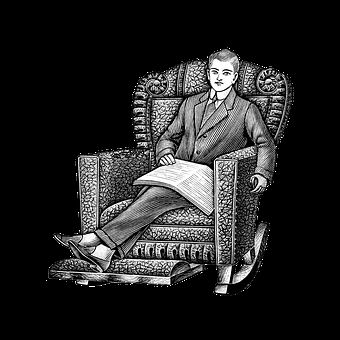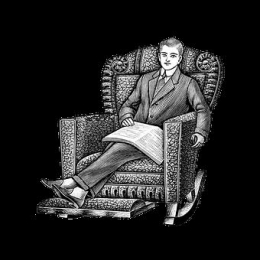Aku masih ingat saat itu tahun 1979, entah bulan dan hari apa aku lupa. Yang pasti itulah hari pertama Ayah mempercayakanku menjadi loper koran.
Setelah berhasil membagi-bagikan koran dan majalah kepada pelanggan, aku pastikan akan duduk di bawah pohon mangga Kadek, sambil melihat anak-anak mandi di sungai. Sekaligus aku tenggelam dalam dunia kata-kata. Ya, aku memang maniak membaca.
Maka kala Ayah menanyakan apakah aku mau menggantikannya meloper koran, sebab encoknya sering kambuh karena faktor usia, aku pun menjawabnya dengan melonjak meninju langit. Kupeluk Ayah dengan suka cita. Membaca lebih enak bagiku ketimbang ayam panggang spesial buatan Ibu.
Aku juga bisa bertahan tak makan siang bila sedang mendapat cerita menarik dari koran atau majalah. Hasilnya dapat ditebak, ada bilur-bilur bekas lidi kelapa di betisku. Ibu paling tak suka aku sakit karena tak makan. Dia malu, karena baginya, tidak makan itu artinya orang miskin.
Ayah tentu mengajak Ibu berbincang di teras rumah. Dia membelaku. Ayah katakan jangan terlalu keras memarahiku. Ibu akan membela diri seperti yang sudah, mestinya membaca tak melupakanku akan arti makan.
Biasanya Ayah diam. Ketika bangun pagi, Ibu akan memandikanku, meski malu rasanya dimandikan karena sudah tamat esde. Serampung mandi, akan kutemukan secangkir susu dan sepinggan nasi goreng spesial bertabur abon di meja makan. Selalu begitu. Ibu suka marah-marah kepadaku, tapi dia akan memperbaiki tingkah lakunya menjadi baik-baik saja, seolah dia ibu yang paling anti marah sejagat.
Kembali ke urusan mengantar koran dan majalah ke pelanggan, di hari kelima bertugas, saat itulah aku bertemu perempuan berambut kepang dua dengan lesung pipit sebelah kanan. Manis sekali. Aku mengangsurkannya majalah wanita dewasa dengan dada berdesir. Ah, anak kelas satu esempe, apakah wajar jatuh cinta?
"Pak Murad di mana?" tanyanya.
"Ayah berjualan di toko," jawabku sambil tertunduk.
Hanya sebatas dua kalimat itu, aku pergi mengayuh sepeda dengan sangat lambat. Kupastikan sekali lagi melihatnya. Dia tersenyum sangat manis. Sadarlah aku mulai mencintanya.
Cih, cinta monyet! Itu kata teman-teman apabila salah satu dari kami ada yang cinta-cintaan. Tapi kupikir merasakan cinta itu lebih asyik ketimbang melihat monyet. Maka kuputuskan menambah kalimat ketika kami berjumpa lagi. Dia sedang membaca majalah remaja. Tanpa kutanya, dia mengatakan bahwa majalah wanita dewasa yang kuberikan sebelumnya adalah milik ibunya. Aku tak menangapi, kecuali cepat-cepat memperkenalkan diri.
Namaku Darum. Dia tertawa geli. Namaku hanyalah kebalikan nama ayahku; Murad. Ayah memang suka membolak-balik huruf. Ayah itu ahli bahasa. Maksudku dia pensiunan guru Bahasa Indonesia. Berjualan koran dan majalah baru dilakoninya sekitar tiga tahun setelah pensiun. Itu pun dia harus mengalah kepada usia, dan menurunkan tahta loper koren kepadaku.