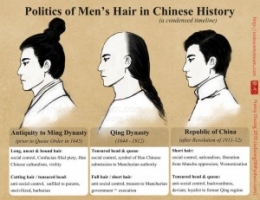Yang juga harus diingat, apapun latar belakang jenisnya, film tetaplah produk seni yang disajikan kepada khalayak untuk menghibur. Di sinilah sepertinya penulis harus mencoba memahami besutan Hanung—yang lagi-lagi atas nama tontonan—harus berusaha menampilkan sisi-sisi 'pop' filmnya. Sehingga, mungkin saja dengan pertimbangan itu, Hanung lebih tertarik menampilkan pergulatan hati Soekarno yang di tengah perjuangannya harus jatuh cinta kepada Fatmawati (diperankan Tika Bravani), seorang remaja berusia 15 tahun, yang merupakan murid sekaligus kawan anak angkatnya saat masa pembuangan di Bengkulu. Padahal, saat itu dia telah memiliki Inggit Garnasih (diperankan Maudy Koesnaedy), istri kedua yang telah setia menenopang perjuangannya di masa-masa sulit.
Termasuk saat dipenjarakan dan dibuang ke Ende dan Bengkulu. Ketimbang harus menggambarkan sosok ideologis maupun heroik Soekarno, seperti yang biasanya ditampilkan pada sosok pahlawan di film-film perjuangan di era 1980-an. Atau mungkin saja melalui ‘kejujuran’ literatur yang dimilikinya, Hanung mencoba tampil berbeda melalui karyanya. Sehingga, dia mencoba untuk keluar dari arus utama tentang sosok pahlawan yang harus selamanya digambarkan suci. Sehingga, tanpa beban dia mencoba menampilkan Soekarno dan Hatta yang terkesan begitu tunduk pada Jepang. Bahkan digambarkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalahbentuk kemurahhatian Jepang atas bangsa yang pernah dibinanya.
[caption id="" align="aligncenter" width="184" caption="Di film ini Hanung menampilkan tokoh utamanya dengan begitu positif. (Wikimedia.com)"]
[/caption]Nah, jika memang itu yang ditargetkan Hanung, tentu akan mengundang pertanyaan lain: Mengapa hal itu tidak dilakukannya di film Habibie dan Ainun? Padahal, tokoh yang diangkatnya ke layar lebar itu merupakan sosok yang jauh lebih muda dibandingkan Soekarno. Masyarakat pun setidaknya akan lebih mengenal kiprahnya, karena selain eranya belum lama berlalu, juga karena sebagian menilai pemerintahan BJ Habibie sebagai bagian dari Orde Baru. Namun, Hanung menampilkannya begitu positif di film itu, tanpa kontroversi sedikit pun.
Apakah Hanung memiliki agenda lain? Apakah Hanung didanai oleh pihak tertentu? Apakah Hanung mendapat titipan? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain bernada menuding.
Kecurigaan-kecurigaan pun akan semakin memuncak karena di karya biopik Hanung lainnya dia tidak mencoba menampilkan kontroversi. Seperti di film Sang Pencerah yang bercerita tentang KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Karena di film itu Hanung lagi-lagi hanya menampilkannya secara positif.
Yang kembali perlu diingat: pada dasarnya tujuan dibuatnya sebuah film adalah untuk menghibur dengan tujuan dapat dinikmati banyak orang. Berdasarkan data yang dilansir filmindonesia.or.id, hingga saat penulis menonton film itu pada 24 Desember 2013—sejak dirilis 11 Desember—Soekarno sukses meraup 543.100 penonton. Walaupun masih kalah dibandingkan 99 Cahaya di Langit Eropa dengan perolehan penonton 804.918 orang pada tanggal yang sama. Dan melalui Soekarno, Hanung setidaknya telah berhasil mengaduk-aduk emosi banyak pihak.
Kini filmnya menjadi perbincangan banyak pihak. Mulai kalangan awam, budayawan, sejarawan, hingga politisi. Sehingga, lepas apakah film itu dapat mengurangi bobot seorang Soekarno di mata generasi muda, maupun peran Jepang bagi kemerdekaan negeri ini, Hanung telah mencoba memisahkan sisi mitos dari sebuah sejarah.Walaupun di sisi lain, jika memang itu yang dituju Hanung, seharusnya juga diimbangi dengan lebih mendalami lagi riset bagi filmnya. Selamat menyambut Tahun Baru 2014!
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI