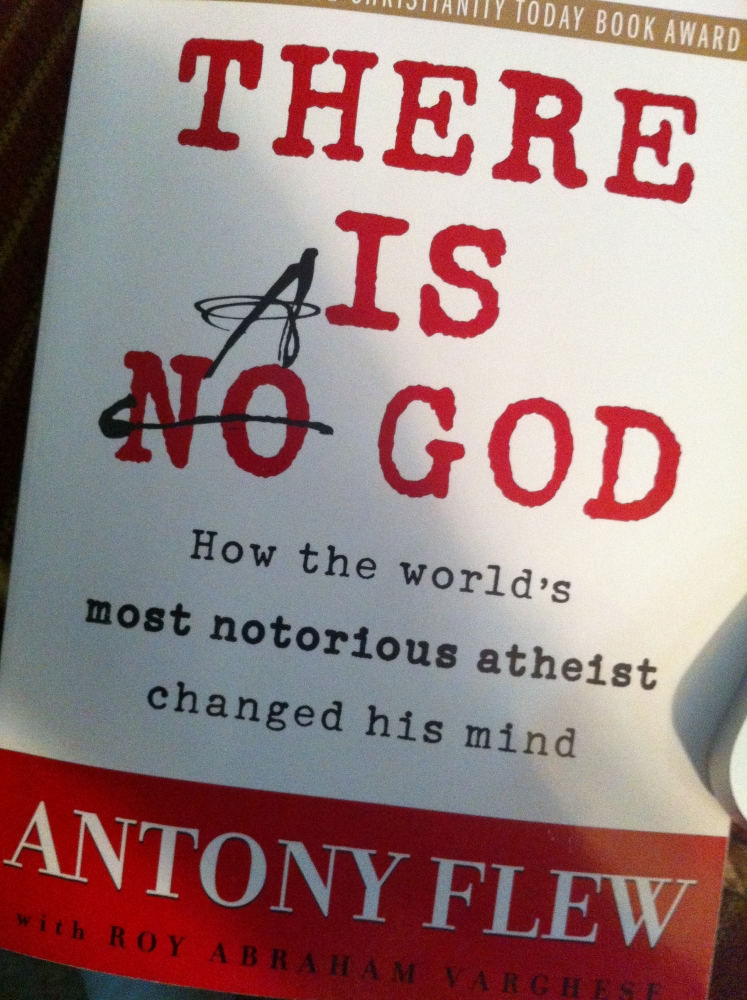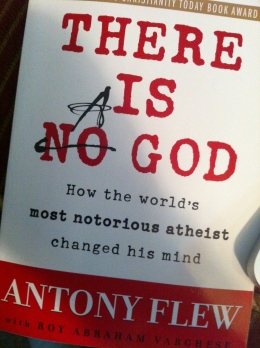Pemikiran tentang ateisme memang bukan barang baru di Eropa. Para ateis mengklaim secara intelektual lebih baik dibandingkan mereka yang religius.
[caption id="" align="aligncenter" width="400" caption="(wrongside1.files.wordpress.com)"]"][/caption]
ISTILAH ateis mulai dikenal di Yunani sejak abad ke-5 SM. Plato memperkenalkan kata atheos yang dalam bahasa Yunani berarti tidak memiliki kepercayaan akan adanya theos, yakni sesuatu yang luar biasa, bercahaya, dan tinggal di langit, yang sering diterjemahkan sebagai dewa atau Tuhan. Kata atheos juga digunakan untuk member predikat bagi kaum cendekiawan yang menyangkal keberadaan dewa-dewa di Yunani.
Sejak awal kemunculannya, ateisme dianggap sebagai momok dan selalu diuber oleh kalangan penguasa di Eropa. Pada abad ke-18, seorang penulis Prancis Baron d'Holbach mengikrarkan dirinya sebagai seorang ateis. Dalam buku The System of Nature (1770), dia menggambarkan alam semesta berdasarkan filsafat materialisme, determinisme yang sempit, dan ateisme. D’Holbach menyatakan bahwa semua manusia ketika dilahirkan adalah sebagai ateis, karena mereka tidak tahu akan Tuhan.
Pendapat-pendapatnya banyak mendapat kecaman. Sehingga pada 1772 Parlemen Prancis mengutuk dia dan membakar salinan bukunya yang berjudul Common Sense di depan umum. Sementara di abad ke-19, seorang filsuf Jerman Ludwig Feuerbach menyebut Tuhan hanyalah angan-angan buah pikiran manusia. Sifat Tuhan yang mengandung semua sisi kebaikan, menurut dia berdasarkan proyeksi atas sifat-sifat manusia. Jika manusia itu baik, maka dia bisa membayangkan sesuatu yang Maha Baik. Sebaliknya jika jahat dia bisa membayangkan sesuatu yang Maha Jahat.
Namun, tak semua penyokong pemikiran ateisme menyatakan bahwa ide ateisme berarti tidak memercayai eksistensi Tuhan. Charles Bradlaugh (1833-1891), seorang aktivis politik yang dikenal sebagai ateis menyatakan bahwa para ateis tidak menyatakan Tuhan tidak ada. Namun mereka memiliki ketidakjelasan akan ide atau pengertian naluriah akan Tuhan. Idenya memang kini dapat dikategorikan sebagai bagian dari agnostisisme.
Ateisme dan Intelektual
Di era modern, pemikiran mengenai ateisme memang mendapat tempat di dunia akademis. Salah satu yang menonjol adalah Richard Dawkins, seorang pakar biologi dari Universitas Oxford Inggris. Dia secara gamblang memperkenalkan konsepsi ateisme melalui karya-karya yang disebutnya berdasarkan penelitian. Mulai The Selfish Gene (1986) yang membahas evolusi dari sudut pandang gen hingga The God Delusion (2006) yang berisi bantahan berbagai argumen atas eksistensi Tuhan. Begitu juga dalam The Greatest Show on Earth (2009).
Masyarakat Barat memang menganggap ide-ide ateisme merupakan bagian dari realitas modern dan sebagian menilai hal ini menunjukkan tingkat intelektualitas. Mereka merujuk pada penelitian Lynn dan Vanhanen dalam buku IQ and Global Inequality (2006). Hasilnya hanya 23 dari 137 negara (17%) memiliki perbandingan populasi masyarakat yang tidak percaya Tuhan di atas 20%. Semuanya, menurut penelitian itu terdapat di negara maju.
Benarkah ateisme berbanding lurus dengan tingkat intelektualitas seseorang? Belum tentu. Bahkan, yang dialami Anthony Flew, seorang guru besar filsafat Oxford University, Inggris, justru membuat kaum ateis terpukul. Flew ternyata menemukan Tuhan justru setelah mengalami pergulatan intelektual selama 54 tahun mendukung ateisme. Dia menyebut ateisme yang telah diyakininya sejak berusia 15 tahun telah terbantahkan. Pada 2007, Flew mengumumkan telah keliru atas pandangannya selama ini. Dia akhirnya bisa menerima bahwa alam semesta telah diciptakan oleh sebuah rancangan cerdas. Termasuk karena penelitian para pakar biologi terhadap DNA menunjukkan adanya sebuah campur tangan sesuatu yang maha cerdas.