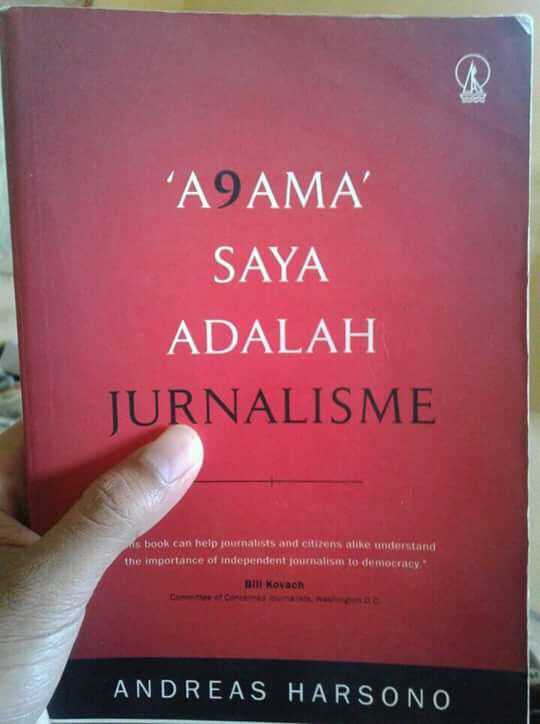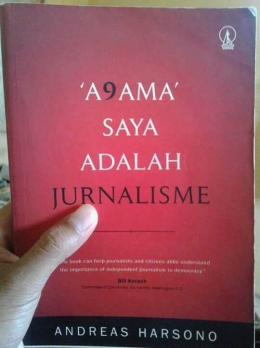Mengusik, kuping ini risih. Mengapa tidak? Saat kita menunjuk seseorang sebagai wakil justru tidak mendengarkan apa yang diharapkan muwakkilnya. Disusul keberpihakan hampir tidak lagi tertuju pada kita yang telah menjadikan mereka sebagai wakil.
Mereka (baca: wakil kita) sepertinya pura-pura tidak tahu -atau bahkan tak mau tahu- benang merah kritik, saran, dan hujatan. Konsekuwensinya, mereka membenci saran dan menolak kritik. Mungkin 'empuk kursi' sudah merubah mindset mereka dan lupa pada statusnya sebagai wakil.
Ada beberapa hal yang terlalu indah untuk dilupakan. Minimal ada tiga: Pertaman, status kita sebagai manusia yang mustahil lepas dari kesalahan. Tanpa menafikan kesalehan, sangat penting untuk mendengar suara orang lain utamanya dia yang sudah memilih anda sebagai wakil.
Kedua, sebagai negara yang demokratis tentu harus menerima 'suara' minamal tidak membuat rambu-rambu teror untuk setiap aspirasi. Bukankah sila pertama menjadi seperti yang kita baca hari ini tidak lepas dari legowonya pejuang terdahulu terhadap aspirasi.
Ketiga, menghormati pola pikir setiap kepala yang pasti berbeda dalam menterjemah fenomina. Perbedaan semacam ini perlu dirawat. Sebab tidak tertutup kemungkinan kepla orang lain lebih purna dalam mereinterpretasi fenomina itu sendiri. Namun selain tiga hal tersebut, masih banyak lagi yang naif bila ditinggalkan.
Jika masih bersikeras untuk menenggelamkan tiga hal ini, berarti mereka masih nostalgia dengan 'jaman old' yang memasung ekpresi. Sikap semacam ini sudah tentu makin meruncingkan buasnya keegoan yang seharusnya terkubur bersama rotasi waktu di tanah air ini.
Alhasil, harapan yang masih tersisia pada aktivis yang tercerahkan, organisasi masyarakat yang peduli, dan jurnalis yang independen.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI