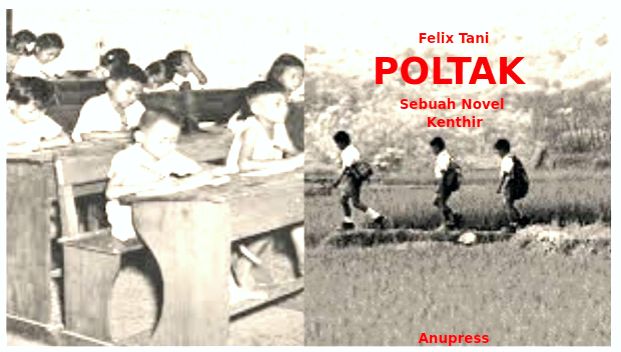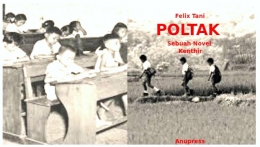Lonceng penanda masuk kelas belum berdentang, Poltak, Binsar, dan Bistok sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu, sekitar sepenghisapan rokok guru, sebelum lonceng lempeng baja SD Hutabolon itu dipukul. Kode panggilan bagi murid agar berkumpul untuk senam pagi di halaman depan gedung sekolah kelas empat, luma, dan enam.
Tiga sahabat itu bergabung dengan Jonder, Polmer, Alogo, Nalom, dan Togu di halaman depan gereja, merangkap gedung sekolah mereka. Berlima, mereka sedang asyik mengamati burung-burung walet terbang keluar masuk menara gereja.
"Bah, seperti pesawat tempur, ya!" Seru Poltak, ikut kagum melihat burung-burung itu.
Sebenarnya burung-burung walet itu sudah sejak lama bersarang di menara gereja. Begitu pun, setiap pagi burung-burung itu terbang hilir-mudik berburu mangsa, cari makan.
Tapi baru pagi itu Poltak mengamati ulah burung-burung walet dengan seksama. Pengibaratannya tepat. Burung-burung itu terbang menukik turun dari menara gereja, kemudian menukik naik ke udara. Membentuk lintasan terbang cekung, menyambar.
"Oh, mereka menangkap capung, rupanya," seru Poltak lagi. Itulah tujuan burung-burung walet terbang dalam lintasan cekung. Mereka menangkap capung-capung yang terbang rendah di pagi hari. Lembab udara pagi membuat capung sulit melayang tinggi.
"Ayo, perang! Tembak pesawat tempur musuh!" Tiba-tiba saja Alogo berteriak keras. Lalu, mengikut teriakannya, buah-buah makadamia berlontaran bak peluru meriam ke udara.
Alogo, Jonder, Polmer, Nalom, dan Togu, sambil berteriak-teriak seru, serentak menembaki burung-burung walet itu. Kantung-kantung celana mereka gembung padat berisi buah makadamia, amunisi perang. Jelas, itu penyerangan terencana terhadap pasukan burung walet gereja.
"Ayo! Poltak! Binsar! Bistok! Tembak!" Jonder berteriak mengajak, sambil mengangsurkan buah-buah makadamia. Tiga sekawan itu pun langsung ikut masuk ke arena perang yang gegap gempita. Itu memang betul-betul permainan anak laki.
Tapi menembaki walet-walet terbang sama susahnya dengan menembaki rombongan kelelawar di udara. Sensor burung-burung itu sangat tajam. Mereka selalu sukses berkelit, mengelak dari hantaman peluru buah makadamia. Alhasil, tidak ada seekor walet pun yang jatuh tertembak.
"Matilah kau!" Kesal karena semua tembakannya takkena sasaran, Alogo melontarkan peluru makadamia terakhir sekuat tenaga. Reputasinya sebagai petembak jitu buah kecapi terasa dilecehkan.
"Buk." Kena! Bukan walet, tapi punggung Guru Gayus yang sedang melintas naik sepeda di jalan depan gereja.
"Hei! Siapa yang melempar! Diam di situ semua! Jangan ada yang bergerak!"
Guru Gayus marah besar. Jika Guru Agama marah, maka hukumannya pasti melibatkan nama Tuhan. Berat, berat sekali.
Menuntun sepedanya mendekat, senyum datar di bibir Guru Gayus adalah isyarat amarah tak terkira. Delapan anak kecil, pasukan penyerang walet terbang, berdiri kaku dengan wajah pias di depan gereja. Mereka menjadi tontonan anak-anak yang lain.
Lonceng sekolah berdentang lima kali. Panggilan untuk senam pagi bersama.
"Kalian berdelapan tetap di sini! Lainnya, pergi sana! Senam pagi!" Perintah Guru Gayus dengan nada suara datar, keras, dan tegas.
Takada murid yang berani membantah Guru Gayus. Dia Guru Agama. Pantang dibantah. Dosa.
"Apa yang kalian lakukan tadi!"
Diam. Delapan anak menunduk. Hening.
"Pak Guru tanya! Jawab!"
"Pe ... perang, Gurunami. Melawan walet gereja," Poltak menjawab, berselimut kembut.
"Perang melawan walet? Otak dungu kalian itu yang harus diperangi. Bukan walet!"
Delapan anak semakin terdiam, semakin tertunduk, semakin kembut.
"Kalian tahu untuk apa Tuhan menciptakan burung walet?" Retoris. Pertanyaan itu hanya mungkin dijawab seseorang yang telah bertungkus-lumus dengan Bibel dan, memang, benarlah begitu.
"Untuk memangsa hama belalang, agar padi dan jagung bapakmu tidak puso!"
Guru Gayus mulai membuka Bibel saktinya. Firman. Tuhan segera turun. Delapan anak mulai gemetar.
"Berfirmanlah Tuhan kepada Musa: 'Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu.' Keluaran Sepuluh ayat duabelas!"
"Kalian tahu sekarang akibatnya kalau Tuhan tidak menciptakan burung walet? Kalian akan mati kelaparan!"
Poltak terpana. Tak pernah terbetik di benaknya, Tuhan menciptakan burung walet untuk mencegah bencana kelaparan. Walet juru selamat.
"Kalian telah memerangi juru selamat. Karena itu harus dihukum. Baris rapat di tangga!" Guru Gayus menunjuk ke arah tangga semen gereja.
"Poltak, Binsar, Bistok dan Jonder di anak tangga pertama. Lainnya di anak tangga kedua. Semua mendangak. Lihatlah burung-burung walet terbang di langit!"
Ada pun anak tangga pertama dan kedua itu penuh dengan bercak-bercak hitam-putih. Kotoran burung-burung walet yang cret-crot saat mereka lepas landas dari menara gereja.
Memang itulah hukuman bagi delapan anak nakal. Menadah cret-crot tahi walet tepat di wajah mereka. Hukuman dari walet gereja.
Plok, plek, pluk. Tak perlu menunggu terlalu lama. Wajah delapan anak itu telah berubah menjadi kakus burung walet. Mereka kini berbedak guano. Seratus persen alami.
Riuh gelak-tawa murid-murid kelas satu, dua, dan tiga, yang berlarian masuk kelas selepas senam pagi. Mereka menertawai delapan wajah berbedak tahi walet.
Poltak belum pernah merasa semalu pagi itu. Di antara anak-anak yang bergelak riuh itu, ada pula seseorang yang tawanya sabgat nyata dengan lengking menikam perih gendang telinga. Berta!
"Pantaslah aku tadi malam mimpi digigit babi. Malu besar inilah maksudnya." Batin Poltak, merutuki nasib sialnya di pagi hari. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H