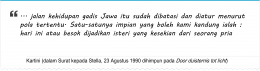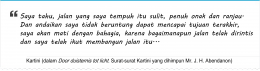Saat saya sedang dalam perjalanan pulang menuju kampung halaman. Dua orang perempuan masuk dalam bus yang sama dengan saya. Salah seorang dari mereka nampak menggunakan gaya jilbab masa kini yang sering disebut hijaber dan yang lain hanya menggunakan kaos dan celana lutut lengkap dengan sepatu olahraga. Selanjutnya, dua perempuan tadi larut dalam percakapan seru seputar kampus, teknologi dan situs jejaring sosial. Saya berusaha memejamkan mata untuk beristirahat. Namun kali ini, saya tidak dapat memejamkan mata. Saya teringat perempuan lainnya. Seorang perempuan dengan mata besar, hitam namun tatapannya menawan dan seolah-olah mengandung perasaan yang halus.
Siapakah dia? Perempuan tersebut adalah Kartini. Raden Ajeng Kartini.
Terlahir dan tumbuh dalam keluarga ningrat yang penuh dengan kungkungan feodal, tidak membuat Kartini tenang saja dalam menghadapi paksaan masa pingitan. Ia tidak tunduk pada semua aturan adat yang diwajibkan padanya. Kartini sangat bertekad kaum perempuan yang tentu saja adalah calon ibu, bisa mendapat pendidikan. Pendidikan inilah yang nantinya membentuk watak anak-anak demi kemajuan bangsa.
Pada tahun 1892, saat sudah menginjak masa remaja, Kartini, seorang puteri layaknya puteri ningrat lainnya di tanah Jawa kala itu, harus masuk dalam fase pingitan. Meskipun ayahnya cukup progresif untuk memasukkan puteri-puterinya ke sekolah, namun Kartini dianggap sudah cukup besar untuk tunduk kepada adat-kebiasaan.
Berkali-kali Kartini berusaha menghibur diri dengan terus belajar, meski tanpa guru. Kartini juga memanfaatkan waktu luangnya untuk menganalisa persoalan yang ada. Hingga akhirnya, ia mulai mengerti adat feodal, poligami dan kawin paksa. Sebuah penemuan justru menjadi konflik bagi jiwa Kartini, sebab saat masa pingitan inilah ia baru menyadari bahwa ternyata ayahnya tercinta juga memiliki dua isteri. Bahwa ternyata, selama hidupnya, sejak lahirnya, ia sudah memiliki dua orang ibu. Masa pingitan yang berat dianggap berakhir oleh Kartini, sejak kembali bersatu dengan Roekmini dan Kardinah. Mereka masih tetap dipingit, tetapi kebersamaan membuat mereka tidak pernah berhenti untuk mengembangkan bakat masing-masing dan terus belajar. Hingga suatu hari, keteguhan ketiganya membuat sang ayah, Bupati Sosroningrat, mengambil langkah yang penting. Pada tahun 1896, untuk pertama kalinya, meskipun hanya beberapa jam saja, ketiganya diajak ikut pergi ke desa Kedungpenjalin, Jepara. Selanjutnya, pada tahun 1898, kurungan ketiganya resmi dibuka, mereka diajak hadir dalam penobatan Ratu Wihelmina di Semarang. Hari-hari berikutnya, ketiganya sibuk keluar-masuk kampung dan semakin dekat dengan masyarakat.
Mari singkirkan pengaruh zaman modern kita saat ini dan lihat dari sisi Kartini. Bayangkan kita adalah seorang perempuan ningrat. Kita yang ketika dewasa akan menjadi Raden Ayu, kita harus dikurung untuk waktu yang tak terbatas, sampai ada orang yang melamar. Kita tidak boleh memilih suami sendiri dengan alasan yang lebih logis, seperti mengenal dan jatuh cinta, misalnya. Kita dipaksa. Kita dimadu. Kita diterlantarkan. Kita dicerai. Tapi kita berdiam diri. Nrima!
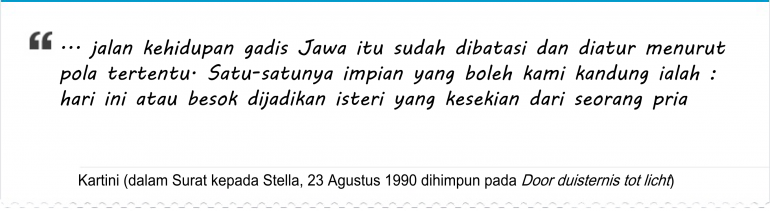
Kemudian, ada fakta bahwa kita sebenarnya bisa lebih harmonis dalam kehidupan berumah tangga. Bahwa dua insan dapat saling menghargai sebagai kawan dan sama-sama mempunyai hak suara. Bahwa dengan pendidikan dan menjadi kaum terpelajar, wanita tidak harus tergantung pada laki-laki, juga tidak dapat dipaksa untuk kawin dan dimadu. Namun, kita tetap perempuan ningrat, dan kita harus siap menerima fakta tersebut. Sekuat apapun berusaha, tujuan takkan pernah tercapai.
Hingga satu ketika, sesuatu terjadi. Kita ditawarkan sebuah jalan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Untuk bisa mengabdi pada masyarakat, untuk mendapatkan pendidikan, sekaligus membuktikan diri. Sekaligus. Akankah kita menolak?
Walaupun akhirnya terbebas dari pingitan lebih cepat, Kartini tetap menjadi orang sederhana yang hanya mengakui keningratan jiwanya. Ia tetap giat dalam masyarakat. Ia membuka sekolah gadis pertamanya. Ia terus menulis dan berusaha mendapatkan pendidikan lebih tinggi dengan biaya Negara. Dan di akhir, ia mengorbankan dirinya, menerima lamaran Bupati Rembang tanpa melakukan penyelidikan dengan seksama. Bahwa Bupati Rembang tatkala melamar Kartini, tidak terbuka mengenai keberadaan tiga selirnya di kabupaten. Keputusan ini menimbulkan kesan seolah-olah diambil karena hanya mau mengorbankan diri sendiri demi kesehatan sang ayah tercinta, yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ia bisa saja melakukan hal lain, toh ia sudah terkenal sebagai wanita modern yang mempunyai pemikiran revolusioner. Ia sudah terbiasa dicemooh dan ditertawakan. Namun, ia membuat pilihan untuk berkorban.
Lihatlah, Cut Nyak Dhien yang tidak berhenti melanjutkan pengorbanan menghadapi Belanda ditengah penyakit rabunnya, Ki Hajar Dewantara-Douwes Dekker-Cipto Mangunkusumo saling berkorban untuk menyelamatkan satu sama lain, Dewi Sartika yang rela berkorban banting tulang untuk biaya operasional sekolah, hingga Soekarno-Hatta yang rela mengorbankan diri mereka diasingkan hingga ke Bangka.
Kesamaan dari mereka semua adalah pengorbanan. Semua karakter tersebut berkorban untuk teman, orang tua, masyarakat dan bangsanya.

Kekuatan pemikiran, perasaan, kecerdasan berpikir yang modern dan segala petunjuk yang diperlukan perempuan untuk menjadi ibu yang baik rasanya tidak akan mengurangi penghargaan saya terhadap Kartini. Meski Kartini memang tidak tinggal lama di kampung halaman saya, di Rembang. Meski masih begitu banyak yang meragukan jasa Kartini dan keaslian surat-suratnya.
Namun tugas saya, kita semua, tetaplah harus mengakui kebulatan pemikiran revolusioner, perjuangan feminisme, hingga gelora nasionalis Kartini yang membuatnya mau berkorban. Jadikan ia pahlawan. Jadikan kisahnya berarti, bukan sebagai dongeng namun juga bagi sejarah Indonesia.
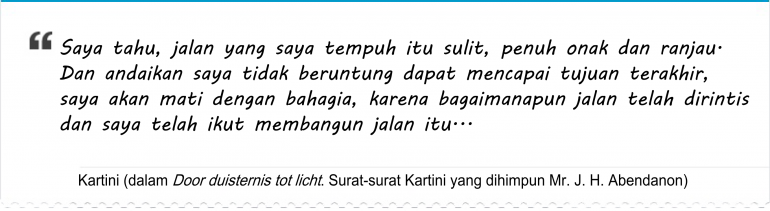
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI