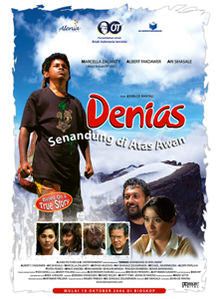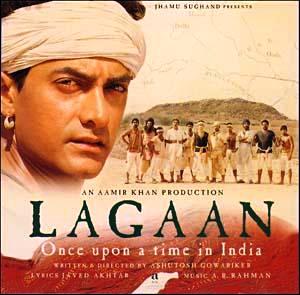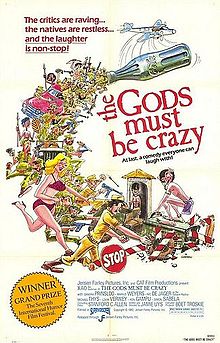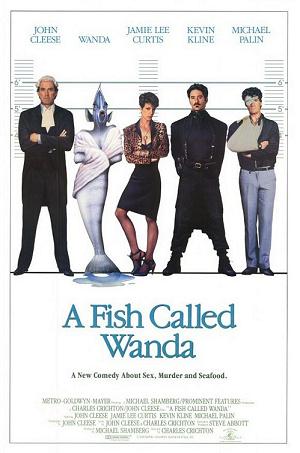[caption caption="Sumber: hauteprovenceinfo.com"][/caption]Tanggal 30 Maret kemarin diperingati sebagai Hari Film Nasional. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 30 Maret ini (tepatnya 30 Maret 1950) adalah hari pertama syuting film “Darah dan Do’a (Long March of Siliwangi)” karya sutradara Usmar Ismail. Film ini dianggap sebagai film lokal pertama yang bercirikan Indonesia, yang 100 % made in Indonesia.
Sejarah perfilman Indonesia sendiri sebenarnya sudah cukup panjang, bahkan melebihi usia republik ini. Film pertama di Indonesia adalah film bisu berjudul “Loetoeng Kasaroeng” karya sutradara Belanda G. Kruger dan L. Heuveldorp (1926).
Meski sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, mengapa perfilman Indonesia susah berkembang?
Inilah beberapa penyebabnya:
- Produser
Jumlah produser film Indonesia yang bisa dihitung dengan jari mengakibatkan film yang dihasilkannya hanya berputar di tema yang itu-itu saja, sesuai selera sang produser. Selera keluarga Punjabi tentu berbeda dengan selera Mira Lesmana dan Ari Sihasale, misalnya. Anda bisa menebak sendiri film jenis apa yang diproduksi oleh keluarga Punjabi, Mira Lesmana dan Ari Sihasale. Tentu bukan masalah jika itu sudah menjadi ciri khas mereka, seperti halnya Walt Disney yang punya ciri khas memproduksi film-film segala umur. Menjadi masalah karena jumlah produser film Indonesia tidak banyak, sehingga penonton tidak banyak mendapatkan film dengan tema alternatif.Jika film dengan genre horor sedang tren atau laris, maka dia akan membuat film horor lagi. Horor lagi dan horor lagi. Begitu juga jika film dengan tema religi ternyata laris, film berikutnya pasti bertema religi lagi. Dengan kekuatan uangnya sang produser bisa mendikte jenis film apa yang akan diproduksinya.
- Sutradara
Kebanyakan sutradara kita kurang memperhatikan detil adegan. Bisa jadi karena harus mengejar deadline alias kejar tayang. Bisa juga karena naskah atau skenarionya yang kurang detil. Almarhum Teguh Karya adalah sutradara yang sangat memperhatikan detil karena beliau juga seorang penulis skenario.
[caption caption="Gambar dari cinematerial.com"][/caption]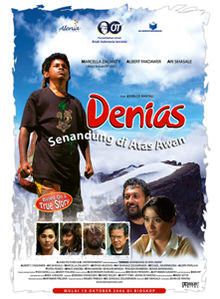
Saya ambil contoh dari film “Denias, Senandung di Atas Awan” (John de Rantau, 2006). Lihat cuplikan adegan Enos pulang ke kampungnya untuk mengambil rapor. Digambarkan Enos harus berlari naik turun bukit, menyeberangi sungai dan danau. Mungkin, sang sutradara ingin memperlihatkan betapa jauh dan beratnya perjalanan Enos sekaligus ingin memperlihatkan betapa cantiknya alam Papua. Bagi yang belum mengenal geografi dan topografi Papua mungkin akan manggut-manggut saja sekaligus berdecak kagum. Tetapi karena film ini didasarkan pada kisah nyata dengan tempat kejadian yang betul-betul ada, saya justru merasa heran. Memang jalur transportasi darat di Papua sangat minim, tapi apa iya dari Kuala Kencana ke Ilaga harus lewat Danau Habaema? Entah itu karena skenarionya yang bilang begitu atau kemauan sang sutradara. Bagi saya kok aneh.
[caption caption="Gambar dari sidomi.com"][/caption]Saya ambil contoh lagi film “The Raid” (Gareth Evans, 2011). Meski film laga ini sukses luar biasa dan mendapat banyak pujian, baik dari dalam maupun luar negeri, tetap saja ada adegan yang membuat saya geleng-geleng kepala. Bukan karena takjub, tapi karena heran bahkan ingin tertawa. Bayangkan, di dalam gedung apartemen berlantai 30, lantainya bisa ditembus/dilubangi dengan kapak karena terbuat dari kayu. Kalau dinding atau sekatnya terbuat dari kayu/papan atau multiplek, OK-lah. Masih bisa diterima. Tapi kalau lantainya dari kayu/papan? Woouuuww! Apalagi lantai yang di koridor/gang terbuat dari beton. Bagaimana bisa, begitu masuk ruangan lantainya berubah terbuat dari kayu/papan? Hellooww... apa kata orang konstruksi bangunan!
- Penulis Naskah atau Skenario
Sebetulnya kelemahan utama dan pertama dunia film Indonesia berawal dari naskah atau skenarionya. Permasalahannya naskah atau skenario sangat terkait dengan sutradara dan produsernya. Ada naskah dan skenario bagus, ada sutradara yang mau menggarapnya tapi tidak ada produser yang mau mendanai. Sebaliknya meski naskah dan skenarionya tidak bagus tapi kalau ada produser yang mau keluar dana, ya jadi filmnya. Ujung-ujungnya kembali ke produser.Sering kita saksikan cerita yang ‘ujug-ujug’ alias tiba-tiba tanpa asal muasal yang jelas. Yang paling sering kita lihat ketika yang miskin, lemah atau teraniaya berdo’a, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Bisa ditebak di adegan atau beberapa adegan berikutnya do’anya pasti terkabul tanpa adanya upaya dari yang berdo’a. Untuk urusan naskah dan skenario, terus terang saja, penulis naskah dan skenario kita –secara umum- masih kalah dibandingkan dengan film India.
[caption caption="Gambar dari quora.com"][/caption]Ambil contoh film “Lagaan” (2001), yang masuk dalam nominasi penghargaan Academy Awards (Oscar) untuk kategori film berbahasa asing terbaik. Film ini berkisah tentang perjuangan warga sebuah desa di India melawan kolonial Inggris melalui permainan cricket. Bagaimana jatuh bangunnya warga desa dalam membentuk tim cricket tergambar dengan sangat jelas dan detil dalam film yang berdurasi 3 jam 35 menit tersebut. Tidak ujug-ujug bisa main cricket dan menang.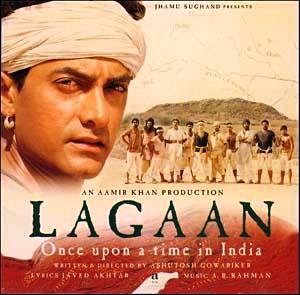
Kalau dirunut lebih jauh, kelemahan penulisan cerita dalam film-film kita karena pelajaran mengarang kurang mendapat perhatian di bangku sekolah. Sehingga kita kekurangan cerita yang bagus dan variatif. Kita kekurangan cerita dengan tema olah raga, kriminal, detektif dan misteri (yang bukan hantu). Saya berharap ada cerita seperti dalam film “The DaVinci Code” (Ron Howard, 2006) atau sekuel “Taken” (2008, 2012 & 2014), -terutama sekuel pertama- yang mengajak kita untuk berpikir secara terstruktur. Dulu ada serial detektif di majalah remaja ‘Hai’ bernama Imung yang ditulis oleh Arswendo Atmowiloto. Semoga ada sutradara dan produser yang mau menggarapnya.
[caption caption="gambar dari ngidambuku.blogspot.com"][/caption]Salah satu kurang berkembangnya cerita dalam perfilman kita adalah masih adanya beberapa isu yang cukup sensitif bagi sebagian masyarakat kita, sehingga para penulis cerita enggan atau tidak punya cukup keberanian untuk menyinggung apalagi mengangkat isu sensitif tersebut. Kondisi ini tentu berbeda dengan di Amerika dan Eropa, yang bebas menulis tentang apa saja.
- Penonton
Latar belakang pendidikan, ekonomi dan budaya penonton Indonesia yang sangat beragam akan menghasilkan penilaian yang berbeda pula terhadap sebuah film. Bagi kebanyakan penonton yang berasal dari golongan menengah ke bawah, film yang bagus itu adalah film yang menghibur, yang ringan-ringan saja tanpa banyak mikir. Buat mereka sisi teknis perfilman seperti editing, sinematografi, tata suara dan musik dan lain-lainya tidak penting. Pokoknya nonton dan merasa terhibur. Titik. Sebaliknya bagi penonton yang merasa terdidik, film bukan hanya sekedar hiburan. Tapi harus ada nilai plusnya, baik dari sisi teknis perfilmannya mau pun pesan yang disampaikan oleh film tersebut.Dua kubu ini akan menghasilkan penilaian yang bertolak belakang terhadap sebuah film. Contoh gamblang, film-film Warkop DKI. Bagi kebanyakan orang Indonesia yang merasa terhimpit dengan beban kehidupan, nonton film Warkop DKI adalah hiburan yang menyenangkan. Film-film Warkop DKI mampu mengalihkan sekaligus melupakan sejenak beratnya kehidupan. Namun bagi kalangan tertentu film-film Warkop DKI tidak lucu sama sekali. Mereka berpendapat “film kok nggak jelas juntrungannya”, “ceritanya gak nyambung” dan komentar-komentar minor lainnya. Menurut mereka film komedi yang bagus itu seperti “The Gods Must be Crazy” (1980) atau “A Fish Called Wanda” (1988), misalnya.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!