“…(Clichés) are also as stale and tasteless as a piece of cheese that’s been scudding around in the fridge for weeks. Don’t feed it to your readers.” – Trish Nicholson (dalam bukunya, Writing Your Nonfiction Book: The Complete Guide to Becoming an Author)
Pertama kali membaca kalimat di atas, saya langsung membayangkan sebagian produk-produk berita media massa yang memuakkan. Ya, banyak klise didalam media massa kita. Gejala-gejala berikut ini dapat anda temukan di koran, kanal berita di televisi dan sumber-sumber berita lainnya:
- Berita tanpa substansi
Munculnya satu atau dua kalimat banal dari seorang figur publik seringkali dianggap sebagai sebuah peristiwa yang patut diberitakan. Tinggal padukan kutipan perkataan tersebut dengan ringkasan peristiwa yang menjadi konteksnya, semudah itu sebuah berita tersaji.
- Opini yang aman dan nyaman
Kita disajikan kolom opini yang diselimuti political correctness. Entah apakah memang para pakar tidak ada yang mampu memberikan pemikiran baru atau memang media membungkam mereka. Sebagai eksperimen, saat membaca sebuah tulisan opini di koran, coba anda menebak arah dan kesimpulan dari opini tersebut.Kemungkinan tebakan anda benar—terlepas dari upaya para pakar untuk unjuk kebolehan dengan memberi kutipan pasal perundang-undangan, kata-kata seorang filsuf atau data statistik.
- Suatu topik berita diperah terus menerus
Sudah berapa kali anda mendengar para ahli membicarakan pro dan kontra terkait lokasi Rumah Sakit Sumber Waras? Sudah berapa hari anda mencoba mengecek televisi hanya untuk menemukan (lagi-lagi) perdebatan mengenai tidak diborgolnya eks-buron Samadikun Hartono saat dibawa ke Indonesia? Kemungkinan anda akan menjawab, “sudah jauh lebih dari cukup.”
- Keseragaman tema antar media massa
Mungkin anda bertanya: bila tidak suka terhadap pemberitaan yang repetitif di suatu surat kabar, kenapa tidak pindah saja ke harian lain? Karena, anehnya, surat-surat kabar alternatif juga menyajikan berita-berita yang kurang lebih sama. Ada sekian banyak topik di Indonesia yang dapat diangkat. Akan tetapi media massa seringkali terkesan serentak dan seirama dalam memilih berita utama yang sama.
Sumber gambar: https://yhalimblog.files.wordpress.com/2014/04/media.jpg
Melihat semua ini, sulit untuk tidak mencurigai adanya kesepakatan pembentukan opini publik di kalangan media-media massa. Tentunya lazim-lazim saja bila suatu media memiliki arah pemberitaannya sendiri—ini adalah diskresi masing-masing pimpinannya dalam mengangkat tema pemberitaan. Keanehan muncul saat beberapa media massa mengangkat tema yang sama dan gejala ini terjadi berulang-ulang.
Bila kesepakatan tersebut benar-benar ada, maka buahnya sudah bisa mulai kita kita petik: munculnya fenomena gejala anti-intelektualisme—di mana masyarakat, dengan berbekal informasi superfisial yang disajikan media massa, menganggap diri mereka menguasai permasalahan. Dalam tulisannya di Harian Kompas tanggal 25 April 2016, “Anti Intelektualisme di Indonesia,” sosiolog Robertus Robet menjelaskan:
“”Masyarakat info” merasa diri mengetahui karena merasa menguasai beragam informasi meski sesungguhnya mereka tidak memahami. Masyarakat info senang untuk terlibat dalam aneka percakapan publik di berbagai media sosial tanpa merasa perlu memahami sejarah dan asal-muasal gagasan...”
Saya setuju dengan observasi ini. Banyak dari kita yang merasa diri bagian dari kaum intelektual bila berhasil mengulangi “mantra-mantra” hasil indoktrinasi media massa mengenai sebuah isu publik. Pada akhirnya, orang-orang di belakang medialah yang diuntungkan saat kita secara sukarela menjadi agen penyebar “propaganda” yang diproduksi media massa yang bersangkutan.
Setelah mengkonsumsi berita di media, dengan mudahnya kita terjun untuk berdebat dengan emosional, seakan kita telah mengetahui seluk-beluk setiap permasalahan. Tanpa kita sadari, kepercayaan diri terlampau besar yang didasari oleh informasi superfisial tersebut pada akhirnya akan mengurangi niat kita untuk benar-benar mendalami konsep.
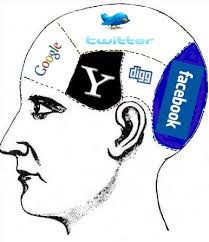
Pada akhirnya kita hanya akan sibuk mendebatkan isu-isu sensasional nan trivial tanpa menggubris permasalahan fundamental yang sebenarnya menyeringai. Pada akhirnya kita lebih sering memperdebatkan etika Ahok dalam bertutur kata, dibanding membicarakan arah pembangunan ibu kota. Kita lebih gemar menilai kemampuan Bahasa Inggris Presiden Jokowi pada saat berpidato di luar negeri, dibanding mendiskusikan arah kebijakan hubungan internasional bangsa ini.
Sulit untuk tidak berpikir bahwa peradaban kita, dengan asistensi media, sedang bergerak ke arah orwellian. Apa itu ‘peradaban yang orwellian?’
Istilah ini merujuk kepada novel berjudul 1984 karya penulis Inggris, George Orwell. Novel ini mengangkat kisah seseorang bernama Winston Smith yang bekerja di sebuah kementerian negara yang bertugas menyebarkan propaganda dan merevisi sejarah demi kepentingan partai penguasa. Secara spesifik, Winston diamanahkan untuk merevisi artikel-artikel surat kabar di masa lalu agar isinya tidak bertentangan dengan tujuan politis pemerintah. Pemerintah dalam novel tersebut adalah pemerintah otoriter yang melarang (dan sering mengkriminalisasi) individualisme dan pemikiran independen. Peradaban semacam itulah yang kemudian dikenal dengan istilah orwellian.








