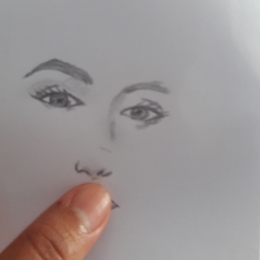Pandangan Marni menyapu tiap sudut ruang tunggu penjemputan. Dia amati satu per satu wajah orang-orang di sana. Namun, kenyataan lagi-lagi menorehkan luka. Tak ada seorang pun dari keluarganya datang. Dia kembali tertunduk lesu. Mengusap perut yang telah ditempati buah hasil perbuatannya.
Dua hari lalu, seharian menanti dering ponsel yang tak kunjung berbunyi. Berulang kali dia membuka pesan yang telah terkirim lima jam lalu. Ruang chat itu masih sama. Kosong. Hanya sederet pesan darinya tanpa satu balasan pun.
"Maafkan aku, Mas," suaranya lirih. Sejurus kemudian dia melangkah ke parkiran dengan sisa kekuatan yang dia punya.
Tidak lama, sebuah taksi menghampiri. Marni pun naik. Sesak di dada tak lagi dapat tertahan. Bulir-bulir bening jatuh dari sudut matanya. Mengiringi waktu menuju lelaki yang telah sah menikahinya.
***
"Jadi begitu ceritanya, Ndok," ujar Laila. Bola matanya berkaca-kaca.
"Jadi Marni itu .... Terus, akhirnya gimana, Bu. Suami Ibu Marni apa mau menerima dia lagi?"
Laila menghela napas berat. Dia menerawang jauh ke masa beberapa tahun lalu. "Sudahlah, Ndok. Yang penting kamu sudah tidak penasaran siapa kamu. Jangan dengarkan orang-orang di luar sana. Ambil hikmah dari ini semua."
Seketika Rahma jatuh ke pelukan Laila. Pipinya bahas. Dadanya sesak. Langit cerah tak mampu menutupi mendung di hatinya. Kenyataan telah menjadi pukulan besar. Gadis hitam manis itu memberi kecupan di pipi kanan Laila, beralih ke pipi kiri, kening, kemudian dia rangkulkan kedua tangannya ke pundak Laila. Dia berbisik, "Terima kasih, Bu. Ibu sudah ikhlas merawat Rahma seperti anak sendiri."
Disaksikan sepiring pisang goreng yang sudah dingin, Rahma mengucap janji. Tak akan ada dengki untuk orangtuanya. Seburuk apapun ibu, tetaplah harus dihormati, sejahat apapun ayah, dialah sebab dia hadir di dunia. Takdir telah mengantarnya ke keluarga Laila. Rumah penuh cinta dan kasih sayang.
"Besok kita ziarah ke makam ibu kamu, ya, Ndok?" ujar Laila mengusap pundak anaknya.