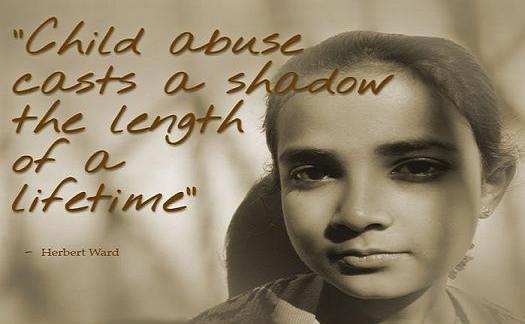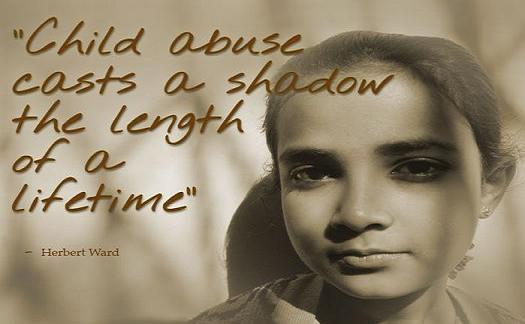Umumnya orang-orang menganggap bahwa tindak kejahatan yang luar biasa pantas dijatuhi hukuman yang ekstrim. Pengandaian dan memosisikan diri sebagai pihak korban untuk menghukum pelaku kejahatan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan. Tetapi, apakah hukuman itu mengandung unsur deterrent effect? Unsur ini diharapkan mampu membuat orang takut untuk ditangkap dan dijatuhi hukuman, sehingga tindak kejahatan dapat dicegah. Pertanyaan itulah yang hendak dijawab oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) ketika menghadapi laporan dan kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat.
KPAI lantas bersikap, dan bertekad untuk melawan serta mencegah kekerasan terhadap anak dengan salah satunya usul kepada presiden supaya menjatuhkan hukuman pengebirian kepada pelaku kejahatan seksual anak. Begitu pula, Yohana Susana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial) mendukung usulan tersebut. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pemerintah setuju dan akan menerbitkan Perppu hukuman tambahan kebiri. Bagaimana pendapat Anda? Apakah upaya pencegahan tindak kekerasan, terlebih kejahatan seksual terhadap anak itu semudah mengebiri pelakunya?
Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, melalui wawancara oleh Metro TV (21/10) menyikapi pengebirian tidak tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual anak. Ia juga menambahkan bahwa mekanisme pengebirian, misalnya suntikan kimiawi; mesti dilakukan secara berulang-ulang dan tentunya membebani keuangan negara.
Sependapat dengan Reza, kejahatan seksual terhadap anak tidak semata-mata terjadi karena dorongan libido si pelaku, tetapi melibatkan faktor lain seperti hasrat untuk mendominasi atau mengendalikan pihak lain yang lebih lemah. Tindakan seksual dengan menggunakan alat genital bukanlah satu-satunya pelampiasan dari hasrat si pelaku. Secara aseksual, pengidap pedofilia dapat meluapkan penyimpangan untuk melecehkan dan menciderai anak-anak. Dr Danny Sullivan, psikiater forensik dari Melbourn yang bekerja di Victorian Institute of Forensic Mental Health, menggarisbawahi bahwa pedofilia bukanlah perilaku atau aksi, melainkan hasrat. Ketidakmampuan pedofil untuk mengatasi emosi berupa rasa frustasi, malu, marah, dan penolakan semakin memperburuk kondisi dan perilakunya apabila ia merasakan bahwa hasrat libidonya tidak tersalurkan. Bukankah perasaan yang sama pun terjadi pada mereka yang normal? Pelarian lewat minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kriminal mungkin menjadi alternatif.
Kejahatan seksual terhadap anak tidak tergantung dan dipengaruhi sepenuhnya oleh dorongan libido si pelaku. Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan sikap permisif di masyarakat memungkinkan bentuk kekerasan itu terjadi. Contoh: tahukah Anda bahwa terdapat tradisi kuno di Afganistan dengan menyuruh anak-anak laki-laki menari di depan para lelaki dewasa? Semakin banyak anak itu dibeli, dikoleksi, dan dipelihara, maka semakin tinggi status sosial tuannya. Warga lokal menyebut tradisi itu bachabaze atau dikenal juga “playing or dancing with boys”. Mungkin Anda pernah menyaksikan pesta saweran ketika para penonton mengitari si artis yang sedang menyanyi dan berjoged, bisa dibayangkan seperti itulah bachabaze, tetapi anak-anak itu harus memakai baju wanita. Kadangkala gelang bel dilingkarkan di kaki mereka. Anak-anak ini yatim piatu atau berasal dari keluarga miskin.
Di negara yang ketat dengan nilai-nilai keislaman itu, perempuan tidak diperbolehkan menari di hadapan umum, tetapi anak-anak laki-laki menjadi korban. Imbalan untuk mereka berupa uang, makanan, tempat tinggal, dan semua itu diperoleh bukan saja dari sekedar menari dan menyanyi, banyak pula yang dipaksa untuk melayani hasrat birahi para pengidap pedofilia dan homoseksual. Sekalipun ada kecaman dari warga lokal, bentuk kekerasan dan prostitusi terhadap anak tersebut sulit dijangkau oleh sistem penegakan hukum dan keadilan di sana.
Pemandangan lain di Timur Tengah, seperti Yaman dan Arab Saudi, pemerintah dan masyarakat melarang hubungan kaum sejenis atau homoseksual. Namun, laki-laki dewasa boleh menikahi anak kecil perempuan dan dilegalkan. Pihak otoritas keagamaan secara konservatif menjustifikasi pernikahan anak itu sebagai tradisi lama. Apapun bentuk kekerasan terhadap anak, tampak lazim terjadi dan terabaikan di negara-negara Arab yang mengagungkan moralitas dan ketakwaan itu.
Bagaimana keadaan di Indonesia? Mayoritas masyarakat kita agamis, religius, dan kabarnya berprilaku sopan-santun. Lalu, apakah lingkungan kita ramah terhadap anak? Kasus Angeline di Bali misalnya, mungkin gadis cilik itu masih bisa menikmati masa kanak-kanaknya jika orang tua kandungnya tetap membesarkannya. Mungkin ia masih akan bermain dan belajar di sekolah apabila guru dari awal telah curiga dan mengawasinya. Tak sebatas lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, masyarakat pun cenderung membisu tatkala peristiwa kekerasan terhadap anak terjadi. Sebagian besar orang masih menganggap bahwa kekerasan terhadap anak adalah urusan domestik, sehingga mereka bersikap acuh tak acuh.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI