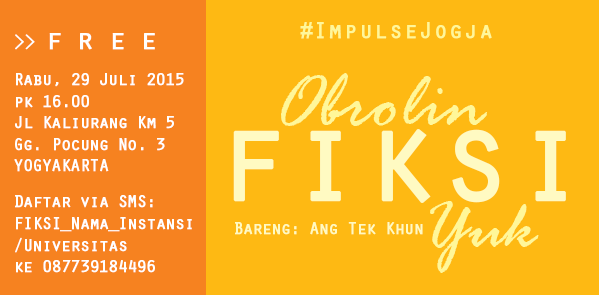Jika ada kota yang denyut jantungnya berdetak kencang dipompa oleh energi warga nan tak kunjung padam, itulah Yogyakarta. Orang-orang yang tidak pernah jatuh cinta pada kota ini tidak akan memiliki jejak langkah menuju rahasia ini, dan alhasil tidak akan pernah mengenali sebab-musababnya. Hari-hari ini ada begitu banyak kritik dan otokritik untuk kota ini yang abai merawat dirinya saat telah memasuki usia ke-259 pada 7 Oktober lalu.

Ketika seorang asing berbekal kemiripan nama yang diserap indra pendengarannya lalu bertanya-tanya apa perbedaan Jakarta dan Yogyakarta, saya menjawab mantap dalam keluguan: Jakarta dan Yogyakarta itu ibarat Tokyo dan Kyoto. Lugu karena hingga kini saya belum pernah ke Tokyo, pun Kyoto. Citra yang masuk dalam diri saya sederhana: Tokyo adalah kota megapolitan dan Kyoto adalah kota “heritage”. Kesahihan jawaban ini akan bisa dengan mudah saya verifikasi apabila ada yang bersedia mengajak saya ke kedua kota di Jepang itu.
Yogyakarta dan Komunitas
Dalam kesederhanaan berpikir, saya sangat menduga kota Yogyakarta lahir dari rahim komunitas. Saat menulis posting Manusia di Antara Kota dan Ruang Publik (http://bit.ly/1MxsYfM) saya berkesempatan mengutarakan contoh sebuah komunitas yang mencatatkan namanya dalam lembar sejarah sastra-budaya negeri ini: Persada Studi Klub (PSK). Komunitas ini lahir pada kisaran waktu 1968/69 dan merebak hingga puncak kejayaannya di ruang publik bernama trotoar Jalan Malioboro. Dengan motor penggerak Umbu Landu Paranggi, seseorang penuh pengabdian yang kemudian didaulat sebagai Presiden Malioboro, lahirlah nama-nama yang tercatat dengan tinta tebal seperti Emha Ainun Najib, Ebiet G Ade, Mustofa W Hasyim, Linus Suryadi AG, dan serenceng nama lain dari antara 1500-an orang yang bergiat di sini.
Jika kita melompat jauh ke depan setelah era PSK, kota ini juga mencatat lekat eksisnya komunitas blogger bernama CahAndong (http://cahandong.org/). CA menjadi rumah bagi sekumpulan blogger yang tinggal, berdomisili, pernah tinggal di Yogyakarta, atau yang memiliki hubungan dan kenangan tersendiri dengan Yogyakarta. Komunitas ini melejitkan namanya hingga ke panggung nasional. Banyak blogger kawakan Indonesia lahir dari “kawah candradimuka” ini. Salah satu aktivitas legendaris CA adalah apa yang dinamai JUMINTEN (JUmat MIdNite TENguk-tenguk), “acara kumpul-kumpul tiap JUMAT MALAM jam 21.00 till drop di Seputaran Titik Nol Kilometer Jogja”. Jika Anda belum pernah mendengar komunitas ini, silakan mengunduh gambaran akan kiprah komunitas ini di blog mereka di alamat di atas.
Bagaimana situasi Yogyakarta hari ini? Menakjubkan! Tak terbilang banyaknya komunitas merebak bak jamur di musim “hujan sepanjang tahun”. Di kota ini, apabila 2 atau 3 orang berkumpul gayeng (baca: seru), maka niscaya akan lahir gerakan atau komunitas. “Celaka”nya, di kota ini orang-orang suka ngumpul. Di pojok-pojok kota hingga pelosok, angkringan tumbuh dan dikelilingi orang-orang. Dalam hitungan hari ini, saya menduga ada lebih dari 150 komunitas yang menggeliat di sini. Mulai dari penyuka sepeda onthel, jogging malam hari, sampai penanam sayur organik; mulai dari kelompok belajar untuk membuat sketsa hingga berbagai aktivitas sosial yang berbasis relawan.