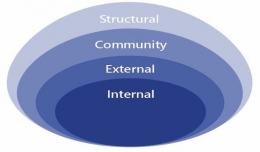Pertanyaan-pertanyaan kompleks menyoal perempuan sering berkejaran dalam kepala saya menjelang tidur; yang kukuh saya gugat, tak berkesudahan saya debat—bahkan sering saya lelah sendiri karenanya.
Apalagi kalau bukan tentang mengapa perempuan harus mengalami ini atau mengalami itu; tentang mengapa perempuan tak bisa lebih leluasa begini atau leluasa begitu atau; mengapa perempuan tidak mendapat banyak pilihan—alih-alih memang dipaksa tidak enak—dalam menjalani kodratnya dari Tuhan dalam sebuah siklus kehidupan.
Ritual menggusur gusar ini kerap saya lakukan di atas kasur saban malam. Sedikit dari sekian banyak yang menarik perhatian akan saya coba ceritakan dan ceritanya akan saya mulai dari tujuh hari sepanjang Ramadan yang saat ini sedang berjalan.
Ramadan. Ia selalu menghadirkan geliat dan untuk itu kau harus sepakat. Seperti tahun-tahun sebelumnya—sekalipun tahun ini berbingkai tahun kedua pandemi melanda—Ramadan selalu menyuguhan cerita dan perempuan selalu punya kisah: mulai dari menyiapkan penganan hingga ritual-ritual sebelum menuju peraduan dan tentu saja—saya berani bertaruh—di antaranya terselip keluhan atau kesedihan yang mungkin tak sanggup dibagikan kepada orang-orang yang secara langsung bersinggungan dengan sang perempuan itu sendiri.
Adalah satu teman sesama desainer grafis yang beberapa hari lalu kesedihannya bisa segera saya tangkap dari cuitan di laman Twitter-nya. Ia mengeluh dan melenguh tentang "sakit" yang ia rasakan buah dari sebuah anggapan. Katanya dalam cuitannya, ia lebih setuju dan memilih menggunakan kata "janda" saja (yang lebih lugas, tegas dan tidak bermakna manis yang dibuat-buat) dibandingkan "single parent". Ia berpedoman karena janda memang bentuk valid dari sebuah identitas seorang perempuan yang ditinggal suami: entah karena bercerai atau ditinggal mati.
Saya terpukau dengan keberaniannya—saya amini pendapatnya. Setidaknya itu relevan bagi kebanyakan perempuan yang berujung sendiri.
Ya, teman saya seorang janda—akibat berpisah dari suaminya yang kerap melakukan aniaya.
Tetapi, seperti perempuan yang menggendong kehidupan dengan sejernih-jernihnya hati, ia pun mencintai anak yang ia lahirkan. Ia berjuang menghidupi buah hati "kehidupan" yang dititipkan padanya meski dengan kepayahan. Di antara keluhan, kesepian dan kesedihan yang menerjangnya, saya tahu ia adalah sosok perempuan yang hebat—dan juga seorang ibu yang kuat.
Ia memang sekarang jadi perempuan yang merdeka secara individu. Tapi, tidak dalam masyarakat. Stigma negatif sebagai janda ditelan bulat-bulat dan sebagian besar justeru keluar dari kebanyakan para perempuan yang terlanjur mengeluarkan kata-kata jahat.
Mari kita rampungkan simpulan dengan membaginya dalam dua pernyataan.
Mana yang benar: perempuan bisa nyinyir terhadap perempuan lainnya karena ia tak sadar bahwasanya ia masih berkutat dengan sistem patriarki—yang entah sadar atau tidak masih ia amini sebagai kebenaran—yang ia terima sejak ia masih kecil—atau; perempuan bisa tidak ramah dengan sesama perempuan yang "berbeda" dari kebanyakan perempuan lainnya yang mungkin saja terjadi karena ia tak mendapat edukasi yang valid jika ia telah keliru dalam menimbang sebuah anggapan?
Keduanya benar, kawan: keduanya beriringan. Keduanya sama-sama menyakiti dengan obyeknya yang adalah perempuan.