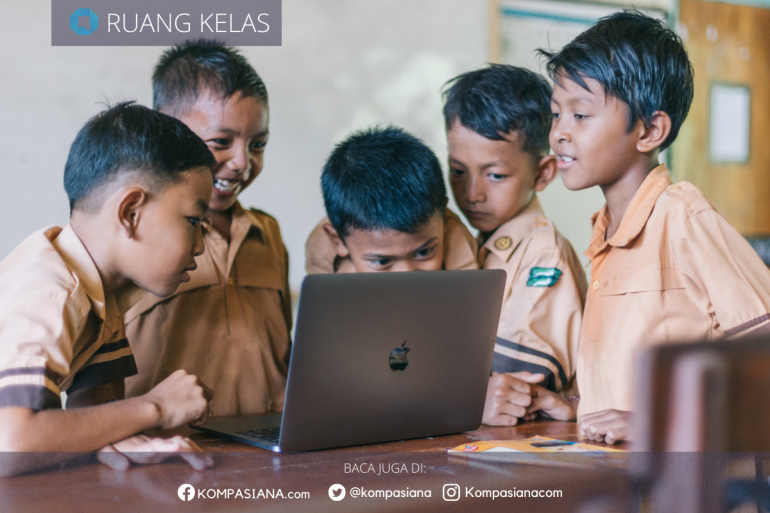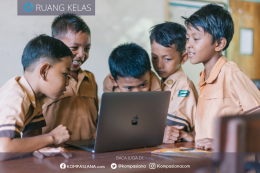Ditulis oleh
Hanifah Dianti Maharani
"Kami telah hidup di hutan ini dari sebelum negara ini terbentuk. Saya tidak tahu bahwa saya tinggal di area konservasi sampai ada beberapa polisi hutan yang datang ke desa kami dan mengatur cara kami hidup!" ujar Pak Ilyas, 64 tahun, salah satu tetua Masyarakat Adat Gajah Bertalut.
Genap dua puluh tiga tahun sudah amanat reformasi mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Masih dapat diingat dengan jelas bagaimana momentum gelombang demokratisasi tersebut turut merekam proses kebangkitan masyarakat adat di Nusantara dengan dikeluarkannya diktum provokatif mengenai posisi masyarakat adat terhadap negara. "Jika negara tidak mengakui kami, maka kami pun tidak akan mengakui negara," pungkas 400 pemimpin dan pejuang masyarakat adat dari seluruh penjuru Nusantara dalam forum Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1 (KMAN 1). Di tengah banyaknya perhatian media massa, kongres yang diselenggarakan di Jakarta tersebut menampilkan diskusi yang berapi-api mengenai represi militer dan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) (Davidson & Henley, 2007).
Tiga dasawarsa sebelum reformasi, yakni masa Orde Baru, memang menjadi salah satu masa terburuk bagi masyarakat adat. Kendati demikian, amanat reformasi selama dua dekade setelahnya pun tak memberi ruang hidup yang lebih layak bagi masyarakat adat. Berbagai produk kebijakan, baik nasional maupun daerah, silih berganti membuktikan masih minimnya kesediaan pemerintah untuk mengakui hak-hak masyarakat adat sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Janji politik yang tidak kunjung direalisasikan oleh pemangku kebijakan juga turut berkontribusi atas gamangnya pengakuan masyarakat adat di Indonesia.
Hal tersebut dibuktikan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merampas hak-hak masyarakat adat atas tanah, air, dan hutan adat yang dimilikinya, alih-alih mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) sesuai dengan janji politik yang dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014 lalu. Peraturan yang diterbitkan tersebut di antaranya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang yang memiliki sejumlah pasal bermasalah, salah satunya pada pasal 1 Ayat 28a UU Minerba yang menyebutkan bahwa wilayah hukum pertambangan mencakup ruang darat, laut, bawah bumi di kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan landasan kontinen. Pasal tersebut berpotensi merampas ruang hidup masyarakat adat yang konsekuensinya dapat menghilangkan identitas masyarakat adat yang berada di ruang hidup tersebut.
Kenyataan tersebut menyadarkan kita bahwa absennya kepentingan politik masyarakat adat dalam produk hukum dipengaruhi oleh kekosongan perwakilan masyarakat adat di kursi parlemen. Gerakan politik non-konvensional seperti blokade, demonstrasi, ataupun petisi yang sering dikaitkan dengan kekuatan masyarakat sipil pun tidak cukup memberi perubahan, justru mempertegas minimnya saluran partisipasi politik masyarakat adat terhadap jalur politik konvensional. Padahal, gerakan politik masyarakat adat memiliki potensi besar untuk meretas jalan demokratisasi di Indonesia yang belum menyentuh ranah substansial, baik dengan cara non-konvensional, maupun cara konvensional. Berhasilnya kebangkitan gerakan masyarakat adat dalam gerakan konvensional, yakni politik elektoral, dapat menjadi alat untuk membangun jalan demokratisasi pada dekade ketiga reformasi ini.
Indonesia sebagai Ruang Hidup 17 Juta Masyarakat Adat
Indonesia sebagai ruang hidup 17 juta masyarakat adat turut mencatat sejarah akan keberadaan masyarakat adat yang telah hidup di Nusantara sebelum Republik Indonesia (RI) berdiri, bahkan sebelum ide nation-state (negara bangsa) dikembangkan oleh para pendiri negara. Masyarakat adat juga ikut berkontribusi atas pendirian RI dengan memberikan tanahnya sebagai bagian dari wilayah negara RI. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat yang dimaksud tersebut sebagai "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya," (AMAN, 2001:9).
Selain dari penggunaan istilah "masyarakat adat" atau Indigenous People, masih terdapat beragam istilah yang merujuk pada komunitas tersebut, seperti istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang digunakan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) beserta 19 peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia (Bappenas, 2013). Pengertian dari MHA dapat dihayati dengan memahami dua faktor yang menjadi dasar pembentukan dan kesinambungan hidup MHA, yaitu faktor teritorial dan faktor genealogis (Syahmunir, 2005: 6). Dua faktor tersebut membentuk tiga kategori MHA, yakni MHA teritorial yang terikat pada suatu daerah tertentu, seperti desa-desa di Jawa, MHA genealogis yang terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, dan MHA genealogis-teritorial yang terikat oleh garis keturunan dan daerah tertentu, seperti Nagari di Minangkabau.
Istilah masyarakat adat di dunia semakin dikenal sejak pengadopsian Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 169 yang merevisi Konvensi ILO No. 107 tentang MHA. Revisi tersebut melahirkan perubahan dalam pendekatan ILO terhadap MHA, yakni perubahan perlindungan yang sebelumnya didasarkan atas pandangan MHA sebagai masyarakat yang "terbelakang" menjadi perlindungan yang didasarkan pada penghargaan atas kebudayaan MHA, cara hidup mereka yang berbeda, dan tradisi serta kebiasaan mereka (ILO, 2003). Sementara di Indonesia, pengakuan akan eksistensi masyarakat adat telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: