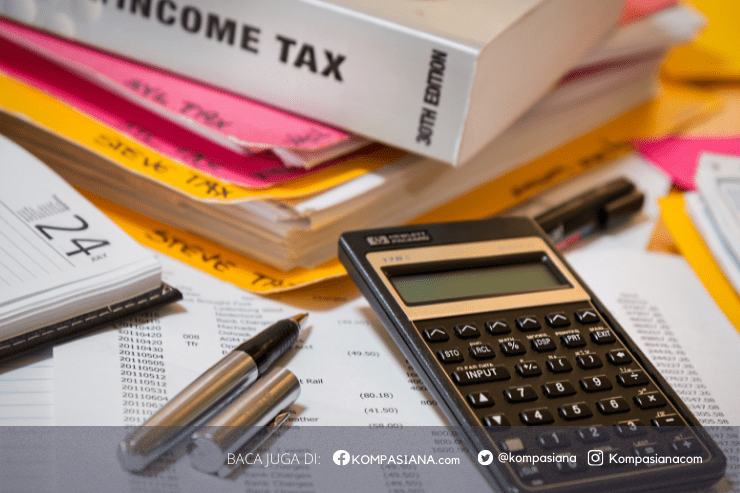Industri perkebunan kelapa sawit dan pengolahan produk turunannya telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah Indonesia. Data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai ekspor minyak kelapa sawit mencapai angka $15 miliar. Jumlah yang besar ini membuat industri minyak kelapa sawit diperkirakan menyumbang sekitar 10% dari pendapatan negara atau 2,5% dari PDB berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lebih lanjut, industri minyak kelapa sawit turut berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, menjamin ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak konsumsi, serta pembangunan infrastruktur dan berbagai program pembangunan dari pendapatan sektor industri minyak kelapa sawit. Melihat pentingnya industri minyak kelapa sawit bagi pemerintah, terlebih masyarakat Indonesia, kita tidak perlu heran ketika media memberitakan bahwa pemerintah Indonesia mulai melakukan hilirisasi untuk produk minyak kelapa sawit. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi dan manfaat dari industri minyak kelapa sawit bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia itu sendiri.
Langkah pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan potensi industri minyak kelapa sawit bukannya tanpa hambatan berarti. Uni Eropa, sebagai salah satu mitra ekspor produk turunan kelapa sawit berupa biodiesel, menyerukan pelarangan ekspor minyak kelapa sawit terhadap negara eksportir kelapa sawit, salah satunya adalah Indonesia. Seruan dari Uni Eropa ini terwujud dalam Renewable Energi Directive II (RED II) yang menggunakan dalih permasalahan lingkungan dan pelanggaran HAM. RED II ini memiliki dampak signifikan berupa pengurangan subsidi serta prosedur baru dalam pengaturan kriteria keberlanjutan dan pelabelan terhadap produksi biodiesel. Hal-hal tersebut tentunya menyulitkan produsen biodiesel berbahan minyak kelapa sawit, baik dalam hal memenuhi kriteria tambahan yang diwajibkan maupun menemukan pasar yang bersedia membeli produk biodiesel nonsubsdi.
Kita perlu tahu terlebih dahulu sejarah perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia yang mungkin berkorelasi dengan alasan dibalik seruan Uni Eropa terkait larangan ekspor biodiesel berbahan bakar sawit. Berdasarkan paper yang ditulis Ian Bourke dengan judul Trade in Forest Products: A Study of the Barriers Faced by the Developing Countries, industri kelapa sawit di Indonesia bermula ketika aktivitas penebangan mulai marak dilakukan pada medio 1970-an. Waktu itu Indonesia adalah salah satu eksportir kayu terbesar di dunia. Aktivitas penebangan ini membuka akses menuju kawasan hutan yang belum terjamah sebelumnya. Ditambah dengan permintaan minyak nabati yang meningkat saat itu, pendapatan dari ekspor kayu yang mencapai $10.000 tiap hektarnya adalah modal yang cukup untuk mengembangkan industri kelapa sawit. Masalahnya dimulai ketika pemerintah Orde Baru membagi-bagikan tanah yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit kepada kawan-kawan politiknya guna menjaga hubungan politik. Pemberian tanah ini berarti pemilik tanah dapat melakukan apa pun terhadap tanah pemberian pemerintah waktu itu. Lebih lanjut, pemberian tanah ini umumnya akan diikuti dengan pemberian izin ilegal terhadap pendirian perkebunan kelapa sawit oleh pejabat yang menerima tanah tersebut secara de facto. Perkebunan kelapa sawit ilegal ini tentunya tidak memperhatikan prosedur keberlanjutan lingkungan dengan aktivitas deforestasi yang tidak diimbangi dengan kegiatan reboisasi. Hal inilah yang dijadikan klaim Uni Eropa bahwa industri sawit adalah penyebab deforestasi dan perubahan iklim serta pelanggaran HAM berupa pekerja anak, pekerja paksa, diskriminasi gender, dan penggunaan bahan kimia berbahaya.
Pemerintah Indonesia telah mengajukan banding ke WTO terkait larangan ekspor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sembari menunggu kepastian, pemerintah Indonesia dapat mengupayakan hal-hal lain yang akan memperbesar kemungkinan Uni Eropa mencabut larang tersebut. Pertama, memenuhi tuntutan Uni Eropa mengenai Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO ini setidaknya menuntut 7 poin utama, yaitu transparansi, penegakan hukum, kelayakan ekonomi dan finansial jangka panjang, praktik terbaik, konservasi alam, hak pekerja dan individu, serta pengembangan berkelanjutan. Tidak bisa dipungkiri, ketujuh tuntutan ini akan menambah pekerjaan bagi pemerintah maupun produsen kelapa sawit. Akan tetapi, jika kita melihat dengan perspektif di masa depan, pemenuhan ketujuh tuntutan ini akan menjamin keberlangsungan industri kelapa sawit di Indonesia. Dalam memenuhi tuntutan ini, pemerintah Indonesia tidak harus mengupayakan ketujuh tuntutan untuk diselesaikan secara bersamaan. Pemerintah dapat memenuhi tuntutan secara bertahap dengan bukti yang disertakan. Bukti ini adalah instrumen penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah kita berupaya dan berkomitmen dalam melanjutkan hubungan dagang dengan Uni Eropa. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah berfokus ke mitra dagang lain sembari memenuhi tuntutan RSPO. Berdasarkan data dari Statista, India, Tiongkok, dan Pakistan adalah tiga negara dengan jumlah impor minyak kelapa sawit terbesar pada tahun 2023. Total nilai impor dari ketiga negara tersebut mencapai $16 miliar. Jumlah tersebut jauh melampaui kombinasi empat negara Uni Eropa dengan jumlah impor minyak kelapa sawit terbanyak, yaitu Belanda, Italia, Spanyol, dan Jerman, yang hanya menyentuh angka $5 miliar. Dengan pangsa pasar yang jauh lebih menguntungkan, menekankan fokus ekspor terhadap India, Tiongkok, dan Pakistan akan menambah pendapatan negara secara signifikan. Lebih lanjut, tambahan pendapatan ini dapat digunakan sebagai biaya pemenuhan tuntutan RSPO sehingga progresnya dapat terus dijalankan, bahkan dipercepat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H