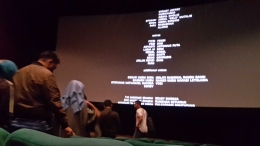Usai sudah Festival Film Indonesia (FFI) 2017 di Manado. Pada malam puncak penganugerahan Piala Citra, 11 November lalu, Film Night Bus bersiang ketat dengan Pengabdi Setan. Night Bus menyabet enam penghargaan, termasuk Film Terbaik, sedangkan Pengabdi Setan meraih tujuh penghargaan kendati bukan untuk kategori film terbaik.
Kedua film di atas seolah menggambarkan sudah semakin tipisnya perbedaan film festival dengan film komersial. Maksudnya, dulu diakui atau tidak, terdapat dikotomi bahwa film yang menang di festival terkesan serius, idealis, dan mengajak penonton berpikir tentang kondisi sosial, budaya, sejarah, politik, atau topik lain yang digambarkan dalam film tersebut. Karenanya film beginian biasanya tidak laku di pasaran. Masyarakat kan maunya membeli tiket bioskop untuk dihibur, bukan diajak berpikir.
Sebaliknya film komersial biasanya ceritanya gampang ditebak, penuh kisah menjual mimpi, lucu-lucuan, atau sensasi horor yang menegangkan. Penonton berjubel, produser meraup laba, bintang film-nya jadi ngetop, tapi keok saat dibawa berlaga di berbagai festival. Padahal ukuran bermutu tidaknya sebuah film, ya di festival itu.
Nah, di FFI 2017 di atas, Night Bus adalah adalah gambaran film idealis yang jeblok di pasaran, Sedangkan Pengabdi Setan adalah film horor yang dibikin tidak asal jadi, dan sangat mempertimbangkan aspek sinematografi. Barangkali saja ke depan, para produser dan sutradara film makin sering saling belajar, sehingga bukan tidak mungkin akan semakin banyak film nasional yang bermutu sekaligus laku.
Terlepas dari FFI di atas, ada satu film nasional yang tidak ikut bertarung, tapi sudah menuai banyak pujian di beberapa festival film internasional. Film ini menjadi satu-satunya film dari Asia Tenggara yang terpilih untuk diputar di festival yang sangat bergengsi di Cannes, Perancis, Mei 2017 lalu.
Film tersebut karya sutradara muda Mouly Surya yang berjudul Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak (Selanjutnya ditulis Marlina).Setelah melanglang buana, akhirnya film ini pulang kandang untuk bisa dinikmati publik sejak 16 November lalu. Seberapa besar dampak berita apresiasi yang diterima Marlinadi Perancis itu akan terjawab dengan seberapa lama tahannya di layar bioskop.
Kalau melihat hanya sebelas dari puluhan bioskop di ibukota yang memutar Marlina, terlihat ada kesan pesimis dari pihak manajemen bioskop. Tapi bila sambutan publik luar biasa, maka bisa saja ada penambahan jumlah layar bioskop yang memutar.
Saya yang menonton pada hari ke 4 (Minggu 19/11) di sebuah bioskop di Jakarta Selatan, melihat animo yang sedang-sedang saja. Bioskop hanya terisi separo. Tapi saya melihat ekspresi kepuasan dari banyak penonton termasuk dari komentar mereka yang sempat saya dengar.
Betapa tidak. Penonton pasti terpukau dengan keindahan padang rumput yang amat luas di Sumba yang muncul hampir sepanjang film. Tapi memang penonton diajak merenung, karena di balik keindahan itu, masyarakat Sumba digambarkan masih hidup dalam kondisi yang amat memprihatinkan.
Gubuk yang menjadi tempat tinggal, kuda dan truk tua yang menjadi alat transportasi umum, ketiadaan biaya untuk menguburkan jenazah sehingga menjadi mumi di rumah gubuk, mungkin bisa menjadi indikator tingkat perekonomian yang masih rendah. Dan yang parah, kaum lelaki merasa berkuasa merampas hak-hak wanita.
Itulah yang dialami Marlina, yang diperankan secara apik oleh Marsha Timothy. Ia yang tinggal sendiri setelah ditinggal mati anak lelakinya yang telah dikubur dan suaminya masih dimumikan di gubuk tempat tinggalnya, didatangi segerombolan lelaki yang mengambil binatang ternak milik Marlina. Satu di antaranya, Markus (diperankan Egi Fedly), memperkosa Marlina.
Namun itulah puncak sensasi film ini, ketika Marlina dalam keadaan sangat terdesak, berhasil mengambil pedang milik Markus dan memenggal kepala si pemerkosa yang lagi berada pada puncak syahwatnya. Besoknya Marlina yang masih dengan ekspresi mendapat tekanan batin yang hebat dengan "jantan" menenteng penggalan kepala Markus itu untuk melapor ke kantor polisi.
Tahun berapa kisah itu terjadi tidak tercantum di film. Soalnya, kantor polisi terlihat demikian kusam dengan mesin tik tua yang dipakai petugas saat menerima laporan. Tapi melihat sudah ada telpon genggam murahan yang digunakan oleh penduduk desa terpencil, tentu diperkirakan masih cocok dengan konteks kekinian.
Banyak yang terpikir saat dan sesudah menonton film ini. Meskipun ini hanya kisah rekaan yang ditulis Garin Nugroho (nama besar di perfilman nasional), tapi tentu berdasarkan riset dan pengamatan yang tajam atas kondisi sosial di Sumba.
Begitu rendahnya harkat wanita sehingga Marlina harus menyelesaikan dengan caranya sendiri yang terkesan brutal dan tentu saja melawan hukum. Namun itulah satu-satunya pilihan yang ada kalau tidak mau harga dirinya diinjak-injak. Ironisnya, Marlina dihadapkan dengan birokrasi yang lamban saat ingin bertanggung jawab, karena ternyata melapor ke polisi tidaklah menyelesaikan masalah.
Mungkin fakta yang ada sekarang di Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur yang eksotis dan mulai menggeliat pariwisatanya, tidaklah separah yang ada di film. Namun bagaimanapun film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton oleh mereka yang berusia di atas 17 tahun. Kalaupun tidak mau berpikir yang "berat-berat", menikmati alamnya saja sudah memanjakan mata layaknya menonton film cowboy zaman dulu.
Bila daya tahan Marlina hanya sebentar saja di bioskop, sungguh sayang karena publik kehilangan kesempatan untuk menonton film sebagus itu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H