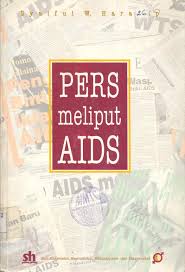Kamis, 9 Februari 2017, diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini kegiatan dipusatkan di Kota Ambon, Maluku, yang dihadri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seiring dengan perjalanan panjang pers nasional yang juga berperan dalam kemerdekaan, patut juga dipertanyakan peran akrif pers nasional dalam ‘perang’ melawan penyebaran HIV/AIDS karena catatan menunjukkan peran pers nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS sangat rendah sekali.
Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 20 November 2016 menyebutkan sampai tanggal 30 September 2016 kasus kumulatif HIV/AIDS di Indonesia tercatat 302.004 yang terdiri atas 219.036 HIV dan 82.968 AIDS dengan 10.132 kematian. Secara global kasus HIV/AIDS di akhir tahun 2015 mencapai 36,7 juta dengan 1,1 juta kematian. Dengan kondisi seperti ini Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara di Asia yang pertambahan kasus HIV-nya tercepat.
Jika dikaitkan dengan epidemi HIV, maka angka-angka itu tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat karena epidemi HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Angka yang dilaporkan atau terdeteksi (digambarkan sebagai puncak gunung es yang muncul ke atas permukaan air laut) yaitu 302.004 hanya sebagian kecil dari kasus yang ada (digambarkan sebagai bongkahan gunung es di bawah permukaan air laut). Estimasi dan proyeksi HIV/AIDS yang diterbitkan oleh Ditjen PP & PL, Kemenkes RI, jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia ada pada angka 608.667 (Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2011-2016, Jakarta, 2014).
Artinya, sejumlah penduduk, terutama laki-laki dewasa, yang mengidap HIV/AIDS di masyarakat tidak terdeteksi karena mereka tidak menunjukkan gejala-gejala yang khas AIDS dan tidak ada pula keluhan kesehatan terkait AIDS. Orang-orang yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi jadi mata rantai penularan HIV di masyarakat, al. melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah.
Angka itu diperoleh dari tes terhadap pasien-pasien penyakit terkait HIV/AIDS di rumah sakit, tes HIV terhadap ibu hamil, tes wajib bagi penyalahguna narkoba (narkotika dan bahan-bahan berbahaya) dengan jarum suntik secara bersama-sama, tes sukarela, dll. Belakangan ini ‘pencarian’ kasus HIV/AIDS bersifat pasif yaitu menunggu orang berobat ke rumah sakit jika ada gejala terkait AIDS kemudian dianjurkan tes HIV.
Celakanya, pemerintah sama sekali tidak bisa menjalankan program yang konkret yaitu pemakaian kondom untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki dewasa, terutama melalui hubungan seksual dengan pekerja seks komersial (PSK) langsung. Program tidak bisa dijalankan karena kecaman dan penolakan yang sangat kuat dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat. Soalnya, program itu hanya bisa dijalankan jika praktek pelacuran yang melibatkan PSK langsung dilokalisir dan kondom tidak ditolak.
Dari 17 ‘pintu masuk’ HIV ke masyarakat yang paling potensial adalah melalui laki-laki yang perilakunya berisiko tinggi tertular HIV yakni sering melakukan hubungan seksual tanpa memakai kondom dengan PSK langsung dan PSK tidak langsung. Dengan menjalankan program penanggulangan di hulu yaitu pada laki-laki berisiko tinggi akan menurunkan penyebaran HIV di masyarakat.
Di awal tahun 1990-an ahli-ahli epidemilogi internasional sudah mengingatkan Thailand bahwa HIV/AIDS akan menjadi persoalan besar di Negeri Gajah Putih itu jika tidak dilakukan langkah-langkah penanggulangan yang konkret. Sayang, pemerintah di sana menampiknya al. dengan alasan negara itu didiami oleh penduduk yang berbudaya dan beragama.
Tapi, apa yang terjadi satu dekade kemudian? Kasus HIV/AIDS di sana mendekati angka 1.000.000. Biaya untuk penanggulangan HIV/AIDS secara langsung dan tidak langsung pada tahun 2000 saja menghabiskan dana 2,2 miliar dolar AS ini setara dengan 2/3 dana yang diperoleh dari sektor pariwisata.
Pemerintah Thailand pun langsung bergegas merancang program yang komprehensif untuk menanggulangi AIDS. Maklum, lorong-lorong di rumah sakit penuh sesak karena tempat tidur tidak cukup menampung pasien dengan penyakit terkait AIDS. Thailand menjalankan lima program dengan skala nasional secara simultan.
Mr Condom
Program di urutan pertama adalah meningkatan peran media massa sebagai media pembalajaran masyarakat tentang cara-cara melindungi diri agar tidak tertular HIV/AIDS. Bersamaan dengan itu diluncurkan pula program berupa sosialisasi kondom sebagai alat untuk mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual di uturan kelima (Integration of AIDS into National Development Planning, The Case of Thailand, Thamarak Karnpisit, UNAIDS, December 2000).
Memang, enolakan terhadap sosialisasi kondom juga terjadi di banyak negara. Di Thailand, misalnya, program ‘wajib kondom 100 persen’ bagi laki-laki yang melacur dengan PSK di lokalisasi pelacuran dan rumah bordir juga dikecam. Tapi, berkat dukungan media massa program itu berjalan lancar dan berbuah manis dengan salah satu indikator yaitu penemuan kasus HIV/AIDS yang terus menurun drastis di kalangan calon taruna militer ketika tes kesehatan. Pengagas program kondom ini adalah Mechai Viravaidya yang dikenal sebagai Mr. Condom di Thailand dngan semboyan “made Thailand a better place for life and love”. Mechai pun menerima hadiah “Magsaysay” tahun 1994.
Pemberitaan yang objektif dan konsisten pun mendorong banyak kalangan menyingsingkan lengan baju membantu pemerintah menanggulangi HIV/AIDS. Pasien yang tidak bisa ditampung rumah sakit langsung dibawa oleh bhiksu ke vihara. Itu gambaran ril betapa media massa berperan besar dalam memasyarakatkan penanggulangan HIV/AIDS. Tapi, itu ‘kan di Thailand.
Bagaimana dengan di Indonesia?
Sejak awal epidemi HIV/AIDS yaitu di tahun 1981 pemberitaan media massa nasional berkutat pada mitos (anggapan yang salah). Mulai dari soal penyakit orang asing, penyakit bule, penyakit pelacur, penyakit perilaku menyimpang, penyakit kutukan, dst. (Syaiful W. Harahap, Pers Meliput AIDS, PT Sinar Harapan-The Ford Foundation, Jakarta, 2000). Celakanya, sampai sekarang pun tetap saja ada berita yang mengait-ngaitkan penularan HIV/AIDS dengan mitos.
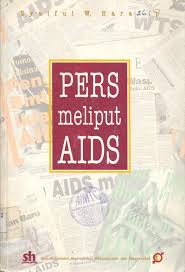
Yang lebih menyedihkan adalah ada berita yang justru tidak memberikan pencerahan tentang langkah penanggulangan AIDS, malahan mendukung pengecam yang menolak lokalisasi dan kondom. Ini terjadi karena ada wartawan yang memakai moralitas dirinya sendiri ketika menulis berita. Banyak berita yang justru berseberangan dengan upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS yang konkret, al. dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berbicara melalut lidahnya dengan moral ketika membicarakan AIDS yang merupakan fakta medis (bisa diuji di laboratorium dengan teknologi kedokteran).
Tidak Berkompeten
Berita pun lebih banyak yang menakut-nakuti daripada meningkatkan kesadaran untuk melindungi diri, misalnya menyebutkan: “penyakit AIDS yang tidak ada obatnya” (padahal ada obat AIDS), “AIDS penyakit mematikan” (padahal belum ada satu kasus pun kematian karena AIDS). Jurnalisme horor seperti ini dikenal di awal epidemi 30-an tahun yang lalu, sehingga tidak pas lagi dipakai saat ini.
Banyak kalangan, bahkan menteri kesehatan, yang menyampaikan statement berupa mitos, tapi wartawan dengan ringan tangan menulisnya dan media pun menyebarlaskan mitos tsb. Misalnya, ada menteri kesehatan yang mengatakan “AIDS tidak mungkin masuk Indonesia karena masyarakatnya berbudaya dan beragama”, ada lagi pernyataan yang menyebutkan “AIDS penyakit bule”. “AIDS penyakit homoseks”, dll.
Kalau saja wartawan sedikit memutar otak tentulah bisa menulis berita yang komprehensif dengan perspektif kesehatan dengan narasumber yang kompeten agar berita AIDS tidak sekedar mitos. Celakanya, ada saja wartawan yang justru mewawancarai narasumber yang tidak berkompeten dalam bidang HIV/AIDS, seperti pemuka agama dan dokter yang membalut lidahnya dengan moral.
Untuk itulah penulis mengembangkan jurnalisme harapan yaitu memberikan pencerahan kepada yang mengidap HIV/AIDS bahwa kehidupan mereka tetap akan berlanjut dengan obat antiretroviral (ARV) serta pola hidup yang baik. Bagi yang sering melakukan perilaku berisiko segera menjalani tes HIV agar tidak mencekalai orang lain, sedangkan bagi yang lain dianjurkan menghindari perilaku berisiko.
Sebagian besar berita HIV/AIDS ditulis wartawan dengan sudut pandang moral dan agama sehingga pesan yang diterima pembaca pun hanya seputar mitos. Dalam banyak berita HIV/AIDS selalu dikaitkan dengan ‘seks bebas’, seks menyimpang, di luar nikah, bukan dengan pasangan resmi/sah, seks pranikah, pelacuran, dll. Tentu saja ini tidak akurat karena penularan HIV melalui hubungan seksual bukan karena sifat hubungan seksual (seks bebas, seks menyimpang, dll.), tapi karena kondisi saat terjadi hubungan seksual yaitu salah satu atau kedua-duanya mengidap HIV/AIDS dan laki-laki tidak memakai kondom.
Selain itu dalam banyak berita HIV/AIDS tidak disebutkan cara-cara penularan dan pencegahan ang realistis. Pemakaian kata yang tidak baku dalam berita juga membuat informasi tentang HIV/AIDS tidak jelas. Misalnya, kondom disebut sebagai ‘pengaman’. Ini jelas tidak baku karena ‘pengaman’ tidak otomatis pengertiannya adalah kondom.
Selama media massa, media online dan media sosial di Indonesia tetap membalut informasi HIV/AIDS dengan moral, maka selama itu pula insiden infeksi HIV baru dan penyebaran di masyarakat terus terjadi secara terselubung karena terjadi tanpa disadari oleh orang-orang yang mengidap HIV/AIDS. Pada akhirnya epidemi HIV terselubung ini jadi ‘bom waktu’ yang kelak bermuara pada ‘ledakan AIDS’. *
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H