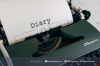Kemarin, saat senja mulai merunduk dan matahari menghilang di balik horizon, saya terjebak dalam kerumunan orang yang sedang mengikuti arak-arakan nyongkolan. Desa terasa hidup, ramai dengan langkah-langkah pengantin dan keluarganya yang berpakaian adat, berjalan sambil bercengkrama. Semua tampak bahagia, penuh warna.
Tapi, ada satu hal yang cukup mengganggu perhatian saya: dentuman keras dari sound horeg yang semakin merajalela. Suara yang menggema sepanjang jalan ini seolah menjadi ciri khas acara tersebut, bahkan lebih dominan daripada iringan musik tradisional yang dulu biasa menemani nyongkolan.
Dulu, nyongkolan begitu khas dengan alat musik tradisional seperti gendang beleq yang menghadirkan irama yang menggugah hati. Sekarang, yang ada justru suara dentuman dari sound horeg, alat musik modern berukuran besar yang seakan tak bisa dipisahkan dari perayaan ini. Bagi sebagian orang, suara keras ini adalah lambang kebanggaan, semangat, dan identitas mereka. “Nyongkolan tanpa sound horeg? Rasanya kurang meriah,” kata seorang pemuda yang ikut dalam rombongan.
Namun, bagi sebagian lainnya, terutama yang punya trauma terhadap gempa atau sedang beristirahat, suara itu adalah gangguan. Kaca jendela bahkan bergetar, dan dinding rumah terasa bergetar. Suara itu menjadi pengingat yang menakutkan bagi mereka yang sensitif terhadap suara keras. Bagi mereka, ini lebih dari sekadar kebisingan, itu adalah gangguan yang menimbulkan kecemasan.
Perdebatan soal sound horeg mulai memanas. Ada yang beranggapan bahwa ini adalah refleksi dari rendahnya kualitas SDM, bahwa suara keras bukan hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga mengganggu kenyamanan warga. Saya mendengar cerita tentang kaca rumah yang pecah, atap warung yang rusak karena getaran dari sound horeg yang lewat.
Namun, ada juga yang melihat sound horeg sebagai bagian dari ekspresi budaya dan hiburan yang sah. Bagi mereka, suara keras adalah bagian dari keseruan dan kemeriahan yang memang sudah seharusnya ada dalam nyongkolan. Bagi mereka, tradisi ini telah beradaptasi dengan perkembangan zaman, mengarah pada modernisasi.
Di satu sisi, saya memahami bahwa tradisi memang harus berkembang, tetapi di sisi lain, saya merasa kehilangan nilai-nilai yang dulu ada dalam nyongkolan—nilai kebersamaan dan silaturahmi. Dulu, nyongkolan adalah momen di mana warga saling mengenal, berbagi kebahagiaan, dan merayakan bersama. Kini, semuanya terasa lebih kepada ajang pamer kebanggaan kelompok.
Mungkin, jawabannya ada di tengah-tengah. Kita tidak perlu sepenuhnya kembali ke bentuk asli tradisi nyongkolan yang lebih sederhana, tapi kita juga harus menyadari bahwa tradisi ini punya esensi yang perlu dijaga. Mungkin, regulasi yang mengatur penggunaan sound horeg bisa menjadi solusi. Pemerintah bisa membatasi volume suara dan waktu penggunaannya agar keramaian tetap bisa dirasakan tanpa mengorbankan kenyamanan warga.
Saya juga berpikir, pendidikan bagi kalangan muda sangat penting. Mereka perlu paham bahwa perayaan yang meriah tidak selalu harus mengganggu orang lain. Dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan, nyongkolan tetap bisa terasa meriah tanpa harus mengorbankan kenyamanan orang lain.
Pada akhirnya, perubahan dalam tradisi adalah hal yang wajar. Tradisi memang harus mengikuti zaman, tetapi nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya tidak boleh hilang. Nyongkolan harus tetap hidup, berkembang, dan relevan dengan zaman, asalkan kita bisa menemukan keseimbangan antara kemeriahan dan kenyamanan bersama.