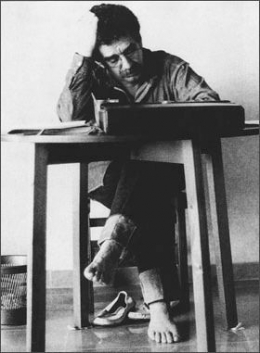Seorang jurnalis seyogianya punya antena yang mampu mendeteksi dan menyerap gelombang realitas sosial. Konsekuensinya, ia seyogianya bersikap dan berlaku etis.
Ini karena seperti dikatakan jurnalis dengan jejak langkah panjang dan cemerlang Sindhunata, "Bagi saya, pekerjaan pertama seorang wartawan adalah pekerjaan kaki, baru kemudian pekerjaan tangan, tulis-menulis."
Jika demikian, berarti jurnalis tulis menjadi mulia justru karena mulai menulis berita dengan kaki kotor. Sekilas itu tampak saling memunggungi. Namun mari coba kita kuliti.
Melampaui Batas
Manusia senantiasa merindukan hidupnya menjadi lebih baik dan lebih bermartabat. Menjalin relasi yang baik dengan manusia-manusia lain merupakan jalan menujunya. Dari situ, dari relasi-relasi itu, mengalirlah berbagai informasi.
Misalnya, seperti ditulis Ashadi Siregar, dkk., informasi ihwal bahaya yang mengancam hidup seperti penyakit, bencana alam, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya; informasi ihwal bahaya yang mengancam atau menekan kebebasan seseorang seperti penahanan tanpa melalui jalur hukum, penggusuran, ketidakadilan ekonomi, dan sebagainya;
informasi yang bertaut dengan kemungkinan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial seperti perkembangan ekonomi, situasi lapangan pekerjaan, arahan untuk menaikkan pendapatan, dan sebagainya; informasi yang mengungkap perkembangan atau penghambat peningkatan kehidupan seperti kemerosotan kehidupan perkotaan, kemajuan pelayanan kesehatan, maraknya hiburan penuh maksiat, dan sebagainya.
Seseorang, yang selanjutnya kita sebut saja Brongkos, mengolah informasi-informasi begitu menjadi pengetahuan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat waktu dalam menghadapi kendala-kendala dan memanfaatkan peluang-peluang. Sehingga, betapa pun gunung Sinabung meletus lagi dan perampokan semakin sering terjadi, misalnya, Brongkos dapat melangkah mendekati yang yang dirindu-rindukannya.
Jika ada yang bertanya apa yang membuat Brongkos bisa begitu, saya bayangkan, ia menjawab dengan mengutip Gabriel Marcel, "Aku berkomunikasi dengan diriku secara efektif hanya sejauh aku berkomunikasi dengan orang lain." Saya bayangkan begitu karena memang begitulah.
Hanya dengan berkomunikasi dengan orang lain seseorang dapat mengenali dirinya. Dan ketika seseorang mengenali dirinya, ia pun dapat mengenali ruang tempatnya berada. Ia juga bisa tahu apa yang harus dilakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Jadilah hari ke hari hidupnya antisipatif, membaik, dan martabatnya menarik.
Namun, tidak ada seorang pun yang berhubungan baik dengan semua orang di seluruh dunia. Jangankan begitu, bisa dipastikan tak seorang pun warga sebuah kota kecil yang berhubungan baik dengan semua warga kota tersebut. Padahal, embusan napas dan gerak langkah orang-orang saling mempengaruhi. Embusan napas dan gerak langkah seseorang pun mempengaruhi cacing, tanah, rerumputan, hutan, angin gunung, debur ombak, bahkan bentangan langit. Begitu pula sebaliknya.
Akibat terbatasnya relasi baik tersebut terbatas pulalah informasi yang bisa didapat oleh setiap orang. Terbatas pula kapasitas setiap orang untuk memungkinkan realitas menjadikan hidup mereka membaik dan semakin bermartabat. Maka cemas, gundah, frustrasi, stres, insomnia, dan sebagainya menjadi kerap mencengkeram mereka. Keresahan sosial pun menjadi seperti lumut dan lumpur di musim hujan. Ekspresinya pun beragam.
Pemerintah pun terlanda dampaknya. Berbagai kebijakan dan peraturan dibuat untuk mengatasinya. Namun sekeras-keras usaha pemerintah tetap saja aksesnya ke informasi, dan dengan sendirinya akses ke kompleksitas realitas, terbatas. Maka seperti ruang-ruang di wilayahnya, ruang-ruang pemerintahan pun diguncang-guncang gundah.
Di situlah media massa terbit. Jurnalisme beroperasi. Jurnalis berkreasi. Terbitnya, operasinya, kreasinya adalah untuk memungkinkan terlampauinya batas perolehan informasi, untuk memenuhi kebutuhan informasi orang-seorang, komunitas-komunitas, dan pemerintahan serta institusi-institusi lainnya. Negara pun menjadi mungkin berkembang menjadi rumah bersama. Dan di situ, berkembang serta berbuahlah kebaikan bersama.
Itulah demokrasi kita, cita-cita luhur para pendiri bangsa kita. Demokrasi yang mereka cita-citakan bukan saja demokrasi politik, tapi juga demokrasi ekonomi. Jika demokrasi politik belaka, jadi seperti Prancis dahulu kala, juga mungkin sekarang. Yang dicapainya sebatas kemerdekaan politik (memilih dalam pemilu). Kesetaraan dan persaudaraan jauh panggang dari api. Demokrasi kita pun, seperti berulang dinyatakan para pendiri bangsa, sudah berabad-abad berakar di dusun-dusun Nusantara. Jadi, negara kita ini sangat besar kemungkinannya menumbuhkan demokrasi yang merupakan pelakasanaan kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan.
Berita Menghipnotis
Akan tetapi, untuk itu jelas dibutuhkan informasi, dibutuhkan berita. Apalagi hari ini. Tak satu pun negara terisolasi. Politik, ekonomi, dan teknologi komunikasi menjadikan batas-batas teritori bisa dikata mencair. Kebutuhan akan berita menjadi lebih besar lagi.
Berita yang dibutuhkan tentulah bukan karangan, bukan berita menyesatkan seperti, misalnya, berita mengenai pandemi Covid-19 yang disebarkan Donald Trump baik melalui media sosial atau brifing pers Gedung Putih. Pada Februari 2020, dalam wawancara dengan jurnalis legendaris Bob Woodward, Trump mengaku bahwa ia tahu bahaya virus korona baru.
Virus ini disebutnya menyebar melalui udara dan jauh lebih mematikan daripada flu berat. Tapi Trump selalu ingin mengecilkannya. Inilah yang membuatnya terus menyebarkan penyangkalannya bahkan sampai setelah ia terinfeksi. Jadilah "America First" di dunia dalam hal warga yang terjangkit Covid-19 dan meninggal akibatnya.
Begitulah jika berita palsu terus menyebar, menjalar, dan mengakar. Bisa jadi bahkan akibatnya jauh lebih mengerikan lagi. Tentu saja itu bukanlah tugas jurnalis. Tugas jurnalis tulis adalah menulis seperti dikatakan Gabriel Garcia Marquez ketika menjadi mentor lokakarya reportase kepada tiga puluh orang jurnalis Amerika Latin.
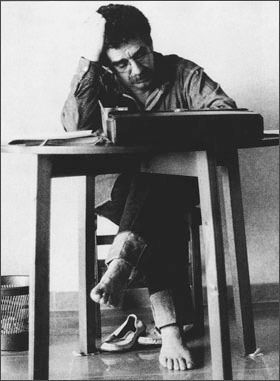
"Reportase adalah cerita lengkap, rekonstruksi utuh sebuah peristiwa. Tiap detil kecil punya makna. Inilah dasar kredibilitas dan kekuatan cerita," ucap Gabo dalam lokakarya yang diadakan Yayasan Jurnalisme Ibero-Amerika Baru tersebut.
Pada kesempatan yang sama di tahun 1995 itu, Gabo pun tegas mengatakan apa itu menulis bagi seorang jurnalis. "Menulis adalah aksi menghipnotis," ujarnya. "Jika berhasil, si penulis telah menghipnotis pembaca. Manakala ada ganjalan, pembaca pun terjaga, keluar dari hipnotis dan berhenti membaca. Bila prosanya pincang, pembaca pun meninggalkanmu. Orang harus membuat pembaca terhipnotis dengan merawat setiap detail, setiap kata. Ini aksi berkelanjutan di mana kalian meracuni pembaca dengan kredibilitas dan dengan irama."
Dari situ, teranglah bahwa tugas jurnalis tulis adalah "meracuni pembaca". Meracuninya "dengan kredibilitas dan dengan irama", dengan "cerita lengkap, rekontruksi utuh sebuah peristiwa" yang setiap detilnya punya makna.
Dengan tulisan demikian pembaca terhipnotis. Dan sehabisnya, cakrawala pembaca meluas. Pengetahuan dan daya analisanya bertambah. Langkahnya pun tegap menempuh jalur temuan penalarannya yang menginsyafi konpleksitas.
Syarat untuk menulis sebagai aksi menghipnotis pun terang sudah. Untuk dapat merangkai cerita lengkap, untuk dapat merekontruksi secara utuh peristiwa, untuk mendapatkan setiap detil yang bermakna, jurnalis tak bisa hanya dengan mengangkat telepon dari kantor redaksi. Ia harus turun ke lapangan yang kotor. Melakukan pengamatan yang terarah dan cermat. Mewawancara sumber pertama dengan plastis dan jeli. Dan mengupayakan untuk melakukan riset dokumentasi dengan teliti. Menempuh proses demikian memungkinkan jurnalis juga tidak hanya sampai di peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sosial, melainkan dapat mengendus gejala sosial.
Kesanggupan mengendus gejala sosial tersebut memungkinkan si jurnalis dapat mengidentifikasi dan memilih fakta secara jernih dan kritis. Juga dapat menjadikan pancaindra jurnalis menjadi lebih peka, hal yang penting baik untuk mengakses ke dalam kompleksitas realitas atau untuk merekontruksi peristiwa dengan setiap detil yang bermakna.
Namun, semua temuan tersebut barulah bermakna jika si jurnalis kemudian berhasil menuliskannya dengan menulis sebagai aksi menghipnotis. Di atas, Gabo mengucap bahwa untuk menghipnotis pembaca, selain "dengan kredibilitas", adalah juga "dengan irama". Yang dimaksudkannya tentulah bukan dengan rangkaian kata yang mendayu-dayu. Yang dimaksudkannya lebih sebagai tuntutan agar jurnalis menulis dengan mengerahkan pelbagai daya bahasa, termasuk daya musikalnya.
Pengerahan pelbagai daya bahasa memungkinkan bahasa menyelami dan mendedahkan lapisan dalam realitas bukan saja dengan dayanya menciptakan pengertian yang menyasar nalar, tapi juga dengan menerbitkan berbagai asosiasi yang membangkitkan pancaindra. Penerbitan berbagai asosiasi ini pun bukan gaya-gayaan belaka, tapi justru demi akurasi. Rekontruksi peristiwa dengan begitu bisa menjadi lebih setia, meyakinkan, dan menggerakkan pembaca ke arah kebaikan bersama.
Pemungkin mewujudnya tulisan jurnalis seperti itu bukan saja kompetensi teknis yang merupakan hasil latihan yang sistematis dan disiplin dari hari ke hari selama bertahun-tahun, tapi pun praktik etis, pengamalan etika. Terkait bahasa misalnya. Kita tahu bahasa adalah lembaga sosial. Keberadaannya menentukan kehidupan seseorang, menentukan kehidupan sekelompok orang, menentukan kehidupan sebuah bangsa, menentukan kehidupan seluruh umat manusia. Maka ketika jurnalis meningkatkan daya bahasa dalam menerangi lapisan-lapisan realitas, teranglah ia memenuhi tanggung-jawabnya selaku manusia terhadap kemanusiaan.
Dan pemenuhan tanggung-jawab itu dicapainya pula dengan membikin pembaca terhipnotis. Inilah yang, maaf beribu maaf, baru sampai di harapan ketika saya membaca tulisan demi tulisan para peserta lomba menulis jurnalistik Kabupaten Karo. Kita agaknya mau tidak mau harus bekerja keras dan disiplin untuk memungkinkan para jurnalis masing-masing punya antena.
Keharusan tersebut bisa jadi berat. Namun, dari Shimmen Takezo ke Miyamoto Musashi, dicapai Musashi dengan sedikitnya tiga tahun tidak melihat matahari. Selama tiga tahun, di sebuah kamar yang lembab dan nyaris gelap di menara Puri Himeji, Musashi tidak pernah pula bicara dengan siapa pun. Setiap hari ia melulu membaca buku-buku dan merenung. Inilah yang membuatnya lahir sebagai manusia baru.
Manusia yang memilih setia menempuh Jalan Pedang, sebuah jalan yang bukan saja "tidak makan dengan pedang, tapi dengan sumpit", melainkan terutama sebuah jalan, seperti dikatakan samurai tak bertuan yang sampai akhir hayatnya selalu memenangkan pertempuran itu, "untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bijaksana." Perubahan personal ini tampak remeh memang. Namun Yoko Ono mengucap,
"Mengubah diri sendiri adalah mengubah dunia."

Pengakuan berhasil atas gerakan yang dipimpinnya terutama karena gerakan petani yang sohor dengan sebutan Zapatista itu orientasinya bukan merebut kekuasaan atas nama rakyat, tapi swakelola pertanian adat minoritas. Jantung gerakan ini adalah paduan politik dan sastra. Paduan ini sudah terlihat ketika Marcos pertama kali datang ke Chiapas, tahun 1983, untuk bergabung dengan gerakan gerilya yang baru terbentuk. Isi ranselnya bukanlah amunisi, tapi novel-novel dan kumpulan puisi para penulis besar Amerika latin seperti Gabo, Julio Cortazar, Vargas Llosa, dan Octavio Paz.
Sebagai pamungkas, mohon izinkanlah saya mengutip sebuah haiku karya Kobayashi Issa yang saya rasa bertaut erat dengan perkara keuletan:
Siput yang kecil
Pelan-pelan mendaki
Gunung Fuji
VBI-28 November 2020
(Ditulis sebagai catatan atas Lomba Menulis Jurnalistik di Kabupaten Karo)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H