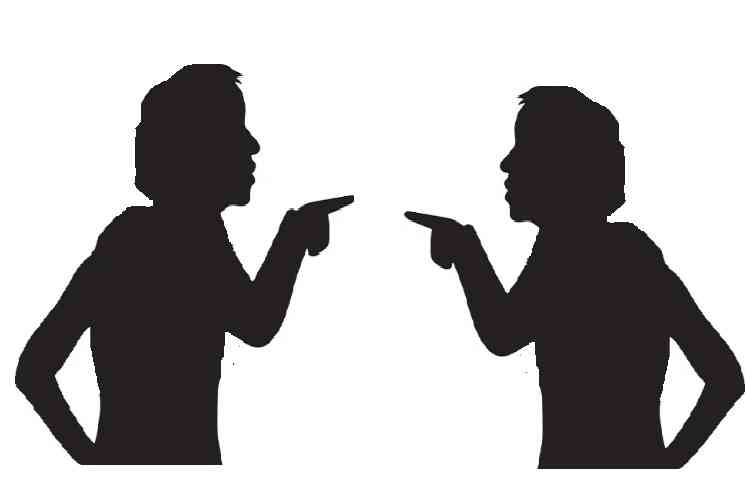Seteru, yang identik dengan pandangan negatif, kiranya dapat menjadi latar belakang dimulainya era kampanye jelang perhelatan Pemilu. Persoalan yang kerap mewarnai panggung media publik, dengan narasi politis dari masing-masing calon kompetitor. Inilah tradisi menarik, dan selalu identik dengan aksi-aksi memukau melalui manuver membangun stigmatisasi publik.
Baik dalam narasi positif atau negatif, suasana saling "serang" menjadi realitas unik yang marak beredar di berbagai media. Unik dalam perspektif rutinitas yang kalau tidak terjadi, konon perhelatan Pemilu dianggap tidak menarik. Hal ini yang selalu memberi pandangan negatif dari publik dalam menilai para calon wakilnya di pemerintahan.
Namun, inilah dinamika perpolitikan Indonesia saat ini. Manuver-manuver dan intrik yang terjadi biasanya akan berakhir dengan sikap legowo. Walau tidak dipungkiri ada rasa yang kurang, bagi mereka yang dianggap kalah. Percaturan politik memang tidak bisa dilihat secara abstrak. Tidak pula dapat diprediksi seperti apa yang tampak di hadapan mata.
Hari ini si A mendukung si B, esok bisa jadi si B mendukung si C, atau tiba-tiba di akhir waktu si C mendadak mendukung si A. Walau telah ada kontrak politik dan kerjasama (koalisi) dalam mengusung calonnya. Hal ini tentu lumrah adanya, apalagi bagi para calon atau kontestan yang telah dipilih oleh para pengusungnya.
Jikalau Marx memperspektifkan sebagai bentuk pertentangan kelas, biasanya ini pula yang terjadi di lapangan. Bagi para pendukung, pertentangan kelas merupakan suatu hal yang mudah dijadikan pemantik konflik atas dasar identitas. Nah, politik identitas mulai dapat dikembangkan pada locus ini. Dimana secara primodial hal ini masih kerap terjadi pada masyarakat "arus bawah".
Maka pendekatan Marx dapat dikorelasikan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang mempersepsikan konflik sebagai bentuk dari perbedaan antar individu dengan kelompok sosial tertentu. Pada area ini, demokratisasi tentu saja "terancam" eksistensinya. Ada pola yang kemudian kerap berakhir secara anarkis pada pendekatan teori sosial.
Tidak tanggung-tanggung, teori konflik yang berakhir pada tindakan anarkis sudah barang tentu menjadi rekam jejak sejarah bangsa Indonesia. Tepatnya sejak perhelatan Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Masih menurut Soerjono Soekanto, konflik berlandaskan politik inilah yang kerap meninggalkan "ancaman" hingga masa kekuasaan sang pemenang berakhir.
Nah, kiranya dapat dipahami, bahwa konflik yang berlatar politik tentu tidak produktif bagi proyeksi kemajuan bangsa. Apalagi bagi bangsa yang menjunjung tinggi semangat berdemokrasi. Ketika para elite justru berseteru dalam memainkan animo publik, maka dapat dibayangkan bagaimana masa depan bangsa di kemudian hari, jika konflik politik tidak dapat diselesaikan secara paripurna.
Diantaranya ya tentu saja merangkul semua golongan yang berbeda pandangan politik, kala perhelatan Pemilu terjadi. Sebuah sikap yang memiliki daya dukung positif bagi semua kalangan. Ini adalah wujud kebangsaan dalam status kepemimpinan paripurna. Agar konflik yang terjadi dapat diredam dengan baik, tanpa memberi tendensi negatif dari kelompok oposisi.
Namun, ada kiranya oposisi tetap menjadi bagian dari check and balance suatu pemerintahan. Sebagai area kritis yang tidak dapat "dibungkam", sesuai kebebasan berpendapat pada aturan perundang-undangan. Kiranya inilah sisa-sisa area bagi rakyat, untuk menyuarakan dapat melakukan kritiknya terhadap suatu bentuk kebijakan publik.