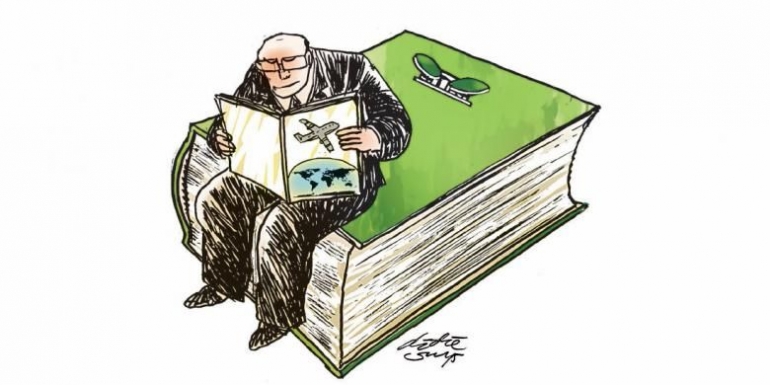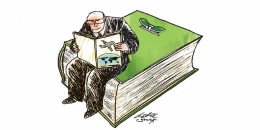Beberapa tahun lalu Raditya Dika tengah berada di Amerika untuk urusan tertentu. Tidak lama, barangkali dua-tiga hari. Sesampainya kembali di Indonesia, Raditya Dika mendapati kabar kalau kucing peliharaannya, Pink, tutup usia.
Pintanya saat itu hanya satu: dikuburnya nanti saja kalau saya sudah sampai di rumah, saya pingin lihat untuk terakhir kalinya. Sayang, permintaan terakhirnya tidak dapat terpenuhi. Mayat Pink sudah keburu menyebarkan bau yang tidak sedap dan setengah badannya telah dikubur.
Raditya Dika sudah punya beberapa kucing. Bisa dibilang banyak, malah. Kucing-kucing itu selain dibeli untuk dipelihara, juga kadang diajaknya sunting untuk beberapa film. Tapi yang pasti, kucing-kucing itu dibeli untuk menemaninya yang tinggal sendiri di rumah.
Untuk kucing yang baru saja tutup usia itu, Pink, didapati Raditya Dika dengan pertemuan yang biasa saja.
Saat sedang memilih kucing di peternak, Pink seperti seorang anak kecil yang ingin diajak main dan bersenang-senang. Dan pada saat itu juga Raditya Dika keluar dari peternak hewan dan membawa Pink.
"Kita tidak pernah memilih kucing, tapi kucing sendiri yang memilih majikannya untuk dipelihara," ujar Raditya Dika.
Tidak ada yang bisa diselamatkan dari kematian, memang, yang tersisa hanya kenangan dan ingatan. Maka setelah Raditya Dika sudah sedikit berdamai dengan kematian Pink, ia membuat semacam video obituary tentangnya. Tentang kali pertama pertemuannya sampai perpisahan terakhirnya di sini.
Saya sepakat untuk itu. Sebab itu tak jauh berbeda dengan buku yang menemui atau memilih sendiri pembacanya. Saya sering mengalaminya. Bahkan lebih sering begitu. Akan saya kisahkan beberapa.
Saya dan Kumcer "Corat-Coret di Toilet", Eka Kurniawan
Ketika hendak berangkat, dari salah satu grup wasap, bertanya: ada yang tahu anggota DPR komisi V yang kompeten untuk jadi pembicara?
Tak lama ada yang menimpali, sebentar dicari dulu.
Entah mengapa, dari tumpukan buku di rumah, saya mengambil satu buku untuk saya baca di kereta. Saya ambil asal saja dan yang terbawa adalah "Corat-coret di Toilet". Saya masukkan ke dalam tas dan saya berangkat.
Membaca cerita-cerita Eka Kurniawan dibuku "Corat-coret di Toeilet" saya kira adalah usaha menjaga rasa penasaran saya terhadap novel terbarunya "O" --yang sampai sekarang belum juga rampung dibaca.
Sebab, barangkali cerita Corat-coret di Toilet adalah ikhwal gaya menulis Eka Kurniawan yang kita kenal sekarang. Banyak sekali fragmen-fragmen yang disusun yang satu sama lainnya terkait dan mengaitkan.
Pada cerita Corat-coret di Toilet, dikisahkan betapa veodalime bisa terjadi di sembarang tempat, termasuk di toilet. Toilet yang baru saja dibersihkan dan dicat ulang.
Corat-coret di toilet, pada hakikatnya, adalah bentuk paling purba dari media sosial kita hari ini.
Sebab corat-coret itu, kadang penting atau tidak, terkadang memang mesti kita keluarkan dalam bentuk apapun --atau tulisan, misalnya.
Dan lalu, corat-coret juga punya arti penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Sebagai contoh, yang kemudian dilakukan oleh pemuda Indonesia ketika baru merdeka, ketika itu, adalah membuat corat-coret di tembok-tembok sepanjang mereka bisa temui. Dari yang bagus sampai yang tak terbaca sekalipun. Coretannya seperti ini: Freedom Indonesia --dan lain sebagainya.
Intinya: mereka ingin memberitahukan bahwa Indonesia telah merdeka. Tapi, yang mereka tidak tahu: pada masa itu hanya sedikit orang Indonesia yang sudah melek huruf.
Jadi, sebanyak apapun coretan, meski bagus, tidak ada yang membaca.
Itu sama halnya dengan orang yang suka foto-foto buku di media sosial, tapi tidak tahu buku yang ia baca itu apa. Eh~
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H