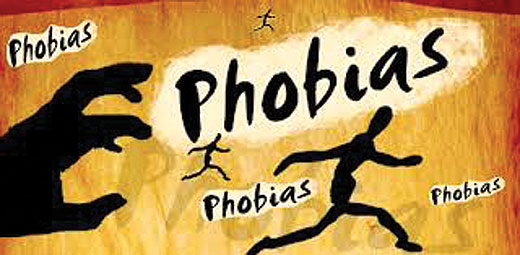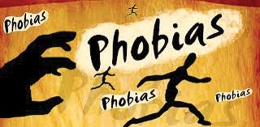Fenomena Ahok ternyata telah memunculkan banyak ketakutan. Ketakutan itu tidak hanya dialami oleh para kaum elit politik (politisi), elit budaya (budayawan), maupun elit agama (agamawan). Bahkan lebih jauh fenomena Ahok juga menciptakan rasa ketakutan pada kalangan pejabat pemerintahan dan masyarakat urban yang terpinggirkan.
Istilah Ahokbia saya adaptasi dan adopsi dari istilah atau konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh seorang tokoh. Seorang tokoh itu biasanya mempunyai pengaruh dan otoritas politik dan atau ilmu pengetahuan dalam menentukan arah suatu pembangunan. Karena itu, seorang tokoh politik atau ilmuwan yang memiliki pengaruh dan otoritas dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu bangsa, maka pada namanya dilekatkan tambahan istilah nomic. Maka kita kenal ada istilah Hattanomic (1), Habibienomic, Hattanomic (2), SBY-nomic, dan mungkin masih ada lainnya.
Fenomena Ahok
Tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi sebuah fenomena tersendiri. Fenomena pertama, pada diri Ahok melekat dua atau lebih identitas minoritas. Identitas mana yang membuat public menggambarkannya sebagai sesuatu yang stigmatis, yang dalam perkembangan sesuai dengan dinamika social dan politik, sering dijadikan sebagai sasaran tembak. Minoritas etnis, agama, dan atau gaya kepemimpinan (leadership styles).
Fenomena kedua, Ahok memposisikan diri sebagai seseorang yang hendak berdiri di luar arus utama (mainstream). Bahkan kadang, karena sikap itu sehingga orang harus menggambarkannya sebagai menentang arus. Kelaziman yang ‘menyenangkan’ selama ini dinikmati oleh sebagian besar elemen masyarakat, elit politik, elit budaya, dan elit agama serta elit pemerintahan, dengan sengaja diterebas. Kesenangan-kesenangan yang sudah menjadi sesuatu yang mentradisi, meski itu harus mengorbankan kepentingan umum, sengaja dihentikan.
Fenomena ketiga, gaya kepemimpinan Ahok yang tanpa kompromi dan tidak tedeng aling-aling membuat sebagian elemen bangsa ini kegerahan. Apalagi harus ditambah dengan model komunikasi politik yang kurang memperhatikan tatakrama, sopan santun ala orang Timur. Model komunikasi politik yang ‘tidak lazim’, yang mana oleh sebagian orang menyebutkannya sebagai bahasa comberan.
Fenomena keempat, Ahok hendak memberikan sebuah kesan yang bersifat monumental ‘ingin dikenang’, sebagai hero. Ahok tidak terlalu mempedulikan efek balik dari sebuah kemungkinan kebijakan yang akan menggerus kepercayaan terhadap dirinya. Baginya, tidak penting untuk terpilih kembali menjabat sebagai seorang Kepala Daerah, jika harus bermanis muka dan berkata ‘lugu’. Ahok ingin menegaskan bahwa untuk membangun sebuah peradaban baru yang lebih memberi harapan untuk semua, maka harus siap menerima resiko. Karena pada setiap pilihan (politik) pasti memiliki resiko sebagai konsekuensi logis atas pilihan itu.
Fenomena kelima, Ahok hendak ingin membangun nilai baru. Nilai kejujuran, spotivitas, kemajemukan dalam kebhinekaan, konsistensi, fairness, komitmen, tanggung jawab, dan keberanian menantang arus. Bahwa bukan merupakan sebuah hal yang muspra dan mustahil, bila kemauan baik yang diikuti dengan kemauan politik serta itikad untuk berbuat baik demi kepentingn bersama, pasti akan menghadirkan sebuah panorama yang indah bagi kebersamaan dalam membangun harmoni bagi semua. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat primordial sekretarian, yang hanya menciptakan inharmonisasi interaksi sosial.
Fenomena keenam, Ahok telah menjadi public enemy (musuh public), khususnya bagi kelompok dan elemen masyarakat yang merasa ‘dirugikan’ karena kehadirannya. Maka berbagai stigma minor dihadirpentaskan ke ranah public untuk mengkapitalisasi kebencian yang membuncah terhadap Ahok. Tidak berhenti hanya di batas itu, Ahok seolah-olah dianggap sebagai ‘penduduk haram’ di negeri Indonesia yang menganut bhineka tunggal ika ini. Karena ‘penduduk haram’, maka haram baginya menjadi pejabat publik, termasuk menjadi Kepala Daerah pada satu daerah territorial di negeri khatulistiwa ini.
Karena tidak ingin langsung membatasi hak Ahok karena ‘keharamannya’, maka doktrin agama pun dipompatuntaskan untuk menyerang Ahok. Umat ‘diintimidasi’ sebagai melakukan tindakan haram bila bukan memilih pemimpin yang seiman dengannya, tapi memilih pemimpin kafir. Meski pemimpin kafir memiliki dan memenuhi semua kriteria sebagai seorang pemimpin yang jujur dan adil. Terjadi gejala ekploitasi nilai religiusitas untuk memanipulasi sentimen dan tingkat keimanan serta kesalehan umat.
Fenomena ketujuh, Ahok dinilai dapat menularkan virus dan pengaruh buruk terhadap sebuah model dan atau style kepemimpinan. Model dan style kepemimpinan yang cenderung menantang arus, meski hal itu demi alasan menghadirkan sebuah contoh peradaban pemerintahan yang bersih dan akuntabel.