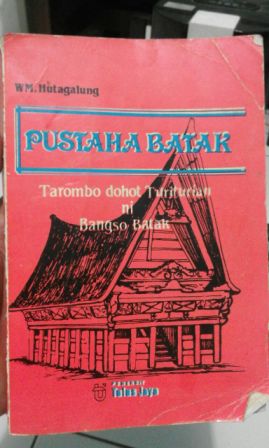Batakologi - Ilmu yang Patut Diseriusi
Sebagai cabang ilmu yang belum populer, termasuk di kalangan orang Batak sekalipun, Batakologi menyimpan sejumlah pembelajaran berikut dinamika klaim-mengklaim khazanah kultural yang ada di dalamnya. Kendatipun sebagian subetnis Batak enggan menyebut diri sebagai orang Batak karena filologi peyoratif yang dominan tercatat di catatan historis tentang keberadaan orang Batak. Tak mudah pula mencari makna aslinya (sebelum di-peyorasi) karena belum ada milestones yang bisa dinapaktilasi secara rapi dan teratur dalam proses diskresi antara periode mitologis (mulai dari Raja Ihat Manisia, si Radja Batak, hingga ke orang Batak zaman ini) dengan periode historis yang sebagian besar dikomando sesuai selera literasi penulis Barat yang sarat dengan agenda misi kekristenan, termasuk upaya politisasi dari pihak kolonial pada zamannya.
Tidak heran kini bahkan dari antara kalangan Batak sendiri, yang kerap bangga menyebut diri sebagai eloquent atau intelligent (kendati pada faktanya mereka bukanlah golongan yang well-disciplined terhadap anasir-anasir sejarah Kebatakan), muncul arus besar yang mengamini bahwa penyebutan Batak adalah semata agenda penjajah Belanda. Kendatipun mereka masih belum sampai pada konklusi "yang namanya orang Batak itu tidak pernah ada".
Mereka tidak begitu kritis mempertanyakan spirit apa yang membuat Parhudamdam begitu gigih membela nation Batak, pun tidak melihat bahwa perjuangan Guru Patimpus yang bermarga Sembiring Pelawi, pendiri kota Medan itu sebagai bagian dari kodrat sense of community dari "sekelompok masyarakat di Sumatera Timur yang tak rela begitu saja tanahnya dijajah dan diperjual-belikan oleh yang tidak empunya hak" (kesultanan Deli) kepada Belanda. Posisi kritisisme mereka pun hampir menyerupai nyinyir karena mereka tidak menawarkan alternatif solusi nomenklatur yang lebih baik (atau setidaknya setara dalam kandungan nilai) dibandingkan nama Batak - yang sejauh ini mampu merangkul dengan baik common things di antara sub-sub etnis Batak (Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Mandailing, Angkola).
Beberapa penulis dari gerakan Karo Bukan Batak misalnya mencoba mengupas dokumentasi historis dari coretan-coretan sejarah para pengembara dan ilmuwan, dan membawa opinionasi yang seolah valid bahwa Batak itu benar-benar suku pedalaman, kanibal, kasar, pemakan babi, dan tak beradab (uncivilized); dan tidak lebih dari itu. Mereka tanpa sadar bahwa mereka sedang melakukan anachronistic treatment ketika di satu sisi mereka mengagumi masyarakat Melayu yang dianggap sebagai suku pesisir, melek budaya, dan beradab (civilized); tetapi di sisi lain melakukan glorifikasi terhadap common things Kebatakan seperti Dalihan Natolu di subetnis Toba yang amat mirip dengan Rakut Sitelu di subetnis Karo. Bahkan juga menegaskan anakronisme pola pikir itu ketika di tempat yang sama mereka menyitir Perret yang menyebut bahwa pada awalnya “Batak” dan “Melayu” itu tak terpisah.
Kendati demikian, sikap enggan mengakui diri sebagai orang Batak ini bisa dimaklumi karena harus diakui ekspansi orang Toba memang begitu dominan melakukan publikasi dan klaim seolah-olah Toba adalah Batak dan Batak hanyalah Toba, dan tidak lebih dari itu. Tak heran, sapaan "Horas" vs "Mejuah-juah" sendiri dijadikan peluru untuk menembakkan opini keberlainan sejarah itu. Ramainya isu itu sempat bergulir kembali ketika para netizen ramai-ramai mengomentari pernyataan dari aktor Tanta Ginting, beberapa waktu yang lalu.
Common Things Batak bukan Produk Penjajah
Penulis setuju dengan Daniel Perret ketika menyebut bahwa sejatinya Batak adalah "ciri kultural yang ditemukan (invented), didefinisikan, dibentuk, dan dirawat ", tetapi tidak jika dipanjangkan menjadi "ciri kultural yang ditemukan (invented), didefinisikan, dibentuk, dan dirawat oleh kaum kolonial". Pembaca boleh saja menilai sikap ini sebagai inkonsisten terhadap catatan Perret. Tetapi sebagai bagian dari generasi muda yang merasa perlunya meneriakkan keprihatinan terhadap keterpecahan dan ketercerabutan dari akar bersama - yaitu Kebatakan - yang menjiwai secara sangat mirip orang Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Mandailing, Angkola (sebagian bahkan meluaskannya ke sekolompok Gayo dan Alas di Aceh), tak selalu harus diterima bahwa sejarah dan perspektif yang fair hanya berasal dari penulis luar yang tidak benar mengerti "rasanya" menjadi orang Batak.
Perret, hemat penulis, tidak bisa merasakan cultural sense yang benar-benar mirip setiap kali berkat kemanusiaan dimohonkan oleh pihak boru kepada hula-hula atau anak beru kepada kalimbubu. Sebagai travel writer ia kemungkinan hanya melihat fenomen visual yang ada tanpa mempertanyakan nilai dasar apa yang membuat tata laku dari orang-orang dari sub-subetnis Batak itu bisa begitu dekat, sedekat keluarga-keluarga yang tinggal bersama di Rumah Manik Karo di Dokan dan Jabu (Ruma) Bolon di Samosir.
Parsadaan Munthe - contoh Preservasi Common Things Batak
Menjadi kebanggaan tersendiri, misalnya, ketika penulis menemukan bahwa Haromunthe adalah marga dari suatu kumpulan lintas subetnis Batak yakni Parsadaan Munthe. Kumpulan ini unik sebab komunikasi di dalamnya mesti toleran, inklusif dan beyond the religion borders.