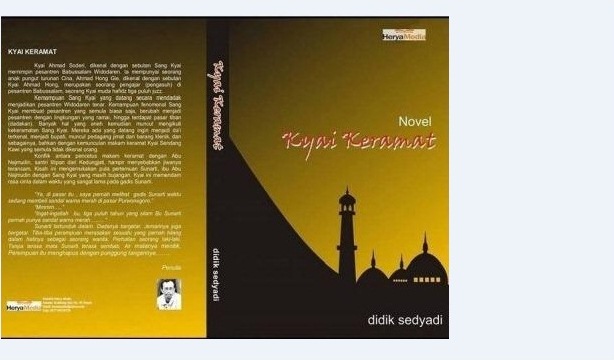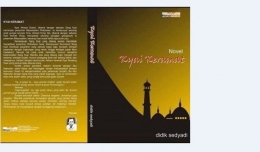RINTIHAN SEORANG MERBOT
Kegelisahan Sang Kyai semakin beralasan. Wajah lebam seorang laki-laki tua membuktikan bahwa telah terjadi sebuah kekerasan. Kejadian itu mungkin menjadi tidak terlalu berarti jika terjadi di tempat lain yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Misalnya di konser, di bar, di tempat-tempat hiburan, di pasar malam atau yang lain. Ini adalah pesantren. Widodaren bahkan baru saja menjadi tenar dengan turunnya karomah bagi pemimpinnya. Sosok yang mampu menjadi manfaat bagi banyak umat, baik yang beragama Islam maupun yang bukan.
Malam ini benar-benar Sang Kyai masygul. Ia tak percaya dengan matanya sendiri yang melihat wajah Wak Wardan lebam. Wajah tua itu tampak mengusik ketenangan Sang Kyai sebagai pimpinanpesantren. Sang Kyai ingat ketika beberapa waktu lalu pernah melihat maling yang dihakimi massa di tahanan polsek. Wajahnya hancur. Pelupuk matanya membesar menutupi bola mata yang tersembunyi. Kini keadaan seperti itu ada dalam wajah Wak Wardan, walaupun tidak sepenuhnya seperti yang dilihat di kantor polisi.
Pemimpin pesantren itu melihat laki-laki yang dipegang kedua tangannya oleh dua orang santri, persis seperti orang yang sedang mengarak pesakitan.
“Apa yang terjadi Kyai?! Kenapa dia jadi begini?” tanya Sang Kyai dengan nada tidak suka.
“Kami telah menuruti perintah Sang Kyai ….” jawab Kyai Haji Soleh Darajat hamper tidak kedengaran.
“Perintah yang mana? Saya tidak pernah memerintahkan warga pesantren untuk menyakiti orang!”
“Sang Kyai memerintahkan untuk menanyai Wak Wardan.”
“Lalu apa maksudnya orang ini dihajar?”
“Santri tidak tahan mendengar jawaban dia yang berbelit-belit.”
“Tapi apa perlu dihajar?”
“Dia yang menikam Udin!”
“Itu baru dugaan Kyai….”
Mendengar percakapan antara Sang Kyai dengan Kyai Haji Soleh Darajat Wak Wardan menghela nafas dalam. Ia melirik ke arah para pengasuh lain yang hadir. Beberapa dari mereka memandang dirinya dengan pandangan tajam.
“Wak Wardan ….. “ panggil Sang Kyai perlahan.
“Iya Sang Kyai.”
“Duduklah….. “
“Ya.”
Wak Wardan duduk. Laki-laki tua itu sama sekali tak menunjukkan wajah takut. Beberapa saat Sang Kyai memperhatikan wajah tua itu. Ada sebersit rasa iba melihat wajah yang mulai keriput itu lebam.
“Wak, maafkan kami. Maafkan santri kami ….”
“Buat apa memaafkan santri, toh dia tidak merasa bersalah.”
“Siapa yang tadi siang memukul Wak Wardan?” tanya Sang Kyai pada dua orang santri yang mengapit laki-laki tua itu.
“Saya Sang Kyai ….. “ kata salah satu santri. Sang Kyai memandang santri itu dengan tajam.
“Apapun alasannya kamu harus minta maaf.” kata Sang Kyai memberi perintah.
“Tapi dia telah menikam Udin Sang Kyai .”
“Benar Wak Wardan?” tanya Sang Kyai.
“Sang Kyai,dengar sendiri alasan dia. Dia tak merasa bersalah. Jadi memang dia disuruh minta maafpun tak akan mau.”
“Wak sendiri melakukan penikaman apa tidak?”
“Saya tidak tahu. Tergatung Sang Kyai , atau yang lain yang di sini ingin saya dianggap menikam santri atau tidak!”
“Waaakkk…. salah satu alasan yang dijadikan untuk mengatakan Wak yang melakukan penikaman adalah karena Wak pernah mengancam Kyai Ahmad Hong , Kyai Haji Soleh Darajat dan para santri dengan keris.”
“Oooo waktu malam-malam itu?”
“Ya benar.”
“Waktu Sang Kyai pergi”
“Ya.”
“Kenapa Wak?”
“Tak apa-apa… hanya rasa-rasanya ketika Sang Kyai mengajak aku untuk bergabung ke pesantren, saya melihat ada kesombongan yang ada dalam diri Sang Kyai …..”
“Waak? Saya tidak mengerti!” Kata Sang Kyai heran. Orang-orang yang hadirpun merasa kaget dengan pernyataan Wak wardan yang begitu berani.
“Mereka, Kyai Hong dan Kyai Soleh mengatakan akan mengajari saya. Saya yakin bahwa ini semua adalah ajaran Sang Kyai agar merasa menang terhadap orang lain. Sang Kyai mengangggap bahwa saya adalah orang yang bodoh!”
“Wak, Uwak ngomong apa?”
“Makanya benar… saya yakin bahwa Kyai Haji Soleh Darajat atau Kyai Ahmad Hong telah cerita ke Sang Kyai bahwa saya mengancam Sang Kyai ….”
“Wak mengancam saya?”
“Ya. Sang Kyai mau apa?”
“Wak Wardan membenci saya?” Tanya Sang Kyai semakin heran dengan kalimat-kalimat laki-laki tua itu.
“Saya sangat membenci Sang Kyai.”
“Atas kesalahan apa?”
“Kesalahan besar, yang mungkin teramat besar hingga menyebabkan sayamenjadi orang yang paling kecewa di Widodaren!”
“Kesalahan besar apa Wak?”
“Haha!”
“Katakan Waaaak!”
“Wardaaaan! Kamu gila ya!” kini yang tidak tahan dengan omongan laki-laki tua adalah Kyai Haji Soleh Darajat.
“Mungkin gila …… “ kata Wak Wardan tenang.
“Sang Kyai, omongan semacam inilah yang menyebabkan santri kita tak bisa menahan diri untuk menghajar orang ini.”Terang Kyai Haji Soleh Darajat seolah mencari legitimasi bahwa tadi pagi telah terjadi pemukulan terhadap Wak Wardan.
“Kalau aku punya sifat seperti kalian, mungkin sudah sejak dulu saya hajar kalian! Terutama kamu Sang Kyai!” Kata Wak wardan sambil bangkit dari duduknya seraya menunjuk muka Sang Kyai.
Des! Sebuah pukulan melayang ke wajah laki-laki itu.
Kyaiiiii!
Teriak Sang Kyai demi melihat tanpa diduga yang melayangkan pukulan adalah Kyai Haji Soleh Darajat , salah seorang pengasuh Widodaren.
Laki-laki tua itu terjerembab ke lantai. Rupanya Kyai Haji Soleh Darajat tak bisa menahan diri dengan perlakuan Wak Wardan pada Sang Kyai .
Perlahan laki-laki tua itu bangkit. Sang Kyai mendekat dengan cepat. Dipegangnya bahu Wak Wardan. Laki-laki itu belum bereaksi. Ketika wajah laki-laki menoleh, Sang Kyai kaget bukan kepalang karena dari hidung meneteskan darah.
“Wak….Uwak tidak apa-apa?”
“Tidak apa-apa …. inilah model sesungguhnya pesantren Widodaren.”
“Pak Kyai, kenapa lakukan ini?” Tanya Sang Kyai pada Kyai Haji Soleh Darajat dengan roman muka yang kemerahan menahan marah.
“Orang ini telah menghina Sang Kyai. Berarti ia juga telah menghina pesantren Widodaren.”
“Pak Kyai…. ada satu hal yang tidak boleh Pak Kyai lupakan. Tak ada asap jika tak ada api. Wak Wardan berbuat begitu padaku pasti ada sebabnya.”
“Maafkan saya, Sang Kyai”Kyai Haji Soleh Darajat baru menyadai bahwa pikirannya tidak sejauh Sang Kyai.
“Waaakk…..” kata Sang Kyai berganti kepada Wak Wardan yang hidungnya penuh darah.
“Puas kalian?!”
“Waakkk…. jangan berkata begitu!”
“Sakitku tidak seberapa dibandingkan dengan sakit hatiku Kyaiii….”
“Sakit hati?”
“Mungkin kalian bunuhpun itu lebih baik! Biar aku tak terlalu lama memendam rasa sakit karena dendam padamu Kyai kekasih Allah!”
“Dendam apa Wak?”
“Dendam apa? Hmh! Dendam apa katanya? Memang manusia itu punya sifat melupakan perbuatan jeleknya pada orang lain. Tidak peduli itu siapa, jalma rucah, orang pidak pedarakan, orang-orang terhormat, haji, termasuk orang golongan suci, ustadz, guru agama, kyai,atau siapa yang merasa dirinya suci.”
“Jangan kemana-mana kalau bicara Wak Wardan.”
“Siapa yang ke mana-mana? Saya hanya bicara apa adanya. Banyak manusia yang melupakan perbuatan jeleknya. Melupakan akibat. Melupakan kelakuan atau apa saya yang melukai hati orang lain.”
“Terus tertang saja Waaak, jangan berputar-putar!”
“Sama seperti da’i juga, kadang-kadang berputar-putar sebelum mengatakan yang sesungguhnya tentang perilaku umat. Apa salahnya saya lakukan ini?”
“Saya tidak mau berdebat Wak Wardan. Saya tahu, Wak lebih tua dari saya. Pengalaman hidup lebih mumpuni. Jadi kami punyai kesalahan itu wajar. Tapi tolong katakan pada saya Wak.”
“Tanyakan pada Allah-mu yang memberikan karomah itu!”
“Jangan bawa-bawa itu Wak Wardan…”
“Tanyakan mengapa hati Sang Kyai sampai menggumpal, beku, tidak dibukakan kesalahan sehingga paham bahwa perbuatannya telah menanam dendam!”
“Jadi Wak Wardan serius?”
“Jadi Sang Kyai menganggap saya tidak serius?
“Apakah aku pernah berbuat salah pada Wak? Apakah masalah kuburan kucing itu?”
“Hmh!”
“Kalau memang itu, kami minta maaf!”
“Kuburan kucing hanyalah sekuku hitam Sang Kyai ….. bukan itu…”
Laki-laki tua itu diam. Perlahan baju komprangnya yang lusuh itu digunakan untuk menyeka hidung. Darah tampak meresap di lengan baju. Tak berapa lama kemudian Wak Wardan menangis. Laki-laki itu duduk. Kemudian mukanya ditelungkupkan di meja. Melihat semua itu yang hadir tak habis pikir. Mereka saling berpandangan, serta saling bisik.
Hingga beberapa lama laki-laki penjaga kuburan itu menangis. Sang Kyai membiarkan laki-laki menumpahkan seluruh beban di hatinya. Adapun hati Sang Kyai menjadi sangat gelisah. Ia melihat bahwa Wak Wardan tidaklah sedang kacau pikirannya. Jika demikian maka benar bahwa laki-laki itu menaruh dendam pada dirinya. Sang Kyai sangat takut. Dia sangat takut karena selama ini tidak merasa berbuat salah pada orang lain.
Beberapa menit berlalu. Wak Wardan mulai diam. Isaknya tak terdengar lagi. Sang Kyai menyuruh santri untuk mengambil handuk dan air panas untuk menyeka hidung Wak wardan. Beberapa saat setelah santri yang disuruh berangkat dan kembali lagi, Sang Kyai mengangkat bahu Wak Wardan.
“Seka wajah Uwak…” pinta Sang Kyai sambil menyodorkan handuk kecil bersih dan air hangat dalam panci. Wak wardan menatap Sang Kyai sejenak. Setelah itu tangan Wak Wardan meraih handuk yang disodorkan Sang Kyai.
Sang Kyai menghela nafas, lega. Kini semuanya melihat pada Wak Wardan yang menyeka wajahnya dengan air hangat hingga bersih. Wajah yang semula belepotan darah kini berangsur bersih.
“Wak Wardan … maafkan saya… “ kata Sang Kyai.
“Ijinkan saya pergi Sang Kyai.” kta Wak Wardan sambil berdiri.
“Pergi?”
“Ya pergi.”
“Tidak. Uwak tak saya ijinkan pergi. Uwak tetap di sini!”
“Sang Kyai akan tetap menyekapku di sini?”
“Bukan begitu Wak. Uwak orang bebas.”
“Kalau begitu ijinkan saya pergi.”
“Tidak.”
“Lalu kenapa? Saya tak ada urusan lagi. Saya katakan sekali lagi bahwa saya tidak tahu menahu siapa yang menikam orang pesantren ini!”
“Bukti nyata Waaak….. “, tiba-tiba Kyai Haji Soleh Darajat menyela, “ ….Wak yang telah melakukan penikaman. Keris Uwaktidak ada di rumah karena memang keris itu menancap di punggung Udin.”
“Hei Pak Kyai Soleh ….. pikirkan nama soleh. Seumur-umur saya menjadi orang kecil, orang bodoh, orang yang berpendidikan…. tapi saya tak pernah memukul orang! Sejelek-jelek orang seperti saya, paling baru saya berbohong ….membohongi orang, seperti kuburan kucing itu.”
“Ya itu sama saja keburukan! Hanya beda bentuk!”
“Tapi ingat Pak Kyai Soleh, nama saya Wardan. Nama yang tidak ada artinya. Beda dengan dengan Pak Kyai, namanya bagus, Soleh, nama yang punya makna dalam. Saya walaupun hanya seorang Wardan, tapi selama hidup saya, saya tidak pernah memfitnah orang!”
“Siapa yang memfitnah orang! Tunjukkan mana keris Uwak yang di rumah kalau tidak digunakan menikam. Wak Wardan memang dendam pada kami!”
“Maaf Pak Kyai …., “ Sang Kyai menyela, “ …… untuk sementara urusan keris lupakan dulu.” Kata Sang Kyai mengingatkan.
“Maaf Sang Kyai.” kata Kyai Haji Soleh Darajat lemah.
“Wak, duduklah dulu. Kalau Wak pergi, maka masalah kita tidak selesai. Bukankah Uwak ingin agar orang yang bersalah pada Uwak tahu kalau perbuatannya yaitu menyakiti Uwak. Kalau misalnya saya tidak tahu, maka Wak yang rugi karena menyimpan dendam, tapi didendami itu tidak tahu. Bukankah Wak ingin membalas sakit hati terhadap orang itu.”
“Terhadap Sang Kyai.”
“Naaah itu maksudnya. Terhadap saya.”
“Ya.”
“Baiklah Wak, sekarang wak tenang dulu. Tolong Wak ceritakan mengapa Wak menanam rasa dendam pada saya. Beritahu saya. Jika sudah, bolehlah Wak lakukan apa saja sesuka Wak… kalau perlu bunuh saya, bunuh saja…. “
Wak Wardan diam. Semua diam. Hingga beberapa saat akhirnya laki-laki penjaga kuburan itu menata duduknya, kemudian membuka mulutnya.
“Sang Kyai ingat saat pesantren ini didirikan?”
“Oooo… ingat, ingat Wak. Tapi itu sudah lama sekali. Puluhan tahun lalu” Kata Sang Kyaiyang merasa senang diingatkan kembali tentang pendirian pesantren.
“Nah, selama itulah saya memendam dendam ini pada Sang Kyai .” Kata Wak Wardan dengan pandangan tajam.
“Hah? Me ...mengapaWak?”
“Sang Kyai masih ingat di tanah bekas apapesantren ini didirikan.”
“Ladang jagung.”
“Apalagi?”
“Dulu seingat saya ada surau kecil.”
“Di mana surau kecil itu?”
“Di sini. Di tanah almarhum Haji Salam.”
“Benar. Memang surau itu ada di tanah Haji Salam.”
“Betul itu.”
“Sang Kyai…. kemanakah surau kecil itu berada?”
“Dibongkar.”
“Mengapa dibongkar?”
“Karena Haji Salam almarhum telah mewakafkan tanah ini kepada saya, dengan amanat kelolalah menjadi sebuah pesantren. Saya sebagai orang yang diberi amanat yang baik, tentu saya laksanakan. Lagi pula kebetulan saya punya rekanyang dapat bantuan pula dari para donatur dari Arab, yang dipinjamkan. Maka jadilah pesantren ini berdiri.
“Mengapa Sang Kyai tidak minta ijin ke penjaga surau?”
“Penjaga surau?”
“Iya penjaga surau.”
“Setahu saya tak ada yang merawat.”
“Ya … pengetahuan Sang Kyai sempit karena Sang Kyai adalah orang pendatang.”
“Ya , saya memang pendatang.”
“Jadi tidak tahu ada penjaga surau itu?”
“Seingat saya tak ada yang merawat. Surau itu menurut pengamatan saya hanya menyediakan tempat bagi orang-orang yang singgah untuk mampir shalat. Tak ada siapa-siapa.”
“Sang Kyai tidak tahu bahwa sayalah yang telah bertahun-tahun merawat surau itu….. “ Kata Wak Wardan dengan mata yang memerah, kemudian mulai menitikkan air mata.
“Apa? Uwak yang merawat?”
“Iya.”
“Pada saat pembangunan, surau itu tak berpenghuni.”
“Dulu saya sedang ke kota sebentar.”
“Surau itu ditinggal?”
“Iya.”
“Kenapa?”
“Karena lapar Sang Kyai. Dua hari saya tidak makan. Waktu itu musim kemarau, tanaman di sekitar surau mati semua. Termasuk singkong, dan tales. Tak ada tumbuh. Tak ada yang bisa saya makan .”
“Dua hari?”
“Ya saya pergi untuk mencari uang, untuk mencari makan. Saya ikut proyek perbaikan jembatan.”
“Kenapa surau itu tidak dititipkan ke orang lain?”
“Tak ada yang mau merawat. Akhirnya saya tinggal. Saya tawakkal. Saya tinggalkan surau itu benar-benar karena setelah dua hari saya tidak makan, ada yang mengajak saya bekerja. Namun ketika saya kembali, surau itu tak ada ujudnya lagiii…….hhhh…… “ Wak Wardan tak kuasa menahan tangis. Sang Kyai termenung. Lubuk hatinya yang paling halus merasa tersentuh. Apalagi ada kata-kata bahwa telah dua hari penjaga surau itu tidak makan.
Setelah beberapa saat Wak Wardan reda tangisnya, Sang Kyai menepuk-nepuk pundak laki-laki. Laki-laki tua itu menatap tajam Sang Kyai , kemudian menggelengkan kepala.
“Aku tahu maksud Wak ….”
“Sang Kyai tak pernah tahu maksud saya.”
“Hari ini juga Wak Wardan saya angkat jadi merbot masjid An Najm. Karena Uwak tahu…. tepat di tengah-tengah pesantren inilah dulu surau itu berdiri. Berarti masjid An Najm adalah penerus surau yang dulu itu. Surau si Uwak.”
“Saya sakit hati Sang Kyai ….. sebab dengan hilangnya surau itu, maka pupuslah sudah harapan satu-satunya dalam hidup saya untuk mendapatkan amal jariyah.” Kata Wak Wardan belum mempedulikan tawaran Sang Kyai untuk menjadi merbot masjid pesantren.
“Wak…. jangan berkata begitu. Wak bisa lakukan itu bersama An Najm.”
“Dulu kusen pintu surau itu saya yang membuat. Saya gunakan tatah dan pasah serut sendiri. Saya paku sendiri, saya rakit sendiri. Setelahjadi dan terpasang, setiap ada orang yang mampir dan shalat melewati pintu itu, saya merasa bahwa Allah telah meneteskan titik demi titik kebaikan atas jariyah dengan dipakainya kusen pintu.”
“Wak, Allah Maha Pandai, Maha Mengetahui hati umatnya. Niat Uwak yang tulus pasti akan selalu dicatat sebagai kebaikan.”
“Itu yang saya inginkan.”
“Terus apa lagi yang kurang?”
“Tidak! Salah besar! Terlambat Sang Kyai….. “
“Terlambat apa?”
“Dulu saya sebagai merbot, merawat, nguri-uri, saya bisa melakukan apa saja, mengaji, tadarus. Namun sejak kejadian itu, kekecewaanku sangat tumus dalam hati. Melukai hati saya yang paling dalam. Hingga akhirnya aku benci terhadap surau, benci terhadap ngaji, benci terhadap Qur’an!”
“Waak, istighfar Waaak!”
“Sang Kyai yang seharusnya istighfar!”
“Astaghfirullaaahhhhal’adziiimmm”
“Sayabenci Islaaaaammm.”
“Waaak!”
“Benci terhadapmu Sang Kyaiiiiiiii!”
“Waaaaakkk!” Sang Kyai menjerit histeris.
“Benci terhadap An Najm, benci terhadap pesantren iniii….. atas kebesaran Allah pula yang kalian puja, seperti yang ditunjukkan kekuasaannya pada Sang Kyai untuk mahir mengobati orang sakit, akupun mendapat bagian yang sama dari Allah-mu itu. Hanya beda bentuk….”
“Berhenti Wak, berhenti, berhenti, saya mohon berhenti Waaakk!”
“Sang Kyai mendapat bagian karomah, aku dapat bagian mendapat kutukan!”
“Waaaaaaakkkk…..!”
“Karena kebencianku inilah yang menyebabkan saya lupa segalanya ….. karena kebencian ini saya lupa mengaji….saya…sayaaa….saaa…. saya tak ingat apa-apa lagi tentang huruf Arab. Tak ingat lagi bagaimana shalat itu ….. dan…. memang tak perlu itu semua ….. biarlah aku sendirian di jalanku yang ini …. yang tak mengenal Tuhan lagi……”
“Waaaaaakkkk……….”
Jerit Sang Kyai disusul dengan tubuhnya yang jatuh ke lantai. Kyai Haji Soleh Darajat yang berada di dekatnya kaget, namun terlambat. Tubuh Sang Kyai sudah jatuh di lantai dengan suara berdebum. Melihat itu semua Kyai Haji Soleh Darajat menoleh ke arah Wak Wardan. Namun kini ia tak berbuat apa-apa.
“Hanya satu yang masih lekat dalam ingatanku, doa orang teraniaya adalah makbul! Karomah Sang Kyai akan hilang dalam waktu tiga pekan ke depaaann... dengarkan itu Sang Kyai! Dengarkan semuanya!” Kata Wak Wardan sambil menunjuk-nunjuk Sang Kyai yang masih tergolek tak sadarkan diri.
Orang-orang ribut mengangkat Sang Kyai ke dalam. Wak wardan bergegas meninggalkan tempat itu. Beberapa santri yang ada disekitarnya bingung.
“Bagaimana Wak Wardan Pak Kyai.... “ tanya salah satu santri demi melihat Wak Wardan beranjak pergi. Kyai Haji Soleh Darajat berfikir sejenak.
“Biarkan dia pergi.” Katanya kemudian.
Para santripun membiarkan laki-laki itu pergi. Dengan langkah gontai Wak Wardan meninggalkan rumah utama, melewati balai. Beberapa saat ia berhenti depan masjid An Najm. Matanya melihat masjid megah itu dengan pandangan kuyu. Yang dalam pikirannya adalah sebuah surau kecil, kotor, menjadi persinggahan orang-orang yang pulang dari sawah, kusen pintu dari kayu nangka buatannya. Tapi semua itu tiada lagi. Semua telah terkubur. Sebuah kemegahan masjid yang berdiri di atas bekas sebuah surau kecil tak bernama.
Sepeninggal Wak Wardan , Sang Kyai masih tergeletak.***
Keterangan kata Bahasa Jawa :
1.ngarit = menyabit / mencari rumput
2.jalma rucah, orang pidak pedarakan = orang kecil , kasta terendah
3.tumus = mendalam
Bersambung ke Seri 20
Insya Allah Selasa mendatang ............................
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H