Adanya penelitian dari organisasi pendidikan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2016, yang mendaulat Indonesia berada di posisi 60 dengan label Negara yang tergolong memiliki minat dan kebiasaan membaca sangat rendah membuat pemerintah, industri penerbitan, penulis, dan segenap masyarakat seakan memiliki tanggung jawab moral untuk bergerak bersama-sama demi cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam perjalanannya, kita dapat melihat penerbit yang berlomba-lomba menerbitkan buku terbaik, penulis yang mulai menggoreskan karya-karya menarik minat khalayak, masyarakat yang peduli pun turut membangun taman baca serta pemerintah yang mulai menggalakkan ketersediaan akses yang mampu mengakomodasi minat baca masyarakat, terutama akses baca bagi masyarakat di daerah terpencil.
Setali dengan itu, bernada tak diundang, muncul-lah oknum-oknum pembajak buku yang alih-alih peduli dengan rendah literasi, dengan menjual buku-buku yang menjadi bestseller dengan harga dibawah pasaran, alias menjual buku bajakan.
Kehadirannya, satu sisi muncul sebagai pahlawan (karena buku dagangannya terbukti laku dengan harga yang miring).
Di sisi lain, ada penulis yang bersedih karena keuntungan penjualan yang harusnya menjadi pundi-pundi pendapatan malah tak dapat, ada editor yang sedang pusing karena hal yang menjadi haknya ikutan dikebiri, ada penerbit yang rasanya salah pilih bisnis karena menganggap memilih bisnis yang salah ditengah masyarakat yang rendah tingkat literasi, serta ada toko buku yang sekiranya bertarung habis-habisan agar tak medapatkan label "senjakala."
Anehnya, melihat fenomena seperti ini, pemerintah cenderung tak melakukan upaya yang berarti dan menganggap perkara pembajakan hanya problema remeh-temeh semata. Seakan para pelaku mendapat lampu hijau untuk mengembang bisnis ilegalnya, tak membayar pajak, dan tak memberikan royalti pada penulis (karena seratus persen keuntungan masuk ke kantong pembajak).
Namun pemerintah agaknya segera bergerak cepat, kala ada penerbit yang bukunya sedikit beraroma kiri (walau hanya dari synopsis) laris manis di pasaran, dan seketika langsung tancap gas, untuk sejenak menyita, mengamankan, dan memberi larangan terbit.
Berdasarkan hal di atas, kesimpulan yang dapat ditarik, bisa saja karena masalah hak cipta tak pernah menjadi prioritas di negara berkembang ini. Sungguh aneh bukan?
Padahal dalam Pasal 1 ayat 23 UU 28/2014 saja, sudah jelas-jelas mengungkap definisi pembajakan adalah "Penggandaan ciptaan secara tak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi."
Bahkan, pelakunya diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda Rp 4 miliar, sesuai Pasal 112, 113 ayat 3, dan Pasal 114 UU Nomor 28 Tahun 2014.
Meski begitu, kurang tegasnya pemerintah dalam hal ini, membuat peraturan yang ada, hanya mirip-mirip seperti buku petunjuk pemakaian pada pembelian barang elektronik. Ada tapi sering kali luput untuk dibaca.
Efeknya, mereka dengan terang-terangan menjajakan buku bajakan di kaki lima, pasar, bahkan turut meramaikan marketplace, yang justru banyak berlabel karya anak bangsa.
Lalu sikap masyarakat? Rasanya mantra "bodo amat" masih mendominasi. Selama murah, selama terjangkau, & selama birahi membaca masih dapat tersalurkan.
Oleh karenanya, agak kurang relevan kala masyarakat kita disuguhi matra untuk "bodo amat" seperti yang terdapat dalam buku yang belakangan nge-hits karya Mark Manson (penulis buku: Sebuah Seni Untuk Bersikap bodo Amat).
Kenapa? Karena masyarakat kita sudah jauh-jauh hari mengadopsi hal tersebut. Buktinya, sampai sekarang ini hal-hal seperti tak menghargai karya orang lain, merebut karya orang, atau memperkaya diri lewat lewat lajur menari-nari di atas penderitaan banyak pihak (penulis, penerbit, editor, layouter, dan segala macamnya), bukanlah sebuah masalah yang butuh untuk disuarakan bersama-sama.
Melihat fenomena ini, diri pribadi memliki anggapan, sepertinya para pembajak telah salah mengartikan mantra dari Bung Karno, ketika Zaman pendudukan Jepang, dengan bersuara lantang "Amerika kita setrika, inggris kita linggis."
Mereka, para pembajak ini, justru malah mensetrika karya orang lain, dan melinggis penerbit-penerbit buku yang telah banyak berkeringat memajukan tingkat literasi dari bangsa Indonesia. Apa kita akan diam saja? I don't think so.
Perlawanan (Pribadi) Terhadap Pembajakan Buku
Hidup di dalam keluarga yang sedikitnya mengamini ucapan Tan Malaka "Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi." membuat diri pribadi menjadi sedemikian paham nikmatnya memiliki buku yang original (apalagi sampai ada tanda tangan langsung oleh penulisnya).
Rasa bangganya dapat dikatakan melebihi saat-saat memiliki smartphone dengan tiga kamera belakang atau mengoleksi sepatu anyar karya Rapper terkenal.
Meski begitu, dahulu, sebelum bisa menghasilkan pendapatan dari kantong pribadi, uang jajan lah yang ditabung untuk membeli sebuah buku. Kala nabungnya rajin, bisa jadi satu buku terbeli dalam waktu satu bulan, atau kalau tak rajin bisa sampai dua-tiga bulan lamanya untuk satu buku saja.
Kalaupun, belum mampu membeli, maka diri pun melangkahkan kaki ke perpustakaan daerah, ataupun rumah salah seorang teman guna membaca buku koleksinya.
Padahal, saat itu bisa saja membeli buku bajakan dengan harga dibawah standart. Namun, diri pun tetap pada pendirian, tak tergoda sedikit pun.
Walau saat itu penolakan membeli buku bajakan hanya berkutat pada alasan sederhana seperti perkara kualitas, perkara kenikmatan, serta perkara kenyamanan. Kepedulian pun, rasanya telah berkembang seiring waktu.
Moment kepedulian terhadap maraknya buku bajakan, ialah saat diri pribadi mulai menyukai aktivitas menulis dan ada salah satu karya yang ambil oleh pihak lain tanpa izin.
Saat itulah diri merasakan bagaimana geramnya para penerbit & penulis yang berkeringat menghasilkan buku populer, kemudian karyanya dibajak oleh orang lain.
Ironinya, disaat buku dapat menganugrahkan hidup manusia kepada ilmu pengetahuan dan kemakmuran. Disaat itu pula sang empu buku, yang meriset karya, melakukan studi langsung, maupun susah payah memikirkan cerita diambil haknya. Sungguh tidak adil, bukan?
Sebuah Harapan
Seiring dengan dipermudahnya oleh teknologi, kini, membeli buku tak harus melangkah jauh sembari berpanas-panasan menuju toko buku. Tinggal buka website atau aplikasi penerbit, cari buku yang diinginkan, masukkan keranjang, pilih metode pembayaran. Dan terakhir, buku pun siap dikirim, sehingga empunya pesanan cukup menunggu dengan tenang di rumah.
Itulah kemudahan yang diri pribadi rasakan akhir-akhir ini. Pembelanjaan terakhir diri pribadi, kalau tak salah ingat ialah membeli dua buku (Animal Farm & 1984) karya dari Geogre Orwell via Website dari penerbit Mizan (mizanstore.com).

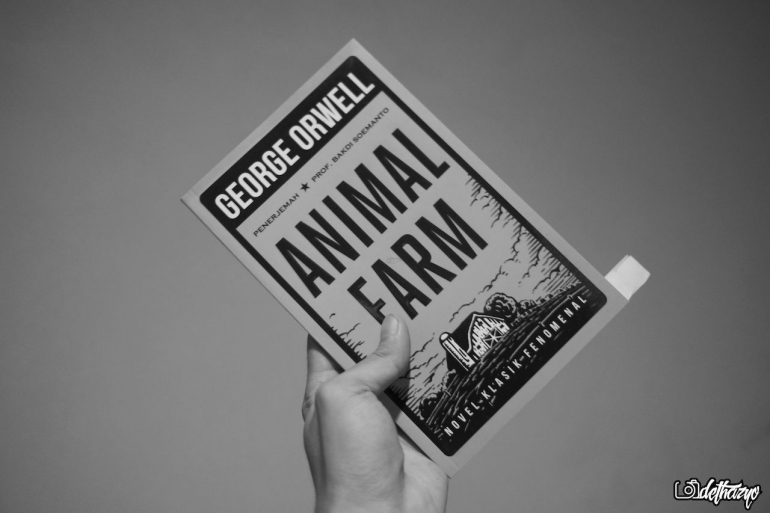
Jangankan generasi sekarang, generasi dahulu saja begitu cekatan ber-ide ketika merasa ada yang mengambil keuntungan dari buih-buih keringat rakyat, seperti yang dicerita oleh Alfred Russel Wallace dalam bukunya "kepulauan Nusantara," terkait Raja Sasak (Lombok) yang geram ketika dicurangi oleh bawahannya terkait upeti yang diterima.
Sang naturalis tersebut menulis "Raja juga melihat keris para membesar dan para pengawal semakin bagus dari tahun ke tahun. Gagang keris yang semula terbuat dari kayu kuning telah berganti gading, sedang gading berganti menjadi emas dan bahkan banyak pula yang berhiaskan intan. Melihat semua hal tersebut, raja menjadi tahu ke mana upeti tersebut hilang."
Reaksi sang Raja, ya awalnya tetap diam, karena belum bisa membuktikan asumsinya. Oleh karenanya, ia berpikir dan berpikir sampai suatu ketika dirinya dihinggapi sebuah ide untuk berpergian ke puncak gunung guna menemui roh agung sendirian saja.
Sepulangnya, ia mengumpulkan seluruh pendeta, pangeran, dan orang terkemuka di Mataram untuk mendengarkan pesan yang (seakan-akan) disampaikan oleh roh agung kepada sang Raja. Berikut pesannya:
"O.. Raja! Banyak wabah penyakit dan bencana akan melanda bumi, melanda manusia, melanda kuda dan melanda ternak. Akan tetapi, karena kau dan rakyatmu mematuhi ku serta telah datang mendaki gunung ku yang agung, aku akan memberi tahukan cara menghindarkan diri dari malapetaka."
Setelah memberikan pengantar, raja pun melanjutkan prihal cara menghindar dari malapetaka, dengan cara membuat 12 keris keramat (yang mendakan 12 wilayah kekuasaan) dengan tiap keris terbuat dari jarum yang jumlahnya mewakili jumlah penduduk di tiap wilayah (satu jarum mewakili satu penduduk).
Bersamaan dengan itu, berita pun kemudian tersebar ke seluruh wilayah, hingga kemudian total jarum (penduduk) telah dikumpulkan.
Strateginya pun berjalan lancar, bila upeti kurang sedikit dari jumlah seharusnya, raja akan memaklumi, tetapi kala kekurangan tersebut mencapai setengah atau seperempat dari jumlah yang seharusnya, maka siap-siap hukuman mati menjadi taruhannya.
Dari cerita di atas, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa solusi akan banyak bermunculan jika kita serius memerangi hal-hal yang berbau pembajakan.
Strategi di atas pun jika digunakan masih relevan, cuman harus di amati, tiru dan modifikasi agar sesuai dengan selera zaman.
Semisal, mulai dari memetakan oknum-oknum penjual buku (bajakan) yang dipermanis dengan istilah non-original di ragam marketplace untuk dipersempit ruang geraknya.
Atau, bila perlu, (kalau memang diperlukan), pemerintah mulainya menggalakkan fokus pada pembangunan manusia, dalam hal ini, seperti menghilangkan pajak buku agar terjangkau oleh seluruh rakyat (seperti langkah turki).
Sebelum menutup. Diri pribadi cuma ingin mengingatkan kembali pesan dari Ki Hajar Dewantara, kepada kita semua, termasuk teruntuk para pembajak buku yang budiman:
Luwih becik mikul dhawet rengeng-rengeng, tinimbang numpak mobil mrebesmili utawa nangis nggriyeng. (Lebih baik hidup sebagai tukang cendol, namun bahagia, daripada kaya tetapi menderita). Salam,...
Referensi Buku:
Kepulauan Nusantara | Alfred Russel Wallace

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H









