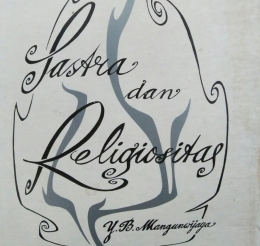Di sini muncul pertanyaan: Apakah arti agama bila tidak mampu berperikemanusiaan? Dengan kata lain: Apa arti agama tanpa religiositas? Apa artinya agama tanpa ''penuntunan manusia ke arah segala makna yang baik". Apakah artinya jika lebih mementingkan huruf daripada roh, lebih mendahulukan tafsiran harfiah di atas cinta kasih?
Sastra dan Religiositas
Dalam membahas tentang Religiositas Langsung, Romo Mangun mengutip sebuah cerpen dari Kuntowijoyo yang berjudul "Sepotong Kayu untuk Tuhan". Dikisahkan.... Seorang lelaki tua ingin menyumbangkan kayu nangka (kayu bangunan yang paling mulia bagi orang Jawa) dari kebunnya untuk pembangunan sebuah surau di desanya. Tetapi ia ingin merahasiakan sumbangannya itu secara total, sebab ''hanya Tuhan jugalah yang diinginkannya".
Dengan bersusah payah dan melalui liku-liku, berhasilah ia dalam kegelapan malam (saat paling keramat bagi orang mistik) menghanyutkan segelondong kayu sumbangannya itu di sungai, sampai berhenti di tempat yang sangat dekat dengan surau.
Pagi harinya sedini mungkin, inginlah kayu itu ia letakkan di muka surau. Agar orang-orang, seperti mengalami mukjizat, akan bertanya heran, dari mana kayu nangka sebesar itu datang. Tetapi pada pagi harinya, setelah ditiliknya, ternyata balok berharga itu sudah hilang, dibawa banjir malam-malam rupanya. "Sesuatu telah hilang. Tidak, tak ada yang hilang," kata lelaki tua itu ... tersenyum. "Sampai kepada-Mu-kah Tuhan?".
Dari cerpen itu, Romo Mangun memberikan tanggapan;
Setiap mistikus atau sufi akan sampai pada titik yang dialami lelaki tua itu, pada awalnya ingin berbakti kepada Tuhan melalui sesuatu institusi yang tampak, yang jelas merupakan lambang agama. Tetapi balok itu dihanyutkan banjir, artinya oleh Yang Sejati, di luar dugaan manusia. Sumbangan si kakek sudah sempurna. Tak perlu orang tahu, siapa yang menyumbang gelondong kayu nangka itu.
Maka pertanyaan religius yang terungkap dalam sastra seperti cerpen ''Sepotong Kayu untuk Tuhan" di atas memang mengandung tanya:
Sanggupkah agama (apa pun) mengakui, bahwa ia bukan Tuhan, tetapi hanya penolong saja, agar si Manusia sendirilah, dengan bakat-bakat dan kekurangannya, dengan keyakinannya yang eksistensial, berusaha bertanggung jawab sendiri menuju ke kedewasaannya, sehingga manusia konkret mendapat kesempatan yang cukup lapang untuk mencari sendiri dan menemukan sendiri Rahmat yang khas personal ditawarkan kepada seseorang yang tergolong orang serius?
Namun dari pihak lain, realisme kita harus mengakui juga, bahwa Rahmat Allah hanya mungkin dan subur ditemukan oleh seseorang, juga yang paling individualis sekalipun, apabila diiringi dan ditolong kawan-kawan lain dalam dialog sosial yang sehat.
Untuk menutup resume ini, saya kembali mengutip pertanyaan reflektif romo Mangun:
Apa yang telah dan masih dapat disumbangkan oleh para sastrawan dalam persoalan eksistensial, yang menyangkut seluruh penduduk bumi kita yang semakin kecil, namun juga semakin padat dan semakin gelisah ini?