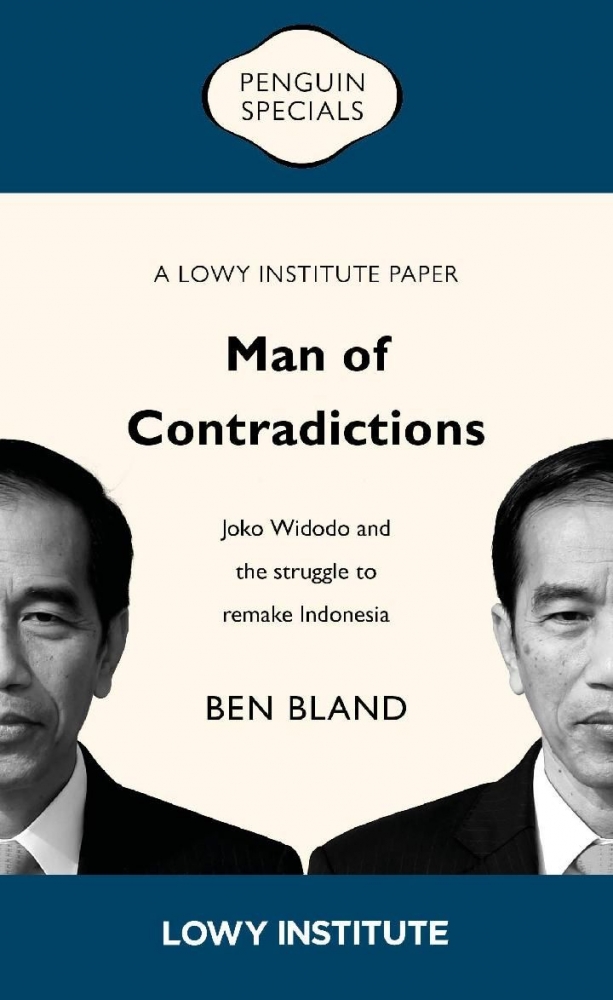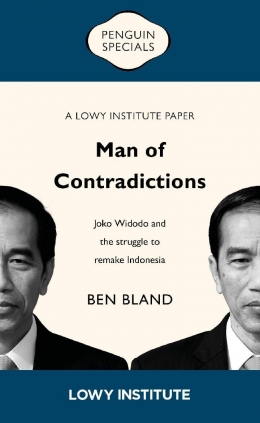Blend bertutur sarkasme dan tajam saat Jokowi hendak maju menjadi calon presiden pada 2014. Jokowi harus 'berdansa' dengan Megawati Soekarno Putri dan para pendukung setia. Jokowi berhasil merayu Megawati dengan menunjukkan rasa hormat yang diperlukan, seperti membukakan pintu untuknya, memindahkan kursi, dan bahkan mencium tangannya di depan umum. Tulis Blend.
Sebelum memahami kepresidenan Jokowi, kita harus memahami saat ini terdapat sembilan partai dalam 575 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak ada perpecahan sayap kiri versus sayap kanan, seperti yang kita lihat di banyak negara demokrasi.
Semua partai memiliki pandangan yang sama tentang ekonomi, dan cenderung proteksionisme. Dalam hal pemerintahan, partai cenderung membentuk koalisi 'pelangi' besar yang dirancang untuk membagi-bagi jabatan, daripada membuat platform kebijakan bersama. Proses ini disebut 'kartelisasi partai, gaya Indonesia' (hlm. 38).
Jokowi mengambil pendekatan serupa dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono, perlahan-lahan membangun koalisi tenda besar yang dirancang untuk membagi patronase dan meminimalkan oposisi, daripada membuat pemerintah lebih efektif.
Terlihat jelas kompromi dengan Megawati melemahkan potensi keontetikan tim menteri Jokowi, yang membuatnya tidak dapat melakukan reformasi atau menegakkan janjinya untuk memerangi korupsi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.
Satu badan riset menyimpulkan bahwa, setelah tahun pertamanya di istana, Jokowi adalah 'presiden lemah yang terjebak antara reformasi dan politik oligarki'. Demikanlah, politik Indonesia adalah tentang merayu orang dengan keuntungan, bukan ide dan ideologi,' kata salah satu menteri Jokowi kepada Ben.
Jokowi selalu pragmatis daripada idealis. Dia adalah pemimpin yang didorong oleh tindakan, bukan ide. Tanpa visi yang jelas tentang bagaimana ingin mengubah ekonomi.
Membuat beberapa kemajuan dalam merampingkan peraturan bisnis, tetapi pembicaraannya yang tak ada habisnya tentang reformasi menyembunyikan kontradiksi yang jauh lebih dalam antara keinginannya untuk investasi asing dan naluri proteksionisnya.
Jokowi telah berjuang untuk mengatasi kontradiksi fundamental yang telah menahan Indonesia sejak kemerdekaan: negara membutuhkan investasi asing dan pengetahuan untuk berkembang, tetapi liberalisme ekonomi dipandang sebagai alat penindasan kolonial.
Fokus Jokowi pada infrastruktur, contohnya, tidak didorong oleh komitmen ideologis terhadap ekonomi pasar bebas. Dia acuh tak acuh pada teori ekonomi seperti halnya teori politik. Sebaliknya, dia adalah seorang developmentalis seperti Soeharto, yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mempertahankan legitimasi politik.
Dan Jokowi menjalankan istana lebih sebagai pengadilan kekaisaran daripada kantor kepala eksekutif, membuat para menteri dan penasihat menebak-nebak niatnya dan, tidak jarang, mengambil keputusan besar dengan seenaknya.