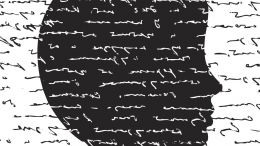“Kejujuran itu seperti cermin. Sekali dia retak, pecah, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Jangan coba-coba bermain dengan cermin.”– Tere Liye –
Hari itu, lima belas tahun yang lalu. Aku memperoleh sesuatu yang unik dari anak keempat kami. Usianya masih sembilan tahun, duduk di bangku kelas III SD. Namun, ia sudah memberiku pelajaran berharga tentang bagaimana cara mengapresiasi sebuah karya dengan jujur. Saat itu, usai pulang sekolah, Adiratna menunjukkan kertas hasil ulangannya kepadaku. Ulangan harian mata pelajaran bahasa Indonesia.
Awalnya, kulihat nilai ulangan harian anakku itu. Tampak angka 60 di sudut kiri atas kertas ulangan hariannya. Selanjutnya, aku mulai mencermati satu persatu soal yang terdapat di dalam kertas tersebut. Rumusan soal yang pendek-pendek dan tak ditemukan ilustrasi soal sedikit pun sebagai konteks.
Dari sepuluh soal, enam jawaban anakku dinilai benar, empat soal lainnya dinilai salah. Dari empat soal tersebut, ada satu soal berikut jawabannya yang menarik perhatianku, yaitu soal nomor 7 yang berisi, “Bangun tidur kuterus ….”. Soal ini dijawab oleh anakku dengan kata-kata, "minum kopi.”
Keesokan paginya, saat anakku sarapan dan hendak berangkat menuju ke sekolah, aku bertanya kepadanya, “Nak, kenapa soal nomor tujuh ini kamu jawab 'minum kopi'?"
“Setiap bangun tidur, aku kan ikut Ayah minum kopi!" jawabnya lugu.
“Kamu sudah bilang kepada Bu Guru?”
“Sudah, Yah. Kata bu guru dan teman-temanku, jawaban yang benar itu 'mandi'."
Aku bergeming. Ada kejujuran yang teretakkan oleh “kekuasaan” seorang pemimpin, dalam hal ini adalah sang guru. Soal yang diberikan kepada anakku dan teman-temanya sekelas itu sesungguhnya tidak berkonteks karena tak didukung dengan ilustrasi.
Batinku ….
Aku berikhtiar, mencoba memahami jalan pikiran sang guru ketika membuat dan memberikan soal tersebut kepada murid-muridnya, termasuk kepada anakku. Soal “Bangun tidur kuterus ….” yang disajikan tanpa didukung ilustrasi sesungguhnya mengundang jawaban yang beragam.