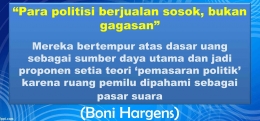Suasana ganjil menyergap, kala pertama menepi di ruang paling sepi. Bisik angin pada dedaunan. Gendang dalam kepala menyerap nada hampa tanpa suara.
Ambisi menggebu-gebu mengantarkannya ke dataran panas penuh bangunan yang pucuknya menggapai langit. Jalanannya pun bukan dari batu-batu atau tanah dipadatkan, tetapi hamparan mulus berwarna hitam.
Hiruk-pikuk. Raungan mesin. Mobil-mobil berlomba dengan auman sekumpulan sepeda motor. Melesat melepaskan asap menyisakan serapah. Klakson-klakson menjerit, menyingkirkan penyeberang jalan lamban yang bertumpu pada tongkat.
Di depan sebuah bangunan menjulang ia berhenti. Memastikan bahwa huruf-huruf tercetak di kertas telah sesuai dengan aksara raksasa pada jidat gedung megah itu.
Sebuah ruang kaku mengalirkan dingin pada lantai tertinggi gedung;
"Hey sobat, berharap ada kabar kemajuan di kampung halaman kita," sosok tambun berbungkus Hugo Boss mengulurkan tangannya.
"Ya ... segalanya masih berlangsung statis. Matahari tampak jenuh, bangkit setiap hari dari timur menuju horizon barat."
Berbeda dengan kota besar, matahari kembar berpendar 24 jam. Siang menyiram cahaya alami. Sinar artifisial memoles malam dengan segala kepalsuannya.
Pria tambun memandang tajam pria kurus di hadapannya, "berarti, di sana engkau tidak menghasilkan apa-apa?"
"Ya, kecuali keringat yang tak sempat mengering."