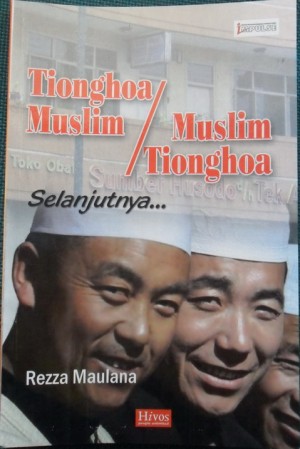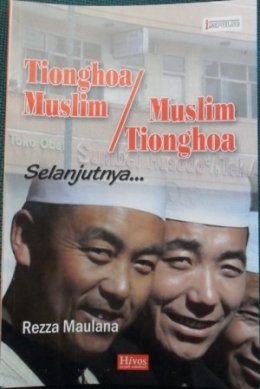Judul Buku: Tionghoa Muslim/Muslim Tionghoa Penulis: Rezza Maulana Penerbit: IMPULSE, Yogyakarta Cetakan: Pertama, 2010 Isi: 164 halaman ISSBN: 978-602-97679-2-6 ‘Tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri China”. Begitulah suatu ketika Muhammad SAW bersabda. Selain menandakan anjuran keras sang nabi tentang kewajiban menuntut ilmu, sabda itu juga dapat disimpulkan sebagai suatu pandangan dan keluasan wawasan sang nabi dan masyarakat Arab kala itu tentang sebuah negeri yang disebut China. Tidak mungkin kata “China” dikenal di negeri berpadang pasir itu kalau sebagai masyarakat, mereka tak pernah berinteraksi dengan entitas kesuku-bangsaan China. Apalagi, China adalah salahsatu peradaban manusia tertua di dunia. Di Indonesia, jejak-jejak China tak bisa dicueki sambil lalu. Secara historis, mereka telah berlalulalang di negeri kepulauan ini jauh sebelum zaman pencerahan di Barat. Cukup banyak cerita-cerita terkait yang menyebutkannya. Dalam Tutur Tinular, misalnya, ada kisah tentang orang China yang menjadi sorotan utama, yaitu Mei Sin (entah bagaimana ejaan China-nya). Konon, ia adalah kekasih sang jagoan di dalam cerita itu, Kamandanu. Juga ada tokoh bernama Pendekar Low, yang pada awalnya merupakan pemilik pedang Naga Puspa. Selain itu, jejak-jejak kebudayaan China juga cukup banyak bertebaran di sini. Mulai dari bahasa, arsitektur, konsepsi spiritual dan keduniaan, nama-nama jalan, hingga aneka kudapan. Di Yogyakarta, ada kue yang kesohor disebut Bakpia. Hampir tak sewisatawan pun yang datang ke kota Gudeg ini yang lupa untuk menyertakan Bakpia sebagai oleh-oleh wajibnya. Menurut Rezza Maulana dalam buku ini, kue tersebut pertama kali dirintis oleh oleh seorang China bernama Goei Gee Oe yang saat itu tinggal di kawasan Patuk, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta. Wajarlah kemudian ada kata “Patuk” di belakang nama Bakpia, yang menunjukkan keasalan daerah kelahiran kue itu. Namun, kekayaan jejak-jejak China itu tak berbanding lurus dengan perlakuan yang diterima oleh orang China. Mereka kerap dianggap sebagai warga-negara kelas dua. Padahal warga negara asing lainnya, seperti Arab, Eropa, India, tak sebegitunya diperlakukan. Belum lagi bila masalah kebijakan politik penguasa disoal. Di masa Orde Lama, ada kebijakan terhadap orang asing demi menanggapi suasana perang dingin. Maka lahirlah kebijakan Sistem Benteng dan PP No. 10 Tahun 1959 yang berbuntut pada pengusiran orang China dari daerah di bawah tingkat II. Bahkan ada yang diekstradisi ke China (hal. 25). Dalam bidang sosial-budaya saat itu juga ada kebijakan pencabutan subsidi dan pengawasan ketat terhadap sekolah-sekolah berbahasa pengantar China (Mandarin). Lain lagi yang terjadi pada masa Orde Baru pasca tahun 1965. Orang China dibonsai di lapangan politik. Meskipun kelak kebijakan itu membawa berkah tersendiri dalam lalulintas bisnis mereka, akan tetapi mereka masih tetap disinisi sebagai konglomerat pencuri kekayaan ekonomi Indonesia. Memang di masa itu ada kebijakan asimilatif, namun ia lebih nampak sebagai lelaku struktural untuk mengusir orang China dari semesta kebudayaannya. Lalu bagaimana dengan realitas adanya orang China yang masuk Islam dan kemudian disebut China-Muslim? Ini permasalahan yang cukup pelik lagi. Tapi jejak-jejak untuk itu juga cukup banyak. Publik Indonesia tentu tak asing lagi dengan seorang pemuhibah nusantara di zaman Majapahit, Laksamana Muhammad Cheng Ho. Di masa kini, barangkali kita semua pernah mendengar nama-nama masyhur seperti H. Syafii Antonio, H. Junus Jahja, H. Abdul Karim Oie, H. Yap A Siong, H. Masagung, H. Faishal Thung, serta masih banyak lagi yang umumnya berhimpun dalam wadah PITI (Pembina Iman Tauhid Indonesia atau Persatuan Islam China Indonesia). Bahkan, menurut Sumanto Alqurthuby, dalam bukunya Arus China-Islam-Jawa: Arus Cina-Islam-Jawa; Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa Dalam Penyebaran Agama Islam Di Nusantara Abad XV & XVI (2003), para wali songo penyebar Islam di tanah Jawa juga adalah orang-orang berdarah China. Perkelindanan kultural Nah, buku ini, mencoba untuk hadir meramaikan wacana tentangnya. Ia tidak mengambil jepretan historis, meski hal itu sedikit banyak dibicarakan di sini. Namun lebih mengarah pada penggambaran bagaimana orang China-Muslim hidup sebagai warga negara Indonesia. Di satu sisi, mereka adalah orang China yang tentu memiliki kekayaan kultural sendiri. Di sisi lain, mereka hidup di Indonesia, di tengah keragaman kultural yang tak perlu lagi dipertanyakan. Hal itu mendorong mereka untuk membingkai kechinaannya dengan keindonesiaan. Sebab bagaimanapun mereka hidup di ranah kultural yang bukan China. Jangan lupakan, bahwa mereka juga terbebani oleh muatan kultural “Islam/muslim”. Karena itu perbincangan menjadi lebih menarik tatkala Rezza melukiskan kejadian bagaimana mereka mengindonesia dan berindonesia. “Mengindonesia” dan “berindonesia” di sini perlu dikasih tanda kutip. Kedua diksi itu mengindikasikan adanya proses berkebudayaan dan perkebudayaanan. Yang pertama mencerminkan adanya proses tarik-menarik kultural antara kechinaan-kemusliman-keindonesiaan yang turut menentukan “diri-kultural” orang-orang China-Muslim-Indonesia itu. Yang kedua merujuk pada bagaimana proses tarik-menarik itu mengambil bentuk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ada tiga poros pembicaraan yang hendak disasar oleh buku ini. Orang China sebagai China. Orang China sebagai orang Indonesia. Lalu orang China sebagai seorang muslim. Tentu perkelindanan tiga aspek ini menjadikan mereka sebagai sosok manusia pemanggul identitas kemanusiaan yang khas. China-Muslim-Indonesia. Ditambah lagi, Rezza memotret perkelindanan tri identitas itu dalam konteks kehidupan di Yogyakarta. Rezza menemukan bahwa orang China-Muslim di Yogyakarta hidup berbaur dan masuk ke dalam sistem-kemasyarakatan. Mereka tak menampakkan gejala pengelompokan seperti lazimnya orang China di Malaysia dan di berbagai belahan dunia lain yang cenderung membentuk perkampungan khusus. Maka bukan keanehan bila di beberapa negara itu kerap ada kota lengkap dengan struktur birokrasi yang independen bernama: China Town. Dalam tataran ritual kultural-kegamaan, di Yogyakarta, pada tahun 2005 kaum China-Muslim pernah mengadakan acara peringatan tahun baru Imlek 2556 sehari setelah mereka merayakan Tahun Baru 1426 Hijriyah. Tradisi itu telah mereka rintis sejak tahun 2003 yang saat itu peryaan Tahun Baru Imlek diadakan di Masjid Syuhada Yogyakarta. Sedangkan pada tahun 2008, perayaan Imlek diadakan di Masjid Al-Husna Iromejan Gondokusuman. Di akhir acara biasanya mereka memberikan santunan berwujud amplop merah (angpao) kepada anak-anak yatim. Bila dicermati lebih jauh, tradisi ini merupakan bentuk analogis dari ragam unsur-unsur kebudayaan lokal yang akrab di hadapan kita. Apa yang mereka lakukan tak ubahnya orang Jawa yang merayakan tahun baru 1 Suro yang sekaligus tahun baru 1 Muharram. Selain itu, dilihat dari realitas kemasyarakatan yang mereka jalani, banyak di antara kaum China-Muslim yang menjalani hidup sebagai pedagang di pasar, guru, tabib, anggota DPRD, bahkan tak sedikit pula yang menjadi ustadz/kyai. Di tingkat nasional, publik Indonesia mungkin sudah mengenal nama-nama seperti Anton Medan, Yusuf al-Islamy serta masih banyak lagi orang China-Muslim yang menekuni jalan hidup sebagai muballigh atau mujahid dakwah. Pengalaman unik mereka sebagai seorang “kafir” tentu menjadi “komoditas” ceramah bagi sebagian besar umat Islam yang mengundang mereka. Belum lagi bila pertobatan mereka dari “sejarah kelam dunia hitam” disinggung-singgung. Islam sebagai narasi sejarah Sayangnya, Rezza tidak menjelaskan mengapa ia memakai diksi “Tionghoa” di dalam bukunya ini. Karena itu, dalam review ini saya lebih merasa nikmat untuk memakai kata “China” saja. Selain itu, saya merasa buku ini meletakkan perbincangan ihwal keislaman-kechinaan-keindonesiaan ini sebagai sub-narasi. Seolah-olah hal itu merupakan keganjilan sejarah. Padahal, di China sendiri, Islam sudah masuk sejak tahun kelima pasca kenabian Muhammad SAW (615 M). Bersamaan dengan utusan lainnya yang dikirim Muhammad SAW ke berbagai belahan dunia, misalnya Ja’far ibn Abu Thalib ke Ethiopia/Habsyah. Mulai dari tahun 615-618 M, ada utusan yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke China, bernama Saad Ibnu Lubaid dan Yusuf di Kanton. Di buku ini juga disebutkan bahwa pada mulanya Islam disampaikan oleh kedua utusan itu kepada pedagang Arab yang telah lama bermukim di China. Tentu hal ini semakin menguatkan bahwa “China” bukanlah kosakata geografis-kultural yang asing di otak masyarakat Arab dan terlebih lagi Muhammad SAW. Apalagi antara China dan Arab telah ada hubungan perniagaan yang cukup mesra. Bahkan sejak tahun 500 SM, telah ada jalur transportasi yang menghubungkan China dan Arab (hal. 31-32). Bila narasi ini dibaca oleh Rezza, tentu permasalahan keislaman orang China ini tidak lagi dianggap sebagai upaya sekelompok manusia sub-minoritas untuk meresinifikasi kultural atau “berkebudayaan China/berchina-chinaan kembali”. Narasi demikian memang akan sangat tepat ditembakkan bila jangkauan periode analisisnya dikaitkan dengan situasi politik yang diderita oleh kaum China itu sejak Orde Lama hingga Orde Baru sebagaimana diasumsikannya di sini. Tapi ia tidak bisa untuk dipakai sebagai narasi tandingan atas sejarah nusantara yang sebagian besar telah rusak akibat kolonialisme. Saya katakan “rusak”, karena fakta keislaman dan keindonesiaan China hingga saat ini masih dibaca sebagai keanehan. Sejarah kechinaan-keislaman-keindonesiaan cenderung dikonstruksi secara salah oleh kaum kolonial. Yang menarik adalah catatan yang ditulis oleh F. De Haan (1935), bahwa orang China yang beragama Islam itu menurut kodratnya bukanlah orang-orang China yang paling utama, oleh karena yang menjadi sebab-musabab mereka masuk Islam pada umumnya karena mereka ingin menghindari ‘uang konde’. Sehingga dengan cara masuk Islam mereka akan terbebas dari pajak ‘uang konde’ (Budiman, 1979:34). Konstruksi kolonial ini ternyata berpengaruh pada realitas sehari-hari sebagaimana ditemukan oleh Rezza. Hal ini dapat dilhat dari komentar warga Yogyakarta yang merasa heran tatkala mereka melihat ada orang China ikut pengajian, berjilbab, dan berislam bersama mereka (hal. 128). Selain itu, mereka juga menempatkan orang China, bersama dengan orang Jawa sebagai dua pihak yang sama-sama belajar Islam. Berbanding terbalik dengan orang Arab dan seluruh keturunannya yang dianggap sebagai moyangnya Islam. Padahal, secara historis, jejaring keislaman tiga etnis dan bahkan barangkali seluruh etnis di dunia tak perlu dilebih-kurangkan. Masing-masing sama-sama berislam sejak dari moyangnya. Bilapun harus ditimbang, timbangan itu amat relatif. Harus diletakkan dalam kerangka letak geografis masing-masing. Maka murni dan tidaknya keislaman seseorang atau suatu kaum, tak dapat dinilai. Di Yogyakarta sendiri, ada seorang tokoh popular, yaitu Tan Jin Sing atau Tumenggung Secodiningrat (1760-1831). Dia menguasai bahasa Belanda dan Inggris, mampu membaca dan menulis bahasa Jawa-sankrit. Awalnya menjadi Kapiten di Kedu (1793), kemudian di Yogyakarta (1802) dan akhirnya diangkat menjadi Bupati Yogyakarta Tahun 1813 karena dianggap berjasa dalam membantu Sultan Hamengku Buwono III naik tahta dan berkomunikasi dengan pihak Inggris. Menariknya adalah ketika Tan Jin Sing hendak diangkat menjadi Bupati, dia meminta saran kepada saudara sepupunya, Kyai Tumenggung Reksonegoro II mengenai nama baru atau gelar yang akan dipakai. Tumenggung Reksonegoro II adalah putra dari Reksonegoro I alias Oei Tek Biauw, adik yang ketiga dari Oei Tek Liong. Oei Tek Biauw telah memeluk Islam dan menjadi ulama. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Bupati Semarang. Kemudian ditarik oleh Sultan HB I menjadi penasehat bidang keagamaan dan kerohanian kesultanan, termasuk menjadi pimpinan dalam upacara adat seperti perayaan Gerebeg. Setelah meninggal jabatan Reksonegoro I dilimpahkan kepada anaknya. Selain nama baru, ternyata suami istri Reksonegoro II juga menyarankan Jin Sing untuk memeluk Islam. Dengan alasan bahwa kebanyakan bangsawan Jawa adalah muslim. Di samping itu, Reksonegoro juga menceritakan tentang tokoh Laksamana Cheng Ho sebagai penguat bahwa orang Tionghoa di negeri leluhurnya juga banyak yang muslim. Akhirnya setelah kurang lebih empat bulan belajar Islam pada Reksonegoro II, Tan Jin Sing beserta istri dan anaknya mengucapkan dua kalimat syahadat (lihat Werdoyo, 1990: 64). Dari kisah ini dapat ditebak, bahwa kechinaan-keislaman-keindonesiaan bukan merupakan sesuatu yang aneh. Ia menjadi aneh karena faktor sejarah dan penyusunan sejarah itu sendiri bermasalah alias ditulis dengan suasana ketidakjujuran. Karena itu, mari membongkar dan menulis-ulang sejarah kita. Semoga buku ini cukup kuat untuk mengatarkan kita ke arah sana. Amin.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI