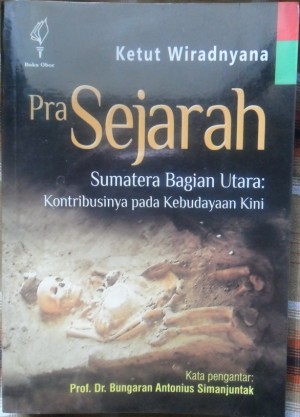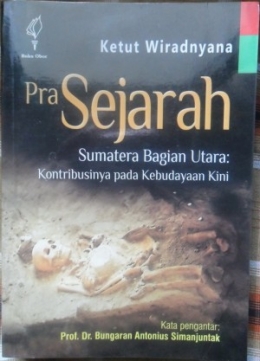Judul Buku : Prasejarah Sumatera Bagian Utara: Kontribusinya pada Kebudayaan Kini
Penulis : Ketut Wiradnyana
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Cetakan : Pertama, September 2011
Isi : xvii + 318 halaman
ISBN : 978-979-461-793-9
Harga : Rp. 57.000,-
Era modern sering dikatakan sebagai masa dimulainya kontak budaya antar berbagai wangsa. Tapi di Indonesia peristiwa kultural itu telah terjadi secara massif sejak era prasejarah. Itulah yang dikatakan oleh penulis buku ini, Ketut Wiradnyana. Argumen opini itu ia dasarkan pada hasil “dialognya” dengan berbagai situs, artefak, fosil, benda kuno, serta aneka peninggalan arkeologis di Sumatera bagian Utara. Sebagai pengantar perbincangan yang lebih serius, di bagian awal buku ini ia menyajikan uraian tentang eksistensi budaya Hoabinh di Indonesia.
Budaya Hoabinh adalah budaya manusia di era prasejarah. Ia muncul sejak 18.000 tahun lalu di Vietnam. Ciri termencoloknya ditandai oleh alat batu kerakal yang khas yang satu atau dua sisi permukaannya diserpih (hal. 18-19). Jejak-jejaknya berupa situs arkeologis didominasi oleh bukit kerang/kitchen midden yang banyak tersebar di Sumatera bagian Utara, terutama di kawasan pesisir Timurnya. Adapun ketinggian bukit tersebut mencapai sekitar 4-5 meter di atas permukaan tanah dan berkisar 4-10 meter di bawah permukaan tanah (hal. 21).
Rumusan interaktif
Jika ditinjau dari teknologi serta morfologi alat batunya, budaya Hoabinh masuk ke Indonesia pada masa Mesolitik. Pentarikhan budaya yang perekonomiannya ditandai oleh perburuan dan pengonsumsian biota laut, payau, tawar, dan darat ini ditaksir antara 10.000 sampai 6000 tahun lalu (hal. 62). Budaya inilah yang kelak ikut memperanakkan pusparagam karakteristik kultural wangsa nusantara prasejarah, terutama yang mendiami jazirah Sumatera bagian Utara. Sejumlah indikasinya antara lain tampak dalam beberapa aspek kehidupan.
Pertama, budaya-estetika megalitik. Aspek ini dapat dilihat dari banyaknya wadah kubur yang terbuat dari bahan batu tufan, breksi, batu pasir, dan andesit yang terdapat di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Hal serupa juga dapat ditemukan di Sulawesi dan sekitarnya. Sementara seni patung, produksi gerabah, dan bangunan monumental seperti candi khususnya di Jawa, dapat dicermati sebagai bukti budaya-estetika megalitik terkonkrit yang bisa disaksikan di zaman modern ini.
Kedua, nalar adaptatif-kreatif. Di telatah asalnya habitat budaya Hoabinh adalah kawasan pesisir pantai. Tapi ketika masuk ke nusantara, ia diadaptasi secara kreatif oleh orang-orang setempat. Sehingga ia berbiak tak hanya di pesisir, tapi juga di pedalaman. Tak heran bila ada cukup banyak situs Hoabinh di Sumatera bagian Utara. Baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Misalnya situs Gua Kampret yang berada di lereng Bukit Barisan, Desa Bukit Lawang, Bahorok, Langkat, Sumatera Utara. Ada juga situs Bukit Kerang di Desa Binjai, Seruwai, Aceh Timur dan masih banyak lagi.
Ketiga, tata-tertib sosial. Saat itu pengusung budaya Hoabinh di Indonesia telah mengenal hukum dan regulasi sosial. Ada kesepakatan konstitutif di antara mereka agar kaum wanita tetap berada di rumah mengurus anak sambil mengolah lahan selagi kaum pria pergi berburu atau melaut. Kiranya inilah asal-mula sistem pembagian kerja antara pria dan wanita yang hingga kini melanggeng hampir di seluruh keluarga Indonesia. Lagipula aspek legalisme ini menyimbolkan betapa gen harmoni dan keberadaban telah menyumsum di dalam diri manusia Indonesia prasejarah.
Selain tiga hal di atas, masih ada lagi pasal kultural lain yang terkena percikan budaya prasejarah. Mulai dari era Hoabinh hingga pasca Hoabinh. Wiradnyana memerinci hal itu di bagian keempat; Pengaruh Budaya Prasejarah Terhadap Budaya Etnis (hal. 197-276). Narasi terpentingnya adalah bahwa sebagian besar budaya yang dimuliakan hari ini merupakan rumusan interaktif dari proses pergaulan dengan bermacam-ragam wangsa dunia sejak era prasejarah. Bila tidak, mana mungkin 75% temuan arkeologis dunia bisa ada di Indonesia. Situs bukit kerang pun pasti mustahil bisa terdapat di Vietnam, Indonesia, China Selatan, dan sebagian Asia Tenggara.
Dengan kata lain, nusantara sejak jauh hari merupakan lahan subur bagi kontak budaya global. Sayangnya, tak semua pihak menyadari apa yang disebut oleh antropolog Bungaran Antonius Simanjuntak dalam kata pengantarnya sebagai petunjuk eksistensial dalam pergaulan antarbangsa ini (hal. xvii). Bahkan agaknya ia masih jarang ditempatkan sebagai basis epistemologis dalam diskursus multikulturalisme maupun pluralisme yang saat ini tengah giat dikembangkan di Indonesia. Wajar bila kian hari bangsa ini lebih sering menonton kontes olah bibir daripada olah karya.
Religi atau kosmologi?
Ada beberapa gejala distorsi dalam uraian panjang Wiradnyana yang mesti dipertikaikan. Di sini ia menganggap bahwa religi orang Hoabinh di Indonesia saat itu bercorak animisme-dinamisme. Wujudnya berupa penghormatan mereka pada orang mati dan kepercayaan mereka pada kehidupan setelah kematian (hal. 106-106). Tesis tersebut ia yakini dari temuan hematite atau batu merah di dalam kuburan kuno. Tapi apakah penghormatan pada orang mati dan kepercayaan pada kehidupan setelah kematian merupakan ciri animisme-dinamisme?
Inilah kerikil yang agaknya tak dinetra oleh peneliti di Balai Arkeologi Medan ini. Karakteristik kultural yang lestari hingga kini sebagaimana disebutkan di atas jelas-jelas merupakan bukti rasionalitas dan ketercerahan manusia Indonesia parasjarah itu. Jadi tak mungkin mereka mengamalkan syariat animistik-dinamistik. Artinya pasti ada sistem religi khas di masa itu yang tak senaif animisme-dinamisme. Bisa jadi bukti arkeologis yang ditemukan Wiradnyana sebenarnya sedang tak melafalkan sistem religi, akan tetapi sistem kosmologi.
Lagipula bau religi sulit diendus dari fosil-fosil. Ia adalah perkara batin. Bila Wiradnyana ngotot untuk tetap mengupasnya, setidaknya ia dapat mensejiwakan data arkeologisnya itu dengan mitos-mitos. Seperti yang dikerjakan oleh JA Sonjaya dalam novel etnografisnya, Manusia Langit (Kompas, 2010). Di sana Sonjaya mewicarakan budaya dan religi orang Nias dengan bersandar pada data arkeologis yang diadon dengan hasil studi mitos diturunkannya manusia dari langit ke desa Banuaha, Nias. Sayang sekali Wiradnyana tak melangkah jauh ke sana.
Distorsi inipun ‘diperparah’ oleh penyakit editorial bukunya. Terdapat cukup banyak kata yang kehilangan satu-dua hurufnya. Ditambah lagi ada banyak keamburadulan peletakan kata sambung di sana-sini. Beberapa pengulangan paragraf, misalnya paragraf di halaman 19 dan 63 yang tertulis lagi secara utuh di halaman 113 dan 67, cukup pas menyempurnakan keparahan itu. Semoga keyakinan pembaca pada validitas isi buku yang awalnya masih berupa naskah laporan penelitian ini tak menyusut karenanya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI